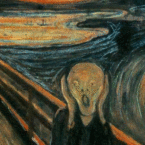Kala itu saya tengah berada dalam perjalanan antar kota dengan seorang kawan. Karena obrolan telah habis, kawan saya membaca salah satu buku dari penulis kondang asal Brazil, Paulo Coelho. Di tengah bacaan ia bertanya karya Coelho mana yang saya sukai, dengan singkat saya jawab: tidak satupun. Mendengar jawaban tersebut sejenak ia keliatan kecewa lalu melanjutkan bacaannya. Saya lalu tersadar, jangan-jangan ia mengira bahwa saya menanggap karya Coelho tidak layak dibaca (karena tidak dipungkiri saya punya kebiasaan sinis dalam memandang sebuah buku sastra yang dengan seenaknya akan saya pilah antara mana yang bagus mana yang tidak). Tapi sungguh, saat itu saya tidak sedang ingin berpandangan sinis. Beberapa karya Coelho sangat layak dibaca, hanya saja ketika membacanya saya sudah kelewat usia. Ambil contoh kawan saya: ia berusia duapuluhan–usia dimana cita-cita midas dan kisah-kisah asing masih memukau pikiran. Saat seusianya, saya sibuk dengan cerita surealis Danarto (sehingga dalam benak saya, cerita-cerita Danartolah yang memberi pijakan dasar pencarian ideal–bukan Coelho). Kisah populer Coelho baru saya baca pada usia sekitar akhir duapuluhan. Mungkin karena masa pencarian ideal sudah berakhir (berganti dengan masa “pencarian tidak ideal”), maka kisah-kisah Coelho tidak lagi menggugah hati saya. Dari kejadian itulah–perbincangan singkat tentang Coelho di sebuah kereta–, saya teringat pada teori sastra yang menyatakan bahwa melekatnya sebuah kisah dalam benak seseorang memiliki resonansi dengan usia. Jika dipikir-pikir, teori tersebut ada benarnya juga. Sebagai contoh, saya tidak yakin seorang paruh baya akan girang ketika membaca sosok Holden Caulfield dalam Catcher in the Rye karya J.D Salinger layaknya saya ketika menemukan buku tersebut di usia belasan. Atau seorang remaja sekolah menengah yang mengamini kegelisahan seorang Hamlet, adalah remaja yang mencuri start dan tua sebelum waktunya. Resonansi inilah yang kemudian saya rasakan ketika membaca ulang Notes from Underground Novel Rusia karya Fyodor Dostoevsky – bahwa seseorang butuh tingkat kegetiran tertentu untuk dapat memahami ceracau absurd sang orang bawah tanah (the underground man).
Dulu sekali, saya lupa tepatnya kapan, Notes from Underground pernah saya baca sekilas namun saya kemudian beralih pada tulisan Dostoevsky lain yang berjudul Crime and Punishment dan berlanjut pada karya lain berjudul The Idiot. Kedua karya tersebut, walaupun memiliki kedalaman khas literatur Rusia klasik yang sulit ada bandingannya, masih dapat dipahami melalui kacamata seorang mahasiswa politik yang terbiasa pada pola sebab akibat (plus agak gaya sedikit: psikoanalisis dan justifikasi kejahatan). Relasi sosial canggung Nikolaevisch Myshkin atau distorsi nilai moral Romanovich Raskolnikov, masih jauh lebih “terbaca” dibanding ceracau the underground man. Gaya absurd Dostoevsky pada bagian pertama Notes from Underground juga adalah tantangan tersendiri–menambah daftar panjang alasan bagi saya untuk menunda pembacaan. Setelah lebih dari sepuluh tahun, saya memberanikan diri untuk kembali membaca buku tipis nan ajaib tersebut. Kali ini saya bertekad untuk menamatkannya–mungkin karena usia yang tepat (entah usia fisik ataupun atau usia kesadaran)–kelakar tajam khas Dostoevsky kini terbaca dengan jelas. Maka maklumlah saya mengapa the underground man disandingkan setara dengan tokoh sastra lain seperti Hamlet, Don Juan, Don Quixote dan juga Faust. Jajaran tokoh ini dianggap sebagai arketipe yang menjadi dasar alusi psikologis dalam penokohan sastra. Notes from Underground yang ditulis pada tahun 1864 disebut-sebut sebagai salah satu karya sastra modern pertama. Sastra modern disini mengacu pada upaya penelusuran relung pemikiran sang tokoh dalam menghadapi realita. Memasuki abad 20, gaya ini semakin populer melalui karya-karya Hermann Hesse, Bertolt Brecht, Samuel Beckett dan penyair T.S Eliot. Alienasi sebagai efek samping modernitas terjangkit dimana-mana (maksudnya dalam karya-karya penulis diatas). Namun, penokohan the underground man yang tanpa nama dan tanpa identitas, menjadikan alienasi hadir diantara kita. Karena the underground man bisa siapa saja.
Pembacaan lengkap Notes from Underground menghantarkan saya pada simpulan: pantas saja dulu saya kesulitan membacanya. Karya ini merupakan karya pertama Dostoevsky setelah bebas dari hukuman mati dan pengasingannya di Siberia. Disini ia memberikan kritik pada beberapa kunci pemikiran Eropa yang tengah berkembang saat itu (Notes from Underground diterbitkan pada tahun 1864), diantaranya: konsep self-consciousness dari Hegel, utilitarianisme praktis, keangkuhan kapitalisme (melalui simbolisasi istana kristal), aliran filsafat romantis dari Perancis dan Jerman (bagian ketika Dostoevsky membandingkan romantisme Perancis, Jerman dan Rusia, adalah salah satu alusi terlucu yang pernah saya baca), dan juga menyasar fungsi agama dan norma dalam tatanan sosial. Tanpa memahami peta pemikiran yang menjadi pijakan kritik Dostoevsky, sindiran the underground man akan kehilangan sisi sarkasmenya. Kritik tersebut, dicampur dalam dosis yang agak berlebihan dengan pesimisme Arthur Schopenhauer dan eksistensialisme Soren Kierkegaard yang berkembang di awal abad 19, menjadikan Notes from Underground sebagai salah satu novel “penghancuran diri” paling terkenal dalam sejarah. Cerita yang ditulis oleh the underground man akan dibangun dalam kerangka (yang sangat meyakinkan) untuk dihancurkan (olehnya dirinya sendiri) kemudian. Dan jangan lupa, St. Petersburg adalah ibukota kemuraman di senatero dunia (dalam kata-kata Dostoevsky sendiri) yang memberikan pengaruh kepada gagasan-gagasan getir the underground man–sebuah kota yang “sublim dan indah”, dengan lumpur yang semakin menghisap aku kedalamnya (Notes from Underground, 10).
Jika pada bagian pertama kita dihadapkan pada monolog absurd, maka pada kedua kita dihadapkan pada relasi absurd. Dalam pandangan saya, bagian ini lebih getir karena satu hal: bahwa ternyata untuk melakukan penghancuran diri (dalam konteks relasi sosial), seseorang membutuhkan niat dan keberanian (juga jangan lupa kenaifan ala prajurit di garis depan yang pada satu titik bisa menjadi penyelamat ketika keberanian tidak kita miliki). Pada bagian dua, the underground man memberikan tantangan bagi para pembaca dalam sejauh mana seseorang mampu menanggung konsekuensi dari kekacauan yang ia buat sendiri. Salah satu adegan adalah ketika sang narator mengundang dirinya sendiri dalam sebuah perjamuan makan, padahal ia tahu betul akan konsekuensi yang akan terjadi. Banyak dari analisis sastra menyatakan bahwa sosok the underground man adalah seorang asosial bahkan outcast. Namun, tanpa disadari bahkan kalangan asosial pun diolok-olok oleh sosok ini. Bayangkan saja, pada kenyataannya menjadi outcast bagi seorang adalah penyendiri adalah sebuah kenikmatan–tapi the underground man melemparkan kenikmatan tersebut dan berjibaku dengan musuh kasat mata yang bernama harga diri. Melalui relasi sosial absurd, the underground man seakan-akan menyatakan bahwa dirinya tidak memihak pada sisi manapun. Ia (mungkin merasa dirinya) lebih agung dari pada para anti-sosial di seluruh dunia. Atau ketika memberi harapan pada seorang pelacur yang ditemuinya, bukan berarti ia memihak pada sisi kejam dunia (karena semua kata-kata yang diucapkannya hanya berupa kutipan naif dan tidak untuk dipegang secara nyata). Pada akhirnya, kita harus menyadari bahwa the underground man adalah juga sindiran bagi silopsisme yang melanda dunia. Ungkapannya adalah jalan satu arah tanpa ada upaya dialog sedikitpun: “Dia itu bodoh, tidak diragukan lagi. Tapi mungkin semua manusia normal memang harus bodoh” (Notes from Underground, 13). Saya, adalah juga yang terkadang berpikiran demikian.
Ketika selesai membaca novel ini, saya seakan menemukan sosok antihero baru layaknya saya menemu Holden Caulfiled atan Mark Renton ketika remaja. Tokoh the underground man mampu beresonansi dengan realita dan relung pikir para pembaca (dengan kegetiran dan sudut pandangnya yang agak sedikit mengkhawatirkan, sebetulnya). Dalam segi resonansi, John Stewart (Dostoevsky and the Novel as Philosophy, 2016) menariknya lebih jauh dari sekedar subjektifitas pembaca. Menurutnya Notes from Underground berpengaruh bukan hanya pada karya sastra, tapi juga pada aliran filsafat tradisi existentialist. Ungkapnya: He treated genuine philosophical issues concerning the nature of the self, human freedom and the nature of modernity. Kutipan dari Stewart ini menjadi penting, bukan karena penegasan kualitas, tapi karena siapapun akan kesulitan membuat sebuah ulasan tentang karya Dostoevsky tanpa ada bacaan sandingan. Dalam memahami Notes from Underground saja dibutuhkan pemahaman akan kerangka kontekstual berbagai pemikiran yang mendasari penulisan karya tersebut. Tapi, interpretasi (sok intelek tersebut) hanya satu sisi. Jika pun kita membaca karakter dalam Notes from Underground seperti seseorang memainkan tuts piano (dengan semata-mata bertujuan agar tuts berbunyi, tanpa harus tahu piano tersebut terbuat dari apa dan untuk apa), rasanya sah-sah juga. Toh menurut sang narator, manusia tidak lebih dari tuts piano.

kontak via editor@antimateri.com