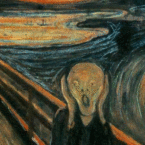Selaku seorang pembaca pemula yang sedang mencoba berkutat pada karya-karya sastra Amerika, saya berterus terang bila sensasi membaca beberapa karangan Mark Twain begitu menyegarkan. Apalagi ketika berhadapan dengan magnum opus-nya, The Adventure of Huckleberry Finn. Novel realis yang ditulis menjelang akhir abad ke-19 ini berhasil menggugah seluruh perhatian saya sejak lembar pertama. Hal itu barangkali wajar mengingat karya ketiga Mark Twain ini sangat fenomenal. Kritikus sastra seperti H. L. Mencken, Lionel Trilling, dan penyair pemenang Nobel Sastra T. S. Eliot menyebutnya sebagai masterpiece; teks sastra asli Amerika pertama yang benar-benar orisinil. Ernest Hemingway melalui Green Hills of Africa (1935) pun pernah melemparkan pernyataan bahwa seluruh sastra Amerika berasal dari satu buku hebat, The Adventure of Huckleberry Finn.
Ini tentu bukan suatu bentuk pujian semata, melainkan juga bukti yang mengindikasikan jika novel tersebut memiliki posisi tersendiri dalam bentangan sejarah kesusastraan Amerika. Meski begitu, uniknya Mark Twain hanya menganggapnya sebagai buku fiksi biasa. Pada tahun 1908, ia bahkan menegaskan kalau The Adventure of Huckleberry Finn masih berada di bawah Personal Recollection of Joan of Arc (1896) dan The Prince and the Pauper (1881) dalam daftar karangan favorit yang ia buat.
Melanjutkan cerita gelandangan liar bernama Huckleberry Finn yang sebelumnya muncul di balik bayang-bayang ketengikan dan kecerdikan Thomas Sawyer di The Adventure of Tom Sawyer (1876), novel ini secara mendasar saya pandang juga sebagai lakon tentang seorang anak lelaki kulit putih yang membantu seorang budak kulit hitam kabur dari perbudakan di daerah Selatan Amerika sebelum terjadinya Perang Saudara. Melaluinya, Twain dengan apik mengeksplorasi beberapa tema universal seperti kebebasan dan perbudakan, keserakahan, hubungan ras, hingga kekerasan. Walau seringkali digolongkan sebagai buku cerita anak-anak atau remaja labil yang baru tumbuh dewasa, nyatanya karya ini menyimpan kisah-kisah serius mengenai implikasi kemanusiaan dalam perjalanan manusia; suatu substansi misterius yang cukup ironis lantaran senantiasa digemakan sekaligus dihancurkan sepanjang zaman.
Olok-olokan terhadap Masyarakat Beradab
Ketika membaca halaman awal, kita akan mendapati bila Huck Finn memperkenalkan dirinya sebagai seorang narator. Dengan menggunakan seorang bocah tidak berpendidikan, Mark Twain jelas ingin bertutur melalui mata seorang pengamat yang polos sekaligus bodoh. Buktinya, kala menyaksikan banyak kekerasan, kejahatan, dan hipokrisi yang terjadi dalam masyarakat, Mark Twain menggambarkan Huck hanya banyak memberikan deskripsi tanpa turut berusaha untuk mengevaluasi atau memberikan suatu penilaian mendasar. Seolah peristiwa yang sedang dilihat itu terjadi di luar atau sama sekali tidak berkaitan dengan diri Huck.
Bila membaca terlebih dahulu The Adventure of Tom Sawyer, kita dijelaskan mengenai sosok asli Huck Finn ini. Hidupnya penuh dengan kebebasan. Ia lebih suka tidur di dalam sebuah tong alih-alih kasur yang empuk nan hangat. Ketika ia diadopsi oleh seorang Janda kaya dan diperkenalkan kepada kehidupan beradab: berpakaian rapi, makan dengan sendok dan garpu, pergi ke gereja atau sekadar berbicara dengan sopan, Huck malah merasa menderita. “Ke mana pun ia berpaling,” tulis Twain saat menjelaskan kondisi Huck, “belenggu dan tali peradaban mengungkungnya, mengikat erat-erat”.
Meski sekilas terlihat aneh, justru karakter Huck Finn merupakan gambaran kuat mengenai seseorang yang hidupnya belum dikotori hiruk pikuk peradaban. Dalam ukuran masyarakat beradab, Ia bisa dibilang sebagai anak yang bodoh. Namun, kebodohan itu telah menjadikannya sosok yang memiliki kejujuran alami. Saking alaminya, Huck digambarkan banyak melakukan tingkah yang barangkali berada di luar nalar masyarakat pada umumnya. Dalam The Adventure of Huckleberry Finn, ia menolak mentah-mentah harta kekayaan bernominal ribuan dolar. Huck merasa tidak memerlukan kekayaan berupa uang lantaran kehidupan bohemiannya sudah lebih dari cukup. Ini jelas merupakan sebuah sindiran halus terhadap kehidupan beradab yang segala seluk beluknya justru diukur oleh buah-buah material bernama uang, yang nyatanya lebih banyak mengungkung ketimbang membebaskan sisi kemanusiaan manusia.
Selain itu, cerita keluguan yang paling berkesan dan banyak dibicarakan orang adalah ketika Huck berkata bila ia lebih memilih masuk neraka ketimbang harus menulis sebuah surat yang memberitahukan keberadaan Jim, budak kulit hitam yang kabur, kepada pemiliknya. Dalam situasi ini, Huck merasa tertekan sekaligus bimbang. Nuraninya mengalami dilema mendalam: Huck yang nakal berniat menjadi seorang anak baik dan soleh, akan tetapi bila ingin demikian, pikirnya ia harus menyerahkan Jim untuk kembali menjadi seorang budak. Setelah mengalami pertarungan batin yang sangat melelahkan, Huck pada akhirnya merobek surat yang berisi keberadaan Jim dan berkata “Baiklah kalau begitu, aku akan pergi masuk neraka”.
Peristiwa ini bagi saya sendiri cukup berkesan dan membuat hati saya bergetar. Sulit rasanya membayangkan menjadi seorang bocah seperti Huck pada zaman di mana perbudakan dilegitimasi oleh ajaran-ajaran agama. Melalui Huck, Mark Twain menyuarakan dengan lantang sikapnya yang mengutuk perbudakan. Ia mengolok-olok konvensi sosial masyarakat umum yang menganggap perbudakan sebagai sesuatu yang sah dan tidak berdosa secara religius; legitimasi terhadap keberadaan tingkatan tertentu dalam wilayah rasial yang harus dijalankan. Dengan keluar dari tradisi perbudakan, Huck sekaligus Twain barang tentu ingin melampaui keadaan masyarakat beradab yang justru buta terhadap kemanusiaan. Meski itu berarti sama saja dengan menceburkan diri ke dalam panasnya api neraka secara sengaja.
Ungkapan lain Mark Twain berupa olok-olokan menohok terhadap masyarakat juga terekam jelas ketika Huck dan Jim membicarakan para raja; penguasa; atau pemimpin. Walau dalam banyak momen Huck tampil hanya sebagai narator yang menjelaskan semua kejadian tanpa membawa seturut argumen yang didasarkan moralitas, akan tetapi kala berbincang hangat dengan Jim mengenai raja, Huck mengemuka dengan banyak bicara seakan sedang menunjukkan bila dirinya sangat benci terhadap penguasa. “Alangkah senangnya bila kita berada di suatu negara yang sama sekali tak punya raja,” demikian kesimpulan Huck mengakhiri perbincangan tersebut dengan Jim.
~~~
Tapi adalah salah besar jika mengatakan Mark Twain sepenuhnya antiotoritas. Walau dengan berani ia mengoyak mitos-mitos peradaban yang mengekang, namun ia tetap bukan tipikal sastrawan seperti Alex Berkman, Oscar Wilde, atau Le Guin yang tampil lebih subversif lewat karya-karyanya. Karyanya yang sedang dibahas di sini, The Adventure of Huckleberry Finn, merupakan dramatisasi atas keinginan ideal Twain akan komunitas yang harmonis: “Sebab di tempat sekecil rakit itu semua orang harus merasa senang dan bersahabat terhadap kawan”. Seperti kapal Pequod yang muncul di Moby Dick-nya Henry Melville, rakit yang ditumpangi oleh Huck dan Jim itu tenggelam, dan begitu juga dengan komunitas harmonis. Dunia rakit yang menjadi representasi komunitas yang sederhana dan murni pada akhirnya ditenggelamkan oleh kapal uap. Simbol dari betapa tidak terelakkannya kemajuan peradaban.
Sumber Gambar Muka: Project Gutenberg
Bacaan Lanjutan:
Messent, Peter. 2007. The Cambridge Introduction to Mark Twain. Cambridge University Press.
Rasmussen, R. Kent. 2007. Critical Companion to Mark Twain: A Literary Reference to His Life and Work. Facts on File.
VanSpanckeren, Kathryn. Garis Besar Kesusastraan Amerika. Terj. Sumantri AR., Eddy Saputra, Eliza Rahmi. Diterbitkan oleh Lembaga Penerangan Amerika Serikat.

Mahasiswa prodi S1 Sosiologi Universitas Jenderal Soedirman
Pembaca dan Penikmat Sastra