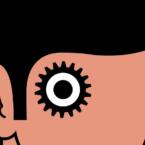Alangkah lucunya bagaimana kanal ingatan mampu membuat seseorang merangkai sebuah kolase atas berbagai potongan kejadian atau cerita – dan berakhir dengan sesuatu yang sama sekali sulit dibayangkan. Demikian pula proses terbentuknya tulisan ini: melalui jalan panjang penuh persimpangan, maka hadirlah sebuah kolase dengan struktur waktu tumpang tindih yang tidak karuan. Pada mulanya tidak pernah terbersit untuk menulis sesuatu tentang William Shakespeare. Alasannya tentu bukan karena ketidaktertarikan (saya penggemar Shakespeare nomor satu di kampung saya, saya rasa), tapi karena saya sama sekali tidak memiliki kapasitas untuk menulis apapun tentang dramawan paling terkenal dalam dunia sastra tersebut. Sampai pada suatu sore yang agak mendung, ketika tengah menunggu seorang kawan di sebuah cafe pinggiran kota Yogya, terdengarlah lamat-lamat lagu berjudul “Dream Brother” karya Jeff Buckley. Tentu lagu ini jauh api dari panggang ketika dibandingkan dengan karya Shakespeare, tidak nyambung sama sekali. Namun, lagu yang sore itu diputar berulang-ulang oleh sang pemilik cafe, mengantarkan saya pada objek yang tidak biasa: death by drowning. Kematian Jeff Buckey adalah sebuah trauma massal yang ditanggung oleh siapa saja yang menghabiskan masa remaja di era 1990an. Pada malam tanggal 29 Mei 1997, ia dinyatakan menghilang ketika tengah berenang di tempat favoritnya, Wolf River Harbor, Missisipi. Jasadnya baru diketemukan lima hari kemudian, dan seperti kebanyakan kasus kematian musisi besar pada umumnya, berbagai teori bermunculan tentang bagaimana sang musisi tenggelam. Bunuh diri adalah salah satunya, namun ketika melihat berbagai fitur wawancara dan dokumentasi tentang sang musisi, Jeff Buckley sama sekali tidak terlihat memiliki gelagat Alain Leroy dalam film Le Feu Follet garapan Loius Malle – sesak, tidak berdaya dan merindukan kematian. Lalu dari mana kegetiran dalam Grace (satu-satunya album yang ia selesaikan) dapat begitu menghujam? Menjawab pertanyaan ini, ia mengeluarkan catatan hariannya: “i put my pain in my pocket, not in my heart”. Kata-kata ini membuatnya diingat sebagai salah satu jenius musik – yang sayangnya – mati tenggelam ketika karirnya baru menapaki puncak.
Ingatan saya kemudian melompat pada jenius lain yang juga mengalami tragedi sama, Virgina Woolf. Sama halnya seperti Jeff Buckley, Virgina Woolf terpisah secara temporal dengan karya-karya Shakespeare – walau sebagai seorang penulis dan essayist, ia menempatkan karya sang dramawan pada tempatnya tersendiri: di bagian istimewa rak buku juga sebagai pengaruh besar dalam novel-novelnya. Seperti halnya Jeff Buckley pula, Virginia mati tenggelam – dengan menaruh batu di kantung jaketnya, ia membiarkan dirinya tenggelam di Sungai Ouse. Bedanya, jika kematian Jeff adalah kecelakaan, maka bagi Virginia, tenggelam adalah upayanya untuk menghindari kegilaan permanen. Ketika membaca berbagai biografi sang penulis, terdapat bertumpuk-tumpuk data tentang diagnosa depresif yang dialaminya. Ini tentu bukan hal yang baru dalam sejarah literatur, karena berkah kejeniusan dan beban mental emosional seringkali merupakan dua sisi dari koin yang sama. Kita melihat banyak contoh tragis lain – Yukio Mishima, Ernest Hemingway, Jaques Rigaut, adalah beberapa diantaranya. Mereka adalah pasukan romantisme radikal yang menghadapi kehidupan dengan kesadaran penuh – tanpa obat penenang ataupun hiburan pengalih perhatian yang bisa membuat manusia bertahan menghadapi kesia-siaan. Begitu pula dengan Virginia – ia dikenal sebagai pilar sastra modern Inggris karena gagasannya tentang eksposisi emosi internal yang kerap dianggap tidak substansial (melalui ungkapan terkenalnya “on the outskirts of every agony sits some observant fellow who points”, ia mengangkat tema keseharian seperti penderitaan disebabkan oleh penyakit yang sebelumnya jarang diangkat dalam karya sastra). Bersama Marcel Proust dan James Joyce, ketiganya dipandang sebagai peletak dasar sastra modern – dengan gaya penulisan yang mengubah wajah sastra menjadi begitu personal. Melalui dobrakan tersebut, nama Virginia Woolf menjadi epitome bagi para penulis, khususnya penulis perempuan setelahnya. Namun ia harus membayarnya dengan diagnosa sakit jiwa dan keputusannya untuk mati tenggelam.
Kisah tragis Virginia Woolflah yang membuat saya, mau tidak mau, harus berhadapan dengan kasus mati tenggelam yang paling terkenal: Ophelia. Ia adalah seorang putri dari bangsawan Denmark, Polonius, yang digadang-gadang menjadi calon istri sang pangeran Denmark, Hamlet. Entah berapa lukisan telah dibuat untuk menggambarkan kematian tragisnya – bahkan dapat dikatakan bahwa tragedi kematian Ophelia adalah salah satu adegan drama Shakespeare yang paling banyak diabadikan kedalam lukisan. Bagaimana tidak – seorang gadis rupawan, nyaris tanpa cela, dalam kegilaan membiarkan dirinya direngkuh oleh kematian yang menanti dibawah pusaran. Tubuhnya lalu mengapung di permukaan, membekukan hati juga pandangan siapa saja yang melihat. Dan melalui tragedi Ophelia-lah saya memberanikan diri untuk mengakrabi karya sang dramawan. Ophelia memang bukan tokoh utama – bahkan dalam beberapa pembacaan, perannya hanya dibatasi sebagai gadis yang terobsesi kepada Hamlet dan menjadi gila ketika cintanya ditolak. Namun, rasanya agak sedikit mengecewakan jika Shakespeare dipahami sedemikian rupa – mengingat reputasinya sebagai master dalam kompleksitas, pasti terdapat berlapis pembacaan yang memberikan bobot lebih pada setiap drama gubahan Shakespeare. Dalam penokohan Hamlet sendiri, kematian ayahnya menjadi pemicu rentetan kegetiran yang berujung pada kematian Polonius (ayah dari Ophelia dan Laertes), pengusirannya dari Denmark, dan kematian Ophelia. Dan kita tahu, bahwa dalam drama Shakespeare, cerita tidak akan berakhir hingga lingkaran tragedi, tergambar secara penuh.
Tenggelamnya Ophelia pada Babak IV menyajikan sebuah akhir alternatif bagi pembalasan dendam. Ketika menyaksikan Hamlet, saya selalu memiliki anggapan bahwa kisah Ophelia adalah tragedi dalam tragedi – ia memiliki panggungnya sendiri, terisolasi dari realita kejam tanpa ampun yang hadir melalui penolakan Hamlet (melalui kalimat: “Get thee to a nunnery. Go, farewell.”) dan kematian ayahnya. Kegilaannya mencekam – sebagai langkah terakhir yang diambilnya dalam menghadapi tragedi di depan mata. Gambaran ini menjadi semakin jelas melalui pemaparan Peter Saccio dalam Hamlet in Action (1995, Shakespeare: The Word and the Action) yang menggambarkan bahwa terdapat tiga versi pembalasan dendam dalam tragedi ini: Hamlet, yang bergulat dengan nalurinya ketika ia bertekad membunuh pamannya sendiri. Laertes, yang menyerah pada kemarahan ketika mengetahui kematian ayahnya serta kegilaan adiknya. Dan Ophelia, yang mengubur rasa malu dan dendamnya dalam kegilaan. Ketiganya memiliki konsekuensinya masing-masing. Pergulatan dan keragu-raguan Hamlet menghantarkan pada kehadiran tragedi lain (kematian Polonius dan Ophelia), kemarahan Laertes menyajikan kematian yang membabi buta, sedangkan dendam Ophelia berujung pada kematian sunyinya yang menggema lebih nyaring dari ucapan terakhir Hamlet – the rest is silence. Gambaran ini memperkuat sebuah fakta, bahwa Ophelia yang tenggelam, menyajikan pemandangan yang lebih mengerikan dari adegan akhir duel antara Hamlet dan Laertes dimana kekerasan adalah nyata. Sedangkan pada kematian Ophelia, (juga pada kasus tenggelamnya Jeff Buckley dan Virginia Woolf) kematian menunggu dengan tenang: menyuguhkan kolase dingin yang sublim dan menghanyutkan.
There’s rosemary, that’s for remembrance. Pray you, love, remember. And there is pansies, that’s for thoughts.There’s fennel for you, and columbines. There’s rue for you, and here’s some for me. We may call it herb of grace o’ Sundays.…

kontak via editor@antimateri.com