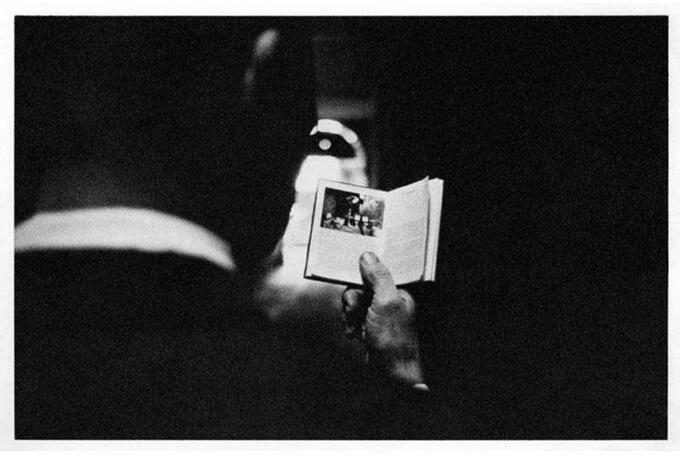(*Puisi bisu: puisi yang tidak menjelaskan dirinya secara gamblang; puisi yang kurang mampu dipahami pembaca)
Rumah-rumah Muumbi
I
dinding rumah-rumah muumbi pucat pasi
layaknya wajah seorang kerdil yang diseret keluar
lalu ditelanjangi untuk sekedar jadi tontonan
setelah keterhenyakkannya diabadikan,
dia menangis, lalu tertidur pulas di jalanan
II
dinding rumah-rumah muumbi pucat pasi
menutup dirinya dari siang juga dari malam
bahkan mengusir Zeus dan seisi dunia
dan lihatlah sekarang,
dia mulai membakar diri
ketakutan adalah membiarkannya mati,
tapi memberinya kehidupan adalah pergulatan
tanpa akhir.
III
rumah-rumah muumbi adalah rahim ibumu
dari kematiannya,
terkutuklah manusia yang semakin tidak memahami
bahasanya sendiri.
(Yogyakarta, 2013)
Puisi di atas merupakan salah satu puisi saya yang dipercaya oleh seorang kawan baik, Agung Prastyo, untuk melengkapi narasi dalam pameran fotonya sekitar dua tahun yang lalu. Saya berkesempatan menghadiri acara pembukaannya, yang bagi saya artinya: mencari hidangan, obrol sana-sini, lalu berdiri canggung di sudut ruangan menikmati suasana. Namun, beberapa hari yang lalu, ingatan tentang malam pembukaan pameran itu kembali menghampiri, yaitu ketika tersebar kabar bahwa di ujung timur nusantara, sebuah mushola yang tengah digunakan shalat ied, hangus dibakar massa. Pembakaran mushola ini mengingatkan saya pada sebuah pertanyaan pengunjung di pameran malam itu: “apa arti puisi ini?”, kala itu saya hanya menjawab sekenanya: “tentang manusia”, sebuah jawaban yang tentu tidak menjawab apa-apa. Dan jadilah ia puisi bisu – karena sang penulis terlalu malas untuk menjelaskan.
Namun, setelah bertahun-tahun membisu, ia (meminta) bersuara ketika sebuah tempat ibadah dibakar (–perhatian ini mengacu pada tempat ibadah agama manapun, bukan hanya mushola). Keterhenyakan ini bukan tanpa sebab, karena puisi di atas adalah rangkuman pemikiran yang mengendap selama saya membantu dalam pengajaran mata kuliah yang membahas tentang konflik identitas dan tantangan multikulturalisme – dengan konflik (identitas) agama sebagai salah satu kajiannya. Sedangkan frase Rumah-rumah mumbi saya ambil dari judul bab pembuka buku karya Harold Isaacs, Idols of the Tribe: Group Identity and Political Change. Kembali pada malam pembukaan pameran – untunglah pada waktu itu, sang penanya tidak mendesak saya untuk menjawab, karena jika saja ia bersikukuh, maka malam pembukaan pameran foto akan beralih menjadi ajang curhat seorang “warga negara” yang gundah gulana melihat kondisi bangsanya.
Secara definitif, rumah-rumah Muumbi adalah simbol persatuan masyarakat Kenya. Di Kenya terdapat sebuah upacara angkat sumpah yang dilakukan setiap tahun dengan tujuan meredam serta meredakan ketegangan antar suku. Dalam upacara tersebut, para perwakilan suku bersumpah: “Aku tidak akan meninggalkan Rumah Muumbi” (Isaacs, 1975: 2). Muumbi merupakan nama bagi leluhur mereka, dan rumahnya merupakan simbolisasi rahim, muasal semua suku yang ada di Kenya. Melalui sumpah kepada Rumah Muumbi, suku-suku di Kenya memberikan loyalitasnya pada para leluhur yang mempersatukan mereka. Namun sejalan dengan perkembangan entitas masyarakat modern (salah satunya melalui konteks “negara-bangsa” yang diterapkan paska dekolonialisasi), loyalitas berubah arah pada kepentingan politik praktis kenegaraan, yang dalam banyak segi mengorbankan persatuan antar suku – dan kini, Rumah-rumah Muumbi hanya menjadi dongeng semata.
Di Indonesia pun kita mengalami hal serupa. Walaupun kita, bangsa Indonesia, tidak dipersatukan melalui kesamaan leluhur, namun tidak ayal bahwa “Indonesia” berasal dari rahim yang sama – rahim yang dinamakan Multikulturalisme. Konsepsi tentang Indonesia diletakkan pada landasan tersebut, sehingga bagi Indonesia, perbedaan adalah asal-muasal. Namun dalam tumbuh kembangnya kebangsaaan, multikulturalisme tidak selamanya mendapatkan perhatian – bahkan cenderung direpresi melalui berbagai bentuk kebijakan: mulai dari kebijakan penggantian nama, pelarangan ritual keagamaan, hingga penguasaan elit politik oleh etnis tertentu juga pernah terjadi di Indonesia. Dalam menghadapi permasalahan ini, Soedjatmoko dalam tulisannya yang berjudul Menjelang Suatu Politik Kebudayaan, menyindir pemerintahan berkuasa saat itu yang melulu berbicara tentang “persatuan nasional” tanpa memahami esensi bahwa dalam persatuan terdapat perbedaan (Soedjatmoko, 1972: 104). Alhasil, Indonesia seperti juga Kenya, berada pada posisi yang sama: yaitu penyangkalan pada rahim, muasal dari konsepsi kebangsaan.
Namun, kecenderungan penghilangan identitas kemajemukan bukanlah hal baru, dan bukan pula kasus yang hanya terjadi pada negara multikultural seperti Indonesia. Dengan alasan yang berbeda, dunia, paska Perang Dunia kedua mengalami fase serupa. Sejalan dengan perkembangan pemikiran liberalisme, hak asasi manusia diletakkan secara mendasar pada individu, tanpa pembedaan ras, etnis, ataupun agama. Nampaknya perkembangan pemikiran ini sejalan dengan gelombang dekolonialisasi yang menuntut persamaan hak, sehingga pasal tentang hak minoritas, ataupun hak yang mengatur tentang identitas khusus (indigenious), tidak tercantum dalam Piagam PBB (Kymlicka, 2003: 5). Namun memasuki dekade 90an, berbagai konflik yang mengemuka, mulai dari konflik Balkan hingga terorisme, menyadarkan dunia bahwa terdapat entitas politik lain selain daripada individu: yaitu etnis dan agama. Kesadaran atas perbedaan identitas berujung pada konsekuensi bahwa setiap identitas memiliki kadar pemenuhan hak yang berbeda-beda (sebagai contoh saja, lihat ketika kebebasan berpendapat bersinggungan dengan dogma agama, keduanya jelas-jelas memiliki nilai keadilannya masing-masing). Dan atas kesadaran ini, barulah pemikiran liberal beranjak dari kesetaraan hak individu menjadi politik multikulturalisme. Kymlicka menyebutnya sebagai “terapi liberalisme” atas shock yang dialaminya terhadap perbedaan – hasilnya adalah diusungnya berbagai kajian tentang hak minoritas hingga pengakuan masyarakat adat (indigenous people) untuk didorong penerapannya dalam bentuk kebijakan negara, (anehnya) termasuk di Indonesia. Aneh – karena multikulturalisme yang merupakan rahim bangsa, harus dirumuskan kembali oleh nilai-nilai dari luar. Gambaran yang mengingatkan saya pada kalimat sinis Isaacs: semakin luas sistem komunikasi kita, maka semakin sedikit yang kita ketahui apa yang kita komunikasikan (Isaacs, 1972: 2).
Dan Indonesia nampaknya memang “semakin tidak memahami bahasanya sendiri”, yaitu bahasa kemajemukan. Padahal mengacu pada pandangan F Budi Hardiman dalam tulisannya yang berjudul Belajar dari Politik Multikulturalisme (dalam Kymlicka, 2003: xix), Indonesia memiliki alasan yang cukup untuk tetap optimis dalam multikulturalisme. Syarat utama yaitu adanya mayoritas yang liberal telah hadir – dalam konteks masyarakat Indonesia, Islam moderat telah memberikan ruang yang cukup luas untuk keberadaan identitas keagamaan lain. Pilar inilah yang harus tetap dijunjung tinggi dan dipertahankan. Namun, demikian pula sebaliknya, kalangan minoritas yang diberikan hak bersuara tidak seharusnya menjadikan hak tersebut sebagai “cagar budaya” atau imunitas dari demokrasi publik (Habermas dalam Kymlicka, 2003: vvii) – dengan kata lain, nilai-nilai yang diusung harus tetap berakar pada politik multikulturalisme.
Jika bisa berandai-andai, rasanya luka lebam sejarahlah yang menjadikan bangsa ini menjadi terbata-bata pada perbedaan, yang seharusnya menjadi gerak alamiah bangsa. Semakin membenci yang lain, karena kurang paham pijakan. Arah (buntu) kebudayaan yang mengacu pada tafsir “persatuan nasional” yang semena-mena menjadi salah satu penyebab utama kita menjadi gamang terhadap multikulturalisme. Dan sebagai bagian didalamnya, tentu kegamangan ini benar-benar terasa, terlebih ketika harus kembali menyaksikan benturan atas dasar perbedaan, baik agama, ras ataupun etnis. Hingga pada akhir puisi, saya terpaksa mengutuk – terkutuklah manusia yang semakin tidak memahami bahasanya sendiri.
Sumber bacaan:
Isaacs, Harold, 1993, Idols of the Tribe: Group Identity and Political Change (terj), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
Kymlicka, Will, 2003, Kewargaan Multikultural (Terj), LP3ES, Jakarta
Soedjatmoko, 1972, “Menjelang Suatu Politik Kebudayaan” dalam Etika Pembebasan, LP3ES, Jakarta

kontak via editor@antimateri.com