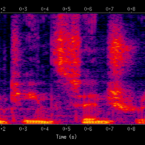Musik memiliki posisi penting untuk memahami gambaran sosial-kultural sebuah bangsa. Kali ini, ulasan tentang musik akan mengacu pada satu buku berjudul Palestinian Music and Song: Expression and Resistance since 1900 terbitan Indiana University Press tahun 2013. Empat editor yang memiliki wawasan mumpuni dalam kajian musik Palestina dan musik Arab bergabung sebagai editor: Moslih Kanaaneh, Stig-Magnus Thorsén, Heather Bursheh, dan David A. McDonald. Adapun sebab diangkatnya tulisan tentang musik Palestina didasarkan pada dua hal: (1) sebagai upaya memahami musik yang berkembang di Palestina, sebelum dan sesudah al-Nakba (‘bencana pengusiran’ tahun 1948); dan (2) untuk menggenapi tulisan terkait identitas musik yang beberapa waktu lalu membahas tentang musik diaspora Yahudi, Klezmer. Kedua kuriositas tersebut terjawab lugas oleh kumpulan tulisan dalam buku Palestinian Music and Song yang terbagi dalam tiga gagasan utama: sejarah, identitas, dan resistensi.
Kini, siapapun dapat dengan mudah menemukan playlist spotify atau kanal youtube ketika memasukkan kata kunci “Musik Palestina”. Sayangnya, lingkup dan persepsi akan musik Palestina kerap terbatas pada posisinya sebagai lagu perjuangan anti-kolonialisme semata. Di satu sisi, persepsi tersebut ada benarnya–bahkan dalam bab pembuka, Kanaaneh menyatakan bahwa “musik Palestina telah diperkuat dan dilemahkan oleh kolonialisme dan pendudukan asing”. Namun di sisi lain, memposisikan “Musik Palestina” hanya sebatas musik perjuangan adalah pengerdilan semena-mena mengingat pengaruh peradaban besar dunia–diantaranya: Persia, Helenistik, Romawi, Bizantium, Turki, juga Arab–dapat ditemukan baik dalam nada, instrumen, hingga lagu-lagu rakyat. Masuknya Palestina ke dalam geografi-budaya Syam (Levant dan Suriah Raya) pada abad 7 masehi, memperkuat pengaruh Arabisasi, termasuk musik, yang masih dominan hingga saat ini. Alhasil, karakter musik Palestina cenderung akan serupa dengan musik di wilayah Aleppo, Damaskus, Beirut, juga Amman, karena memiliki pengaruh budaya yang sama.
Perkembangan musik Palestina di awal abad 20 menggambarkan keberlanjutan pengaruh geografi-budaya Syam dalam segi musikalitas ataupun lingkaran para musisinya. Hadirnya panggung musik (venue) dan teknologi rekaman, memungkinkan para musisi Palestina untuk semakin terhubung dengan lingkaran musisi di kota besar lain, seperti Istanbul, Beirut, Aleppo, Damaskus, hingga Kairo. Bahkan pada periode 1920-1930an, Palestina yang memiliki posisi strategis di wilayah Kanaan, menjadi magnet bagi para seniman dan musisi dari Jazirah Syam dan Arab Maghribi. Musisi kenamaan seperi Ummu Kulthoum, misalnya, kerap berkunjung untuk berkolaborasi dengan musisi lokal, Tawfiq Jawhariyyah, pemain nay (seruling) kenamaan asal Yarusalam. Beberapa musisi besar lain seperti Mohammad Abddul al-Wahab atau Mohammad Hasanain, bahkan menetap di Palestina.
Selain pengaruh Arabisasi, perkembangan musik rakyat adalah karakter lain yang mengemuka dari sejarah musik Palestina pada awal abad 20. Berbeda dengan pengaruh Arabisasi dalam musik populer, musik rakyat Palestina mengadopsi lirik dari cerita rakyat yang sudah ada, bahkan sebelum dominasi budaya Arab di Palestina. Sehingga tidak aneh apabila terdapat lirik musik rakyat Palestina yang menggunakan bahasa Persia, Armenia atau Turki. Karakter unik ini bersandingan dan memiliki tempat tersendiri di kalangan masyarakat Palestina. Dan ketika Radio Jerusalem diresmikan pada tahun 1936, siaran udara dibagi ke dalam tiga segmen: Musik Arab, Musik Yahudi, dan Musik Rakyat. Radio Jerusalem ditutup pada tahun 1948 ketika identitas Palestina dinegasikan, termasuk identitas musiknya.
Setelah peristiwa Al-Nabka (sebutan warga Palestina atas pengusiran tahun 1948), identitas musik Palestina tidak lagi sama. Dalam buku Palestinian Music and Song, gagasan terkait musik dan identitas setidaknya dapat dirangkum dalam beberapa poin penting: Pertama, terjadinya arus ‘Yordanisasi’ antara tahun 1949-1967, dimana kiblat musik Palestina berubah arah. Perubahan kiblat ini merupakan konsekuensi langsung dari arus pengungsi masyarakat Palestina ke Yordania, dan memberikan dampak pada terbentuknya skena-skena musik Yordania di Palestina yang berkembang pesat pada kisaran tahun 1960an. Kedua, paska 1948, terdapat pengkategorisasian musik atas dasar batas geografis dalam memetakan musik di dunia Arab, seperti musik Kuwait, musik Arab Saudi, musik Suriah, musik Lebanon, musik Irak, musik Mesir, dan juga musik Palestina. Gagasan ini lantas dikritik sebagai upaya kooptasi budaya melalui logika kolonial; walau sebagian musikolog, seperti Thorsén dan Bursheh (dua editor buku Palestinian Music and Song) memberikan dekonstruksi atas gagasan kolonial melalui penekanan musik vernacular, ungkapnya: “the distinctive nature of Palestinians as individuals as well as their belonging to humankind” (hal. 11) .
Ketiga, semakin menghilangnya musik sekular digantikan dengan musik bertema pan-Arabisme dan nasionalisme. Repertoar ini merupakan persinggungan musik dengan politik, dan semakin menguat pada kisaran 1967, ketika konflik Arab-Israel memuncak. Salah satu contoh perubahan repertoar terjadi pada musik rakyat Palestina, yaitu ketika wacana nasionalisasi dijejalkan ke dalam sejumlah cerita rakyat. Bentuk ini, menurut Bursheh, memunculkan perdebatan sengit antara para musisi Palestina yang menempatkan musik pada posisi yang bertentangan: “al-fann li al-fann” (seni untuk seni), atau “al-fann li al-nās” (seni untuk manusia) (hal. 54); dan sejak tahun 1967, fungsi kedua lah yang lebih mengemuka. Tiga poin di atas merupakan dampak langsung dari Al-Nabka terhadap musik di Palestina. Palestina banyak kehilangan musisi terbaiknya, juga kehilangan repertoar musik rakyat yang lugu. Awalnya, lagu rakyat dinyanyikan para petani di ladang, atau pada acara sukacita (perkawinan atau festival); namun paska 1967, lagu rakyat menjelma teriakan lantang tentang penolakan pengusiran dan okupansi. Menurut Kanaaneh, perubahan repertoar musik rakyat menjadi fungsi politik, adalah bentuk negosiasi identitas untuk dapat bertahan dalam konflik berkepanjangan.
Negosiasi identitas dalam musik Palestina juga berkelindan dengan aspek lain, yaitu globalisasi dan agenda kemanusiaan. Adalah tahun 1998 ketika musik hip hop mulai memasuki ruang imajinasi dan menjadi bagian dalam repertoar musik generasi muda Palestina. DAM, merupakan grup pertama yang mempopulerkan gerakan hip hop di Palestina. Menurut Basel Abbas, produser musik yang lalu menjadi bagian dalam gerakan hip hop di Palestina, karakter skena hip hop yang “beragam dan terpecah” memiliki kesamaan dengan karakter musik Arab, “It expresses as much frustration, polarization and diversity as Arabs themselves enjoy and suffer” (hal. 70). Tidak ada manifesto atau festival yang menyatukan gerakan hip hop ini; secara alamiah, hip hop menjadi cara berkomuninasi sekaligus terapi bagi generasi yang terpecah. Safieh (hal 80) menyatakan bahwa hip hop memenuhi fungsi musik rakyat pada awal abad 20 di Palestina. Memasuki abad 21, platform media sosial menjadi sarana penting dalam penyebaran dan pengarsipan digital musik hip hop di Palestina. Selain hip hop, musik populer lain yang menjadi bagian keseharian masyarakat Palestina antara lain: Mustafa al-Kurd (Yarusalam), Fairuz and Nancy Ajram (Libanon), Shireen (Mesir), Kathem Al-Saher (Irak), dan Mohammad Abdo (Saudi Arabia); namun, berbeda dengan hip hop, musik populer lainnya tidak berkembang menjadi gerakan resistensi.
Pengaruh musik lain yang hadir di masyarakat Palestina bersinggungan dengan agenda kemanusiaan. Terdapat upaya dari berbagai organisasi kemanusiaan dan kebudayaan dunia untuk menghidupkan kembali identitas musik Palestina melalui penggalian unsur Arab klasik dan jejak musik Turki dalam musik rakyat Palestina. Gagasan ini berakar dari kesadaran pentingnya musik dalam narasi identitas sebuah bangsa; namun, karena alasan praktis dan tekanan konflik, upaya ini memiliki hambatan yang lebih besar dari sekedar “tidak adanya sumbangan dana”. Buku Palestinian Music and Song adalah bagian dari proyek kebudayaan di atas. Namun berbeda dengan sudut pandang etnomusikologi, seperti Orientalism and Music Mission: Palestine and the West karya Rachel Beckles Willson yang diterbitkan Cambridge University Press tahun 2013, buku ini lebih menyoroti pembentukan identitas dan transformasi musik Palestina ketika bersinggungan dengan Al-Nabka (bencana pengusiran). Musik resistensi, yang kini menjadi bagian keseharian masyarakat Palestina, adalah bagian dari negosiasi identitas musik untuk memenuhi fungsi “al-fann li al-nās” (seni untuk manusia). Tanpa memahami sejarah panjang dan bangun budaya Palestina, resistensi musik Palestina akan dipersepsikan sebatas lagu perjuangan yang kalah nyaring dari suara desingan bom dan mortar.
I’m Jerusalem, Bethlehem, and Jenin refugee camp
The call to prayer, the bells, the crescent and the cross . . .
I’m the teacup and the falafel sandwich
Generosity and greed, morality and farce
Lies and betrayal and honesty and persistence
I am Palestinian until I die
(h2z, Ana Falastini)
Sumber Gambar:
Musicians in Jerusalem, late 19th century, wiki image
Sumber Bacaan:
Kanaaneh, M., Thorsén, S., Bursheh, H., McDonald, D. 2013. Palestinian Music and Song: Expression and Resistance since 1900. Indiana University Press.
Beckles Willson, R. 2013. Orientalism and Music Mission: Palestine and the West. Cambridge University Press.

kontak via editor@antimateri.com