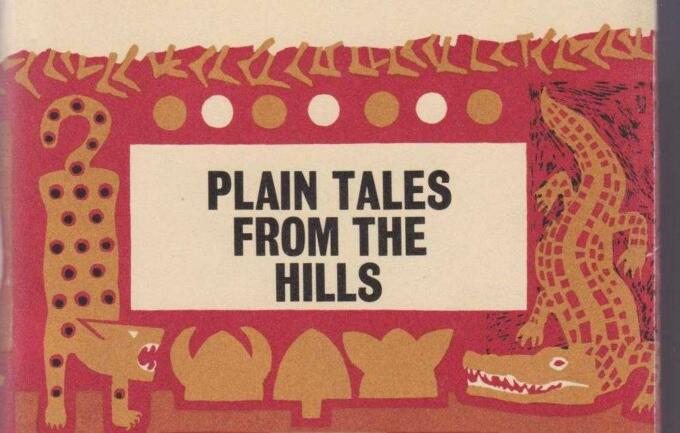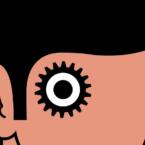Rudyard Kipling memulai karir sebagai penulis cerita pendek lewat kumpulan karya berjudul Plain Tales from the Hills yang saya terjemahkan sekenanya menjadi ‘Kisah-kisah Datar dari Perbukitan’. Didalamnya terangkum empat puluh cerita dengan berbagai latar dan nuansa: mulai dari cinta buta seorang gadis jelita bernama Lispeth; balada tragis seorang bocah lelaki yang bunuh diri karena menganggap segala hal terlalu serius; sepak terjang Nyonya Hauksbee yang mendatangkan masalah dimanapun ia berada; hingga kisah McIntosh, sang oportunis sekarat yang tidak memiliki apa-apa lagi untuk ditawarkan pada kehidupan. Plain Tales from the Hills diterbitkan pada tahun 1888 ketika Kipling menjadi editor dan pengisi kisah fiksi pada Civil and Military Gazette, koran harian British India yang berbasis di Lahore–kini Pakistan. Namun berbeda dengan pilihan diksi untuk antologi cerpen perdananya, karir Kipling jauh dari kesan datar. Kontroversi pertama dapat dimulai dengan mengangkat fakta bahwa Kipling menjadi sastrawan Inggris pertama yang menerima nobel sastra pada tahun 1907 sebagai sebuah ironi, mengingat Kipling mendapatkan penghargaan tersebut justru karena mengolok-olok konvensi ‘adiluhung’ kesusastraan Inggris. Majelis nobel mengekstrak apreasiasi atas karya Kipling dalam kalimat berikut: “in consideration of the power of observation, originality of imagination, virility of ideas and remarkable talent for narration which characterize the creations of this world-famous author“. Sebuah apresiasi yang tidak didapatkan Kipling dari publik sastra di negaranya sendiri.
Jika setelah membaca paragraf pembuka di atas rasa penasaran menghampiri dan tergugah mencari Plain Tales from the Hills melalui pencarian kilat dunia maya, membacanya, lalu menemukan diri kecewa karena mengharapkan sesuatu yang mencengangkan, tapi tidak menemukan sama sekali–maka saya sarankan untuk kembali mengingat bahwa yang tengah anda baca adalah ‘kisah-kisah datar’ secara harfiah. Melalui berbagai pembacaan (Friedman, 2016; Trilling, 1996; Page, 1985), sampailah saya pada fakta bahwa kata ‘datar’ adalah kunci dari kekuatan artistik cerita pendek seorang Rudyard Kipling. Ia tidak ‘secanggih’ Charles Dickens, tidak pula ‘sarkas jenaka bercampur genit’ seperti Oscar Wilde. Jika dibandingkan dengan dua pilar sastra Inggris tersebut, cerita-cerita Kipling sangat sederhana. Bahkan pasangan Woolf (Virginia dan Leonard) menyayangkan keberadaan karya Kipling sebagai bagian dari kesusastraan Inggris. Namun, nampaknya kita harus sepakat dengan celotehan George Orwell (seteru politik sekaligus pengkritik karya-karya Kipling) yang menyatakan bahwa bagian paling menyebalkan dari karya-karya Kipling adalah persistensinya–bahkan setelah dua generasi sastra karya Kipling diperbincangkan. Tapi apa yang membuat ‘kisah-kisah datar’ Kipling dapat melampaui waktu?. Friedman (2016) menjawabnya dengan singkat: Kipling mampu menyuntikkan imajinasi kedalam realita dalam takaran yang tepat. Takaran inilah yang membuat karyanya mampu bersentuhan dengan banyak orang.
Alih-alih tenggelam dalam ‘snobbisme’ akut yang banyak diidap oleh penulis, Kipling memilih untuk berjalan pada sisi lain dari dunia gemilang (sastra) intelektual. Simak saja magnum opus sang pemenang nobel: The Jungle Book (1984). Ia tidak bercerita tentang kegelapan relung pikiran manusia sebagaimana banyak digeluti penulis di peralihan abad 20, tapi memilih tema yang jauh dari genre sastra modern, yaitu tentang kisah petualangan Mogwli, anak kecil yang dibesarkan oleh kumpulan serigala dan beruang madu sebagai mentornya. Membaca The Jungle Book mengingatkan saya pada lukisan ‘naïve’ Henri Rousseau yang hadir layaknya angin segar ditengah hiruk pikuk teori seni juga teori sastra. Kipling dengan sadar menjadikan kesederhanaan (baca: ‘kedataran’) ini sebagai kekuatan dari karya-karyanya. Entah berapa penulis yang kemudian menjadikan teknik penulisan cerita pendek Kipling sebagai inspirasi, setidaknya tiga dapat saya sebutkan (Friedman, 2016): Jorge Luis Borges dengan gaya detil realistik pada berbagai institusi dan komunitas surreal; Isak Dinesen yang membuat karakternya ‘datar’ (plain) namun punya greget tersendiri; dan Flannery O’Connor’s yang menggunakan ukuran a la Kipling untuk menakar keseimbangan antara realita dan imajinasi surreal.
Namun, sepak terjang sang cerpenis ‘datar’ ini tidak berhenti pada penghargaan nobel dan pengaruh luasnya. Ia juga menuangkan karyanya dalam bentuk lain, yaitu esay dan puisi. Kebanyakan esaynya bertema catatan perjalanan atau hasil pengamatan selama ia berkenalan ke berbagai belahan dunia. Salah satunya berjudul From Sea to Sea and Other Sketches, Letters of Travel yang berkisah tentang perjalanannya ke Burma, China dan Jepang. Dengan gaya tutur khas, Kipling berhasil memunculkan berbagai istilah yang masih begema hingga saat ini, sebut saja ungkapan ‘But that’s another story’ atau frase ‘once upon a time’ yang diambil dari cerpen dalam Plain Tales atau judul puisi anti-revolusioner nya yang kini dijadikan slogan politik konservatif, yaitu “The White Man’s Burden”.
Take up the White Man’s burden—
Send forth the best ye breed—
Go, bind your sons to exile
To serve your captives’ need;
To wait, in heavy harness,
On fluttered folk and wild—
Your new-caught sullen peoples,
Half devil and half child.
—The White Man’s Burden
Tidak ayal bahwa puisi ini lantas memunculkan kontroversi dan berujung pada pengucilan karya-karya Kipling oleh lingkaran anti-imperialism. Mark Twain, penulis kenamaan Amerika yang dengan sekuat tenaga mengkritisi sistem nilai imperialisme dan rasisme, di satu sisi terpaksa angkat bicara melalui esay bertajuk ‘To the Person Sitting in Darkness’ (1901) yang menyasar pandangan imperialism pada perang Boer juga perang Amerika-Filipina–dua perang yang didukung oleh Kipling. Namun di sisi lain, Twain berada pada jajaran penulis yang memberikan penghargaan setinggi-tingginya pada eksplorasi, improvisasi dan teknik penulisan Kipling. Dillema ini lantas membentuk karakter pada hubungan antara keduanya yang berpijak pada titik keseimbangan rentan antara adu jotos dan adu gelas. Sang penyulut kontrovesi sendiri tidak banyak berkomentar, pun tidak pernah mengoreksi gagasan politik konservatif yang ia pegang hingga akhir karirnya. Kontroversi lain hadir ketika gagasan orientalisme mulai dikemukakan–dan tentu saja Kipling berada pada daftar utama jajaran penulis orientalisme dan menjadi sasaran empuk kritisisme para akademisi dari mazhab ini
Untungnya Kipling tidak mengalihfungsikan seninya menjadi semata-mata teater politik. Di tengah hiruk pikuk yang ada, ia tetap mempertahankan gaya lugunya dan memberi ruang bagi imajinasi untuk dapat melampaui desakan realita. Atau itulah yang kita pikirkan, karena T.S Eliot mewanti-wanti bahaya dari penulis yang satu ini (Trilling, 1996): ‘An immense gift for using words, an amazing curiosity and power of observation with his mind and with all his senses, the mask of the entertainer, and beyond that a queer gift of second sight, of transmitting messages from elsewhere, a gift so disconcerting when we are made aware of it that thenceforth we are never sure when it is not present: all this makes Kipling a writer impossible wholly to understand and quite impossible to belittle’. Setelah membaca ucapan Eliot, Jungle Book menjelma menjadi lebih dari sekedar kartun selintas di acara televisi pagi (walau sangat disarankan untuk membaca teks aslinya). Melalui teknik penulisan khasnya, Kipling tidak tertandingi dalam meramu beragam ‘kisah datar’ menjadi karya sastra yang mendunia. Alhasil, seperti ungkapan Eliot: kita tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi (dalam cerita-ceritanya) tapi kerap menemukan diri sulit beranjak hingga penghujung cerita.
Sumber Bacaan:
Friedman, R. L. 2016. Rudyard Kipling’s Techniques. Master’s thesis, Harvard Extension School.
Page, N. 1985. A Kipling Companion. New York: The Macmillan Press.
Trilling, L. 1996. Kipling’s Mind and Art. California: Stanford UP.

kontak via editor@antimateri.com