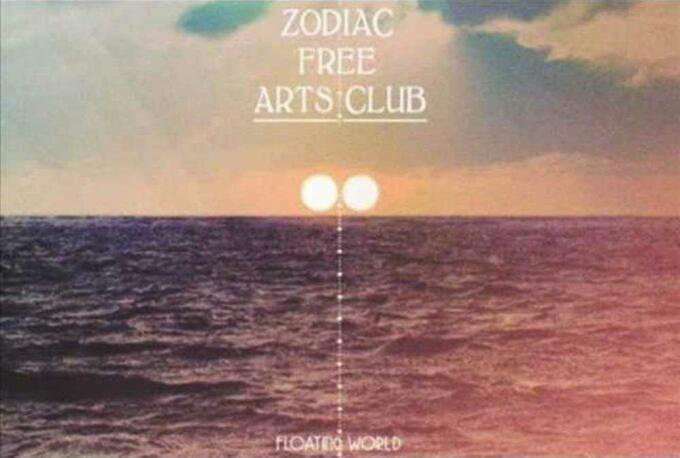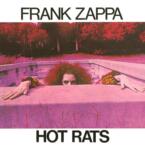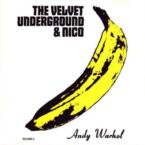Persinggungan musik dengan berbagai ritus keagamaan telah berlangsung sejak awal perkembangan agama itu sendiri. Manusia yang berkumpul dalam sebuah perayaan keagamaan menggunakan nyanyian atau musik sebagai ekspresi cinta mereka terhadap objek imanen yang mereka puja – oleh sebab itulah maka kebanyakan situs ritual keagamaan, mulai dari paganisme hingga agami samawi selalu riuh dengan nyanyian atau musik puja-puji. Namun ketika agama mengalami dekadensi – dengan hanya menyisakan ritual-ritual tanpa makna –, ruang kosong di dalamnya diisi oleh berhala-berhala baru (idol atau dewa-dewa palsu) dalam berbagai bentuk: alat elektronik, mesin atm, kendaraan atau objek apapun yang mewakili pencapaian tertinggi manusia. Dan dari sekian banyak dewa-dewa pagan baru tersebut, terdapat satu yang menarik perhatian kami: idol dalam bentuk musisi, setengah Dyonisus setengah Manusia, dengan kuil-kuil pemujaan yang bertebaran di sepanjang sejarah musik modern.
Music Venue dan Paganisme Modern
Teori psikologi massa menyatakan bahwa ketika manusia berkumpul atas tujuan yang sama – yang diasosiaikan dengan istilah club –, namun tidak menemukan cara berkomunikasi yang tepat, mereka akan secara otomatis bernyanyi (atau menciptakan nyanyian). Mungkin inilah yang menjadi awal mula berkembangnya Vaudeville di Amerika pada kitaran tahun 1880 hingga 1930-an – Vaudeville sendiri diambil dari bahasa Perancis yang berarti “nyanyian kota”. Bayangkan sekumpulan koboi di saloon-saloon, minum sambil kebosanan setengah mati hingga pada akhirnya tercetuslah ide untuk membuat suasana meriah dengan nyanyian, tapi karena suara mereka hilang bersama tegukan bir, maka mereka memutuskan untuk menyewa penyanyi dan penari – sebuah konsep yang berkembang menjadi music venue yang kita kenal saat ini. Sedangkan sejarah music venue di Inggris – dan Eropa secara keseluruhan – merupakan dari penyederhanaan music hall (muncul untuk pertama kalinya di Wina pada abad 16), yaitu sebuah theater musik yang menampilkan oskestra lengkap namun berubah sejalan dengan perubahan musik dan instrumennya. Pada perkembangan selanjutnya, music hall di Inggris mengadopsi konsep saloon ala Amerika dengan bar di dalamnya, diawali dengan kemunculan Canterbury Music Hall di Middlesex pada tahun 1850 kemudian menyebar ke seantero negeri.
Selain bar dan gedung pertunjukkan, music venue dapat muncul dalam beragam bentuk, seperti festival yang biasanya mengambil tempat di luar ruangan dengan tujuan menampung banyaknya jumlah massa. Venue luar ruangan lainnya adalah bandstand, biasanya berupa panggung sementara untuk masa yang jumlahnya terbatas – bentuk venue ini banyak berkembang di Amerika pada tahun 1930an untuk menampilkan blues, grass dan folk. Venue musik lain yang tidak kalah menarik adalah belakang truk – secara harfiah. Beberapa musisi folk awal seperti Woody Guthrie jarang sekali menggunakan panggung dalam tur antar kotanya, ia cukup turun dari truk, atau bahkan menyanyi di atasnya, lalu melenggang pergi tanpa meminta salut dari para penontonnya. Konsep ini dikenal dengan istilah bandwagon, diambil dari kebiasaan rombongan sirkus yang menjajakan musiknya dari satu kota ke kota lain. Namun dalam perkembangannya, istilah bandwagon mengalami perubahan, bukan lagi “belakang truk” secara harfiah, namun mengacu pada bentuk loyalitas penggemar tingkat tinggi, hampir menyerupai kultus – salah satunya dilakukan The Deadhead, para penggemar Grateful Dead yang mengikuti hampir semua pertunjukan band pujaannya pada tahun 1960an.
Music venue, baik dalam gedung pertunjukkan, klub-klub musik atapun bentuk lainnya, pada akhirnya menjadi salah satu kiblat bagi kemunculan kembali konsep pagan: karena disanalah dengan mudah kita dapat melihat kelahiran – bahkan kematian – berhala-berhala musik modern yang dipuja penggemarnya sedemikian rupa. Paganisme sendiri merupakan [sistem] kepercayaan untuk menemu hidup ideal melalui eksplorasi tanpa batas dan pengangungan kebebasan – dalam paganisme kebebasan adalah absolut, kecuali (tentu saja) ketika bersinggungan dengan kehendak dewa. Melalui penggambaran tersebut, tercermin bagaimana gerakan pagan berkembang di venue-venue musik: musisi – sebagai idol – menjadi peletak aturan main bagi para penggemar dan pengikutnya. Melalui eksplorasi gila yang mereka lakukan, kualitas musik mereka berhasil menembus dinding gedung pertunjukkan dan meyebar ke segala penjuru bumi, maka menjelmalah kuil-kuil pagan modern dimana kita bisa menziarahi jejak para musisi tersebut dalam mencipta – atau menghancurkan – konsep musik mereka.
Ziarah Kuil Pagan Modern
Dalam sejarah Rock n roll – mengacu pada definisi luas rock n roll yang mencakup tidak hanya musik, tapi juga industri dan gaya hidup yang muncul pada akhir 1950an – kita mengenal sejumlah klub musik yang memberi pengaruh luas bagi perkembangan dunia musik pada eranya ataupun setelahnya – pengaruh ini dikarenakan satu hal: menjadi tempat kelahiran band/musisi yang bukan sembarang band/musisi. Dan New York adalah tujuan “pertama” dan “utama” dalam catatan peziarah manapun yang telah menjual jiwanya pada rock n’ roll – kota yang mengingatkan kita pada nostalgia, bahwasannya: “New York is just like Jerusalem for musicians”. Terdapat catatan panjang mengenai ke-sakralan New York dalam mempengaruhi perjalanan musik yang kita kenal saat ini, dan pengaruh-pengaruh itu dimulai dari klub-klub yang bertebaran di seantero kota. Salah satunya adalah Gerdes Folk City, sebuah restaurant yang dibuka pada tahun 1960 namun berkembang menjadi salah satu venue music paling dikenal di wilayah West Village, New York – rentaurant/bar ini menjadi begitu terkenal karena disinilah karir Bob Dylan mulai mendapat perhatian publik. Pada era 1960-1970an, Folk City – sebutan tenarnya – menjadi panggung beberapa nama terkenal mulai dari Janis Joplin, Jimi Hendrix, The Byrds, hingga Joni Mitchell, dan tidak ketinggalan Emmylou Harris yang kebetulan menjadi pelayan di Folk City sebelum memulai karirnya sebagai musisi. Pada tahun 1978, dikarenakan perubahan manajemen, Folk City mengubah konsep musiknya dengan memasukkan genre rock secara lebih luas, sehingga memberi ruang bagi Elvis Costello, Yo La Tengi, 10.000 Maniacs untuk bermain disana – juga Sonic Youth yang selalu menyebutkan Folk Music sebagai tonggak awal musik perkembangan mereka.
Di akhir tahun 60-an, terdapat beberapa klub yang menjadi tempat bagi sejumlah pemusik terhebat dunia berkumpul, salah satunya adalah Filmore East, sebuah klub yang berada di jalan 105 Second Ave, New York. Dalam legendanya, konon klub ini menjadi tempat “terpanas” di masanya, tercatat sejumlah nama besar seperti Jimi Hendrix, Jefferson Airplane, Led Zeppelin, Crosby Stills dan Nash, The Allman Brothers Band, Pink Floyd, The Grateful Dead , Frank Zappa, king Crimson, John Lennon, Derek dan domino, Flying Burrito Brothers, dan Van Morrison pernah menginjakkan kaki mereka di klub ini. Akan tetapi pada tahun 1971, klub ini terpaksa ditutup karena alasan keuangan, dan setelahnya sejarah Fillmore diperingati dengan dibangunnya mosaik pada tiang lampu lalu lintas diantara sudut jalan, sebagai bentuk penghormatan para peziarah [rock n roll] terhadap klub tersebut.
Tempat lainnya yang juga memiliki kekentalan sejarah adalah Max’s Kansas City, yaitu sebuah klub yang menjadi tempat nongkrong populer berbagai seniman dan penulis di akhir era 60-an – sebut saja diantaranya Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Richard Serra, Phillip Glass, William S. Burroughs, dan Allen Ginsberg. Selain itu klub ini merupakan episentrum bagi gelombang baru musik 70-an dengan musisi seperti Lou Reed, David Bowie, Patti Smith dan Iggy Pop sebagai pengisi acara tetap di sana – bahkan The Velvet Underground memainkan beberapa pertunjukan terakhir mereka di club ini, Max’s ditutup pada tahun 1974. Electric Cicus adalah klub lain di New York yang menjadi saksi bisu kegilaan para seniman Amerika. Klub malam yang berdiri pada tahun 1967 sampai 1971 ini menampilkan pertunjukan band-band seperti The Velvet Underground, Sly and the Family Stone, dan The Grateful Dead. Dengan mengangkat para musisi dengan konsep musik ajaib yang “sulit untuk ditebak”, maka Electric Circus menjadi terkenal dengan sebutan lain: “Psychedelic and Experimental Club”. Electric Circus juga memiliki keajaiban lain, ia menjadi klub yang mempelopori pencahayaan dan proyeksi efek sebagai latar bagi para pengisi acara yang tampil – sehingga pada akhirnya klub ini dipilih menjadi tempat pertunjukan musik elektronik awal di Amerika yang dipopulerkan oleh Terry Riley dan Morton Subotnick. Bangunan ini direnovasi pada tahun 2003, dan sekarang menjadi rumah bagi beberapa toko termasuk St. Mark Market dan Chipotle.
Memasuki era 70-an, terdapat sebuah klub yang menjadi tempat penting dalam hari-hari awal “New York punk”, yaitu Mudd Club. Tempat ini adalah pusat kelahiran “No Wave” dan “New Wave”, yang menjadi petanda masuknya episode baru dari pergerakan dunia Art and Music di Amerika. Tempat ini sering dikunjungi oleh Nico, The B-52, Black Flag, Jean-Michel Basquiat, Keith Haring, Madonna, dan David Byrne. Bahkan Talking Head mengabadikan klub ini dalam lagu mereka, “Life During Wartimes”. New York memiliki tempat sakral lain bernama CBGB – singkatan dari Countries, Bluegrass and Blues, yaitu aliran musik yang berkembang di Amerika sejak 1920an – namun klub musik ini menjadi terkenal bukan karena musik yang tercantum dalam namanya, tapi karena dobrakan punk yang berkembang di New York pada tahun 1970an. Sejumlah band punk yang menjadikan CBGB tempat ibadahnya antara lain: Ramones, Television, Patti Smith, The Voidoids, Blondie, hingga Misfit. Pada saat itu, belum sempurnalah keimanan seorang musisi punk jika belum tampil di CBGB.
Selain New York, kiblat lain musik Amerika – yaitu California – memiliki kuil legendarisnya tersendiri bernama Whiskey a Go Go. Bar dengan konsep discotheque ini – yang hanya memainkan musik rekaman – dibuka pertama kali pada Januari 1964 di kawasan Sunset Strip yang terkenal sebagai jalanan milik dewa-dewa musik Amerika, dengan Whiskey a Go Go sebagai pusatnya. Namun dalam perkembangannya, Whiskey a Go Go mengubah konsep discotheque menjadi live music performance dan hadirlah Whiskey a Go Go seperti yang kita kenal saat ini: rahim bagi industri musik, karena tak terhitung berapa banyak band terbentuk atau menandatangi kontrak setelah memainkan musiknya di tempat ini. Diantaranya sekian banyak musisi/band tersebut, terdapat dua band yang berada di atas rata-rata, yaitu Mother of Invention, band “sangar” garapan Frank Zappa dan The Doors – walaupun dalam kasus the Doors, kontrak didapat setelah mereka dipecat dari Whiskey a Go Go terkait insiden tabu Oedipus yang dinyanyikan Morrison dalam The End (The most of iconic performence born in a most iconic place. Sounds great, right?). Adapun band yang terbentuk dalam aura sakral Whiskey a Go Go diantaranya adalah the Monkeys – yang menculik basis Chip Douglas dari the Turtles setelah melihatnya tampil di a Go Go. Band lainnya yang “menetap” disana adalah The Byrds, Alice Cooper, hingga Them-nya Van Morrison pada era 1960an, berlanjut pada Mudhoney, Soundgarden, hingga 7 Years Bitch pada era 1990 – menjadikan Whiskey a Go Go salah satu klub musik paling berpengaruh di Amerika. Dengan rentang waktu yang telah dilaluinya, Whiskey a Go Go saat ini masih menjadi kiblat musik, salah satunya dengan menjadi tempat pilihan konser reuni Black Sabbath pada tahun 2011 – karena menurut mereka, sejarah rock [Amerika] berawal di Whiskey a Go Go.
Di Inggris kita menemukan jenis venue yang berbeda namun memiliki pengaruh yang sama kuat. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa sejarah pertunjukkan musik Inggris berawal dari bentuk konser klasik, maka bentuk venue-nya pun masih menggunakan konsep gedung pertunjukkan. Dua diantaranya bersinggungan langsung dengan sejarah rock, yaitu Royal Albet Hall di London dan Free Trade Hall di Manchester. Royal Allbert Hall adalah tempat prestisius bagi para musisi sebagai bentuk pembuktian kebesaran namanya. Sedangkan Free Trade Hall adalah tempat Sex Pistols meneriakkan ide-ide anarki mereka, sehingga akhirnya dikenal sebagai tempat lahirnya subkultur punk di Inggris pada tahun 1976. Namun, keberadaan gedung pertunjukkan sebagai music venue utama di Inggris tidak menutup jalan bagi bermunculannya klub musik dalam berbagai genre. Salah satunya adalah The Roxy, sebuah klub yang berdedikasi pada penyebaran gagasan punk – klub ini meneruskan teriakan Rotten dari Free Trade Hall ke lorong-lorong di kota London. The Roxy hanya beroperasi selama 100 hari, namun dalam waktu singkat tersebut berhasil meletakkan pilar-pilar punk awal dengan mengangkat nama-nama seperti The Damned, The Slits, The Stranglers, Wire, hingga The Jam. Memasuki tahun 1980, Inggris – khususnya Manchester – mengenal The Hacienda, sebuah klub malam yang operasionalnya didanai oleh penjualan rekaman New Order. Karena kemunculannya yang berbarengan dengan kelahiran genre new wave, maka The Hacienda dikenal sebagai basis musik new wave dan hal lain yang membuatnya begitu terkenal – yaitu sebagai pusat peredaran zat adiktif di Manchester, dan dari sanalah Hacienda mendapatkan julukan lainnya: acid house.
Namun ketika berbicara tentang sakralitas music venue dalam dunia rock, tidak ada yang bisa menyaingi Zodiac Free Arts Lab yang muncul di Berlin, – Jerman Barat saat itu – pada tahun 1969. Zodiac Free Arts Lab bukanlah sebuah gedung pertunjukkan ataupun klub musik, tapi sebuah ruang belakang yang disulap menjadi pusat pergerakan seni progresif jerman termasuk berbagai gagasan musik di dalamnya. Disini praktek pagan dalam kebebasan eksplorasi radikal dilakukan, sehingga musik yang muncul jauh dari tataran “standar pasar” – dan bergemalah free jazz, psychadelic rock dan avant-garde setiap malamnya. Malalui atmosfer kebebasan ekspresi musik yang dibangun di Zodiac Free Arts Lab, maka lahirlah apa kita kenal dengan krautrock – sebuah gerakan musik pembaharu yang dilakukan oleh generasi muda Jerman pada tahun 1969 demi menemu kembali identitas mereka yang telah lenyap terkubur pada masa kekejaman rezim Hitler – karena ternyata kekejamannya merangsek hingga wilayah [kebebasan] musik. Dari tempat ini munculah band-band seperti Amon dull, Faust, Harmonia, Popol Vuh, Can dan beragam kelompok musik lainnya yang dapat dikatakan seragam dalam hal musikalitas – keseragaman yang dipicu oleh kesamaan landasan pemikiran, yaitu: mempertanyakan ke-eksistensian duniawi, dan menganggap luar angkasa sebagai satu-satunya solusi atas keraguan mereka tersebut.
Epilog
Diantara tempat-tempat di atas, tidak semuanya dapat bertahan melalui pergantian scene musik dan gelombang gaya hidup, beberapa diantaranya memang telah menghilang – baik karena alasan finansial, masalah manajemen, ataupun karena tugasnya telah paripurna: seperti dalam kasus The Roxy dan Zodiac Free Arts Lab, keberadaan mereka yang singkat adalah bentuk dari dobrakan itu sendiri. Namun sebagai peziarah, rasanya kita tidak kehilangan cara untuk memasuki dunia sakral tempat-tempat tersebut. Ritual masih dapat dilakukan dengan musik sebagai salah satu kuncinya, sebagaimana Arthur Lee yang merangkum Whiskey a Go Go dalam lagu “Maybe the People Would Be the Times or Between Clark and Hilldale”. Keabadian situs-situs tersebut dapat kita temukan dalam karya musik yang lahir disana – melalui ritual pagan untuk melampaui pengkultusan berlebihan terhadap sang musisi (– sebagai idolatry) – karena dalam musik, bahkan sang musisi sendiri pun tidak penting: ia hanya dewa [palsu] yang dapat menghalangi pencarian, karena musik adalah kebebasan itu sendiri. Dan makna dari ziarah ini bukanlah terletak pada apa yang tersimpan di balik dinding yang kapanpun dapat hancur – melainkan pada apa yang pernah ada di dalamnya – inti dibalik simbol ragawi, yang siapapun tak akan pernah bisa menghapusnya.
…adrift in the age of aquarius.