Terdapat segitiga sakral dalam musik yang membuat musik memiliki makna namun di saat yang sama, kerap memunculkan perdebatan tidak perlu. Segitiga itu adalah komposer, musisi, dan pendengar – ketiganya senantiasa tumpang tindih dengan cara yang aneh dalam memperlakukan, menafsir dan memaknai musik (dalam hal ini, mari kita kesampingkan kritikus, karena keberadaan mereka sebetulnya hanya aksesoris industri semata dan tidak inheren dalam keberadaan musik itu sendiri). Musik menurut John Cage adalah sebuah hubungan antara ketiganya: komposer adalah seorang tukang kayu, ia hapal betul seluk beluk perkayuan, mulai beda antara mahagoni hingga jati, juga tekstur dan kepadatan. Ia jugalah yang memiliki visi akan menjadi apa kayu tersebut. Musisi adalah pengrajin, ditangannya kayu bisa menjadi kursi atau benda seni. Sedangkan pendengar adalah pengguna atau pembeli hasil olahan kayu tadi, memilih sesuai selera dan kebutuhan. Ketiganya hidup di dunia yang berbeda, dengan pemaknaan yang diskontinyu satu sama lain. Namun yang kemudian terjadi adalah, pendengar (orang yang paling akhir bersentuhan dengan sebuah karya musik) selalu memiliki keinginan berlebih untuk memaknai musik – alhasil lahirnya genre, sejarah musik, pemilahan klasik dan kontemporer, dan istilah-istilah seperti musik rakyat hingga musik eksperimen. Bisa saja, visi sang komposer sama sekali tidak tersentuh oleh pemaknaan pendengar – tapi itu tidak jadi soal, karena setelah tercipta, musik, (seperti berbagai gagasan lain yang lahir di muka bumi: seni, filsafat, ilmu pengetahuan) – memiliki jalan dan sejarahnya sendiri.
John Cage paham betul bahwa manusia (baik dari golongan komposer, musisi ataupun pendengar) sebaiknya jangan terlalu ambil pusing tentang musik. Karena seperti kayu – musik akan tetap mengada, dengan ataupun tanpa persentuhan manusia. (Cage hanya protes pada satu hal, ia tidak setuju pada istilah musik eksperimen, karena bagi seorang komposer dan musisi, ekperimen dilakukan dalam proses pembuatannya – sedangkan musik yang dihasilkan (seganjil apapun) adalah bentuk matang dari proses tersebut). Pandangan tadi – bahwa musik akan tetap mengada walau tanpa persentuhan dengan manusia – diungkapkan Cage dalam tulisan yang ia beri judul “The Future of Music: Credo”. Ia mengemukakan gagasan tentang kredo musik ini pada tahun 1937 di sebuah perbincangan seni yang diorganisir oleh kurator musik Bonnie Bird, sedangkan bentuk cetaknya baru hadir 20 tahun kemudian sebagai brosur yang dibagikan pada pertunjukan George Avakian di Town Hall, New York. Dalam tulisan tersebut, Cage memaparkan bahwa keberadaan musik adalah alamiah – ia hadir bersama gerak alam semesta dalam bentuk bermacam suara (angin, desir ombak, kepakan sayap burung adalah bentuk alamiah dari musik). Juga hadir dalam bentuk dengung (noise), yaitu suara yang dihasilkan dari daya progresif manusia (bunyi mesin atau getaran elektromagnetik). Ungkapnya, “wherever we are now, what we hear is mostly noise. When we ignore it, it disturbs us. When we listen to it, we find it fascinating”.
Lalu, suara dan dengung bersinggungan dengan konsep musik yang didefinisikan sepihak oleh manusia. Kata musik menjadi definitif sebagai “bunyi terorganisir” dengan struktur dan pakem yang diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Berpijak pada kapasitas manusia untuk melakukan repetisi, musik pada akhirnya menemukan bentuk yang mapan, dengan aturan baku dan kesepakatan umum tentang harmoni, melodi, dan ritme. Aturan-aturan dan definisi musik seperti ini, menurut Cage, pada akhirnya mengalienasi musik dari kehidupan. Keberadaannya menjadi fungsi artifisial penggugah emosi yang dimainkan apabila diperlukan lalu dimatikan jika sudah bosan. Dengan ini, manusia telah mencapai fase terendah dalam pemaknaan terhadap musik. Keteraturan yang mengekang imajinasi bukan hanya menjangkiti pendengar, namun juga secara tidak sadar menjadi penghambat terbesar bagi kreativitas komposer dan musisi. Itulah sebabnya perkembangan musik hadir dalam fase yang tersendat, karena kebaruan yang hadir, jika tidak dianggap heretik, maka akan dikategorikan kedalam dadaisme, sebuah gerakan (komunikasi) seni yang begitu cair sehingga keberadaannya (dianggap) tidak akan menggangu pakem arus utama. Musik, di tangan manusia, beralih menjadi tongkat diktator – dengan nada-nada otoriter yang kita kenal dengan istilah pakem.
Gelagat perlawanan terhadap kepasifan manusia atas musik telah hadir sejak awal abad 20 melalui gerakan Futurisme yang digagas oleh Marinneti, Luigi Rusolo dan Balilla Pratella melalui pemasrahan diri manusia pada (dengung) mesin sehingga pada akhirnya kita mengenal konsep noise music. Bersandingan dengan futurisme, perlawanan dilakukan pula oleh Edgar Verese yang mendorong imajinasi musik hingga mencapai akar alamiahnya – karyanya berjudul Desert adalah sebuah rekaman orkestra alam yang menakjubkan. Kembali pada tokoh yang gagasannya mendasari tulisan ini, John Cage – nampaknya ia pun memiliki cara tersendiri untuk menunjukan perlawanan terhadap tirani musikalitas yang dihadapi oleh umat manusia. Sebuah cara yang menghadirkan penamaan baru dalam gagasan musik: yaitu musik kontroversial – karena perdebatan atas karyanya tidak hanya mencakup pakem nada, namun mengacu pada kredo dari musik itu sendiri dan menghadirkan kembali pertanyaan mendasar, what is music?.
Karya kontroversial Cage berjudul 4′ 33″ digubah pada tahun 1952. Karya ini menjadi gangguan bagi zona kenyamanan konseptual musik karena dalam komposisi ini, Cage memainkan hanya satu elemen dari musik, yaitu: silence (silence memiliki padanan kata sunyi, namun saya tetap menggunakan silence, karena kata “sunyi” walaupun memiliki arti yang sama, sangat riuh dengan beban emosional, silence dalam konteks ini memiliki sifat yang lebih netral). Ketika pertama kali karya ini dimainkan, tanggapan yang hadir beragam, mulai dari gerutu yang mengeluhkan ketidakjelasan konsep, kegelisahan untuk duduk diam selama komposisi dimainkan, kebingungan tanpa petunjuk, kegeraman khas musikolog yang terlalu banyak melahap teks-teks musik klasik, hingga senyum para pseudo-intelektual yang merasa langsung terhubung dengan komposisi aneh ini (senyum yang kemudian diakhiri dengan ungkapan, “ah magnificnet, a silent piece”). Komposisi 4′ 33″ membutuhkan pianis sekelas David Tudor untuk memainkannya. Sebagaimana seremonial konser tunggal pada umumnya, ia memasuki panggung, membungkuk, lalu duduk di depan piano. Dengan penuh khidmat dan penghayatan Tudor membuka lid piano, namun alih-alih menekan tuts, ia meletakkan jemarinya di pangkuan – lalu diam. Memasuki menit kedua ia menutup lid piano, membukanya, lalu kembali melakukan pertunjukkan diamnya. Pada akhir komposisi yang berdurasi selama 4 menit 33 detik tersebut, Tudor menutup lid piano, berdiri lalu membungkuk di depan penonton yang kebingungan. Menurutnya, hanya setengah dari pendengar yang memberikan tepukan, sisanya (mungkin) masih tenggelam dalam dillema eksistensial musikalitas.
Tidak membutuhkan waktu lama bagi 4′ 33″ untuk menjadi sorotan publik. Kritikus yang menolak kategorisasi 4′ 33″ sebagai sebuah komposisi berdedebat dengan kritikus yang mendukung 4′ 33″ sebagai sebuah komposisi. Ketika dimintai keterangan atas karyanya, Cage hanya memberikan keterangan singkat “the material of music is sound and silence” dan ia memilih untuk memainkan hanya salah satu dari kedua elemen tersebut. (Keterangan singkat ini sebetulnya adalah pencerahan, karena Cage dikenal dengan gaya kuliah nyentrik dan pernyataan-pernyataan monolog, dalam sebuah diskusi bisa jadi ia menjelaskan musiknya melalui puisi, bahkan seringkali ia telah menyiapkan jawaban, tidak peduli pertanyaan apa yang akan dilontarkan). Pengamat seni kemudian menyandingkan 4′ 33″ dengan lukisan “Soup Can” Andy Warhol sebagai sarkasme yang mengkritik kegamangan masyarakat paska perang dunia dua – tapi seperti halnya Warhol, pembacaan 4′ 33″ dapat ditarik lebih jauh dari sekedar kritik (permukaan) sosial. Menggunakan istilah Bergson, kita melihat bahwa yang dilakukan Cage adalah sebuah statement of disorder. Ia menyuarakan apa yang diusung oleh pada futurist empat puluh tahun sebelumnya, yaitu sebuah perlawanan terhadap pemaknaan musik. Dengan hanya memainkan silence, Cage menghadirkan anarki dalam konseptualisasi musik. Interpretasi dobrakan anarki ini dapat dilihat dari dua sisi: pertama, bahwa musik tidak terbatas, tapi manusialah yang membatasinya melalui bentuk persepsi. Kedua, melalui silence, Cage berhasil menghadirkan musik yang inheren dengan kehidupan yaitu suara (sound) dan dengung (noise) (karena pada dasarnya silence tidak pernah ada, bahkan ketika di ruang hampa udarapun detak jantung tetap terdengar). Pada sebuah dialog berjudul “Where are we going? and What are we doing?” (direkam pada tahun 1961), Cage mengungkapkan: Well, the grand thing about the human mind is that it can turn its own tables and see meaninglessness as ultimate meaning. Ia membuktikan bahwa (persepsi) tirani musik hanya dapat dikonfrontir dengan menghadirkan elemen oposisinya, silence: yang kerap dianggap meaningless dalam sebuah komposisi. Dan melalui 4′ 33″, Cage seakan-akan berucap (dengan senyum geli ciri khasnya) “selamat menikmati silence, dan gairah anarki yang hadir bersamanya”.

kontak via editor@antimateri.com

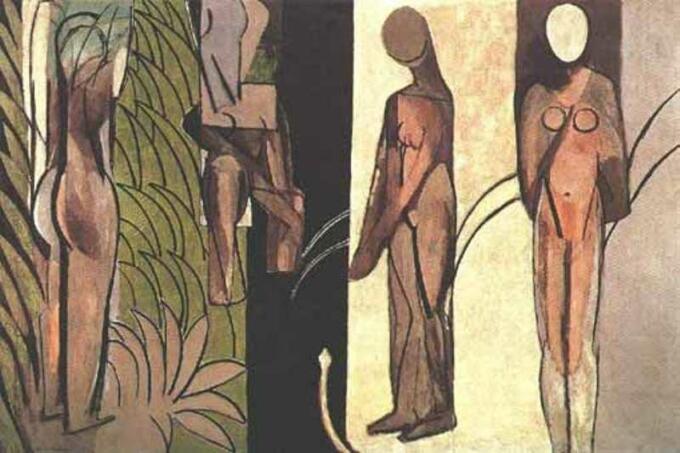






Resensi yg menggugah ‘tuk pemikiran & rasa yg baku (classic), dg filosofi perluasan elemen & materi yg futuristic menyegarkan kebekuan.