Epos Ramayana tidak perlu diuraikan terlalu panjang karena siapapun telah mengenal kisah ini – tidak terhitung berapa ratus ribu kali Ramayana di wejang ulang dalam berbagai versinya sejak Walmiki (वाल्मीकि; Vālmīki – dalam bahasa Sanskirt) menulisnya pada kurun waktu antara 500–100 sebelum masehi. Namun semerta-merta menyetujui frase di atas – bahwa Ramayana telah begitu kita kenal – adalah sebuah lelucon yang mengandung kritik diri: Ramayana digubah dalam 24.000 bait, terurai dalam 7 buku, dan dilantunan dalam 500 lagu. Lalu pada bagian mana kita mengenal karya pujangga besar tersebut?.
Dan ternyata ingatan kolektif – yang [seringkali] diturunkan secara serampangan – hanya merangkum garis besarnya saja. Epos Ramayana yang monumental mengisahkan tentang penyelamatan Dewi Shinta, Istri Sri Rama, yang diculik oleh Raja Raksasa, Rahwana. Dalam perjuangannya tersebut, Sri Rama dibantu oleh Kera Putih Bijaksana bernama Hanuman beserta anak buahnya. Di akhir cerita Sri Rama (tentu saja) menang, Dewi Shinta direbut kembali, dan Rahwana setengah mati dihimpit gunung (karena ternyata si Raja Raksasa tidak bisa mati). Dan setelah ditambah pembuktian kesucian Dewi Shinta melalui upacara bakar diri, akhirnya kebaikan berhasil dikukuhkan kembali dan kejahatan dikucilkan jauh di sudut cerita. Disinilah kebanyakan versi berakhir – karena akhir bahagia dengan kemenangan mutlak bagi kebaikan tidak menimbulkan geger paradoks kehidupan yang ditakuti semua orang – layaknya ceritera kanak-kanak, kita dibuat nyaman layaknya kisah cinta manis putri-putri kerajaan Disney.
 Namun epos Ramayana – seperti juga Mahabharata – bukanlah sebuah ceritera. Ia adalah ayat-ayat yang memiliki makna transendental sebagai upaya manusia dalam memahami berbagai aspek kehidupan – baik memahami diri, nilai, dan tatanan moral – menuju objek imanen di luar dirinya. Sehingga pemaknaan dalam epos Ramayana dan Mahabharata tidak pernah usai – dan memang uraian Ramayana tidak terhenti ketika Rahwana dikalahkan, setelahnya Sri Rama lantas berperang dengan melawan musuh-musuh yang lebih kuat, yaitu kedua anak kembarnya dan dirinya sendiri. Pemaknaan ulang inilah yang kemudian memunculkan banyak versi [ceritera] tentang Ramayana – di Indonesia sendiri setidaknya saya menemukan dua pemaknaan ulang dari kisah Ramayana yang sangat baik, yaitu Anak Bajang Menggiring Angin (Sindhunata) dan Kitab Omong Kosong (Seno Gumira Ajidarma). Dan layaknya kitab transenden lainnya, sebanyak apapun Ramayana ditulis ulang, ia akan memberikan makna sesuai dengan tujuan pengkajiannya.
Namun epos Ramayana – seperti juga Mahabharata – bukanlah sebuah ceritera. Ia adalah ayat-ayat yang memiliki makna transendental sebagai upaya manusia dalam memahami berbagai aspek kehidupan – baik memahami diri, nilai, dan tatanan moral – menuju objek imanen di luar dirinya. Sehingga pemaknaan dalam epos Ramayana dan Mahabharata tidak pernah usai – dan memang uraian Ramayana tidak terhenti ketika Rahwana dikalahkan, setelahnya Sri Rama lantas berperang dengan melawan musuh-musuh yang lebih kuat, yaitu kedua anak kembarnya dan dirinya sendiri. Pemaknaan ulang inilah yang kemudian memunculkan banyak versi [ceritera] tentang Ramayana – di Indonesia sendiri setidaknya saya menemukan dua pemaknaan ulang dari kisah Ramayana yang sangat baik, yaitu Anak Bajang Menggiring Angin (Sindhunata) dan Kitab Omong Kosong (Seno Gumira Ajidarma). Dan layaknya kitab transenden lainnya, sebanyak apapun Ramayana ditulis ulang, ia akan memberikan makna sesuai dengan tujuan pengkajiannya.
Gugatan Rahwana dalam Epos Ramayana
Lakon-lakon pewayangan, baik dalam Ramayana, Mahabharata ataupun kisah carangan, yang mengacu pada tulisan yang digubah sekian ratus tahun lalu, seringkali memiliki kesamaan dengan sikap dan perilaku yang dapat ditemui saat ini. Dari sini kita menemukan cermin realita: bahwa walaupun secara kasat mata kita selalu dihadapkan pada kubu positif dan negatif – melalui penggambaran hiperealita dari tokoh protagonis (digambarkan sebagai dewa-dewi yang santun, bijak nan rupawan), dan lawannya, tokoh antagonist (raksasa yang kasar, bengis, dan buruk rupa) – namun kedua kutub tersebut sama sekali tidak berada diam pada tempatnya.
Gambaran dinamis tokoh pewayangan tersebut sangat jelas diuraikan dalam kisah epos Ramayana – pembacaan gaya ini membuat Ramayana bisa kita nikmati seperti novel Dostoyevski yang sarat nilai psikologis. Rama yang merupakan sosok ideal merupakan simbol kebaikan – dengan penokohan Rama yang santun, bijak, sakti dan rupawan – adalah sebuah cermin dari nilai-nilai adiluhung manusia. Namun ternyata ia [bisa] menjadi tanpa ampun bagi Dewi Shinta dengan memintanya membakar diri untuk membuktikan kesuciannya, dan menjadi gelap mata akan kekuasaan setelah ia menduduki kembali tahtanya – melalui bait persembahan kuda, Rama menaklukan negeri manapun yang dilalui Kuda sucinya – sehingga dalam hal ini, simbol kebaikan bukan dihancurkan oleh Rahwana, tapi oleh kebaikan itu sendiri ketika ia meletakkan diri jauh di atas masyarakat yang harus dilindunginya. Melalui gambaran ini, Walmiki tidak berhenti pada titik bahwa Rama adalah titisan Wisnu, tapi juga membawa Rama kedalam labirin psikologis yang sarat dengan pertempurannya sendiri – mengingatkan kembali akan sebuah kredo yang sering kita dengar: bahwa manusia bisa tinggi layaknya dewa ataupun rendah seperti binatang.
Sedangkan Rahwana, sang Raja Raksasa yang bengis, dipercaya mewakili segala macam keburukan – dalam bahasa Sanskrit namanya berarti “yang menyebabkan tangis”. Namun dibalik pelanggaran norma dan tata nilai yang dilakukannya, khususnya dalam kasus penculikan Shinta, ternyata ia memiliki landasan logis (yang dapat dipertanggungjawabkan) melalui uraian sebab akibat berikut: Rahwana, raksasa yang terlahir dengan sepuluh kepala, memutuskan untuk melakukan pertapaan selama 1000 tahun. Setiap 100 tahun, ia akan memenggal satu dari kepalanya dengan tujuan untuk mengurangi unsur jahat dalam dirinya. Namun ketika kepala terakhir akan dipenggalnya, para dewa melarang dengan alasan bahwa Rahwana adalah penyeimbang dunia dan imbalan atas pengorbanannya tersebut – pengorbanan untuk menjadi simbol kejahatan – ia dijanjikan seorang bidadari bernama Dewi Setiowati. Disinilah persoalan menjadi pelik, karena ternyata Dewi Setiowati tidak langsung diberikan dalam wujud bidadarinya, namun akan dititiskan kedalam tubuh seorang manusia, yaitu Dewi Shinta. Sehingga tidak ayal lagi, ketika Rahwana melihat Shinta berjalan sendirian di Hutan, ia teringat akan istri yang dijanjikan kepadanya – Shinta yang tidak tahu apa-apa, menolak mentah-mentah karena telah menikah dengan Rama – sehingga dimulailah epos kisah cinta tragis ini. Tragis, karena ternyata setiap tokohnya – Rama, Shinta dan Rahwana – adalah korban dari alur ceritera kehidupan itu sendiri. Rasa-rasanya, dengan memberikan bukti yang lengkap dan pengacara yang handal, Rahwana bisa melakukan gugat atas pandangan semena-mena para pembaca atas dirinya.
Rahwana dan Paradoks Universal
Rahwana adalah penyeimbang dunia – namun tugas khususnya adalah penyeimbang Rama. Titik keseimbangan yang diutarakan oleh Walmiki ternyata dikemukakan juga oleh Anthony Giddens berabad kemudian: Giddens menyatakan bahwa struktur mempunyai dua fungsi yaitu (1) sebagai tempat untuk berinteraksi dan, (2) sebagai tempat pengekangan nilai. Konsekuensinya ketika dua kekuatan saling berinteraksi, maka struktur akan mengekang mereka pada titiknya masing-masing sebagai upaya untuk menciptakan keseimbangan – yang hanya dapat berubah bila terjadi perubahan mendasar, katakanlah melalui sebuah perang. Sehingga jika saja Rama dan Rahwana hidup pada abad 20, mereka dapat menyatakan dalam uraian teori yang rumit, bahwa penculikan Shinta tidak lain merupakan sebuah upaya untuk mengubah struktur. Namun yang menarik dalam sebuah perang – termasuk perang Rama dan Rahwana – aspek kebaikan (dan keburukan) hanya bersifat sebagai pembenaran, bukan tujuan sebenarnya – karena kita tahu, tujuan itu bernama Shinta (- atau minyak dalam roman perang modern).
Tarik menarik kebaikan dan kejahatan juga tergambar dalam tokoh lain dalam epos ini, diantaranya pada diri Wibisana dan Kumbakarna. Wibisana adalah adik Rahwana yang membelot pada kakaknya dan negerinya sendiri karena pergolakan konsep kebenaran dalam dirinya. Sedangkan Kumbakarna, juga adik dari Rahwana, bertarung melawan Sri Rama atas nama negeri dan kesetiaan adik pada kakaknya, walau sepenuhnya mengetahui timbangan kebenaran tidak memihak padanya. Kedua tokoh ini berada pada jajaran yang sama dengan Bisma dan Adipati Karna dalam Mahabharata – yaitu tokoh yang mendukung alur filsafat kenegaraan, yang juga memiliki penekanan [paradoks] tersendiri dalam epos pewayangan.
Sedangkan Hanuman, tokoh penting lainnya dalam epos Ramayana, merupakan penggambaran dari instrumen penegak kebaikan dan keadilan – ia merupakan senjata yang akan menghukum kejahatan – bangun darma yang ia pegang sampai titik penghabisan: sebuah hal yang tidak dapat dipertahankan oleh Rama dalam melaksanakan tugasnya kemudian – sajian ironi lain yang disajikan oleh Walmiki. Dan mengingat Hanuman tidak dapat membunuh Rahwana, maka ia tidak pernah jauh – di pengadilan, muncul di televisi, di tikungan gelap, di etalase mall, bahkan di tempat tidur tetangga. Rahwana menjelma menjadi sebuah paradoks universal yang diperangi oleh agama – pemegang nilai-nilai dan konsepsi kebaikkan – selama berabad-abad. Dan mungkin karena darmanya belumlah selesai, sehingga ia bersikeras untuk terus hadir di antara kebaikan dan keburukan [yang menghimpit setiap pilihan tindakan umat manusia].

kontak via editor@antimateri.com





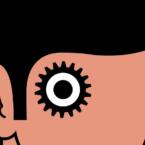


wow, sangat strukturalis, dialektik dan deterministik… Ali banget lah…
qiqiqi cepetan nulis aang, komen ajah :))