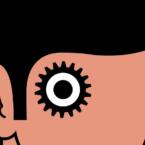Fiksi adalah cerminan realitas. Walaupun validitasnya dipertanyakan sebagai sumber sejarah, namun kegelisahan, emosi bawah sadar, ataupun geliat mimpi-mimpi fana, tumpah ruah di dalamnya. Kini, kamus kesusastraan modern menambahkan genre Climate Fiction (Cli-Fi), berisi deretan karya fiksi yang beririsan dengan wacana kritis ekologi. Kehadiran genre ini erat kaitannya dengan polemik perubahan iklim yang digadang-gadang sebagai ‘pemusnah massal’ abad 21. Dengan atau tanpa dukungan kajian saintifik, ragam novel bergenre Cli-fi bermunculan layaknya gerai cepat saji: banyak, dengan menu hampir serupa, yaitu kisah perusakan lingkungan yang berdampak malapetaka bagi bumi dan segala makhluk yang ada di dalamnya.
Secara pribadi, fiksi model ini tidak masuk dalam menu daftar bacaan, namun saran seorang Profesor yang mendorong membaca fiksi untuk mempertajam penulisan narasi (dalam tugas akhir saya), tentu tidak bisa diabaikan begitu saja. Saran tersebut menjadi menarik karena dua hal. Pertama, dalam belantara akademik yang kering kerontang, pendekatan lewat narasi ala fiksi adalah oase pelepas dahaga. Kedua, Cli-Fi yang disarankan, ternyata tidak terlalu mengecewakan–setidaknya berbeda dengan kebanyakan Cli-Fi yang sibuk menjual ketakutan pos-apokaliptik. Cli-Fi yang dimaksud berjudul Gun Island (2019) karya Amitav Ghosh; lewat ulasan atas Cli-Fi satu ini, dentuman kiamat dan akhir peradaban dalam fiksi, akan diulas secara singkat.
Kisah dalam Gun Island dituturkan oleh seorang kurator sekaligus penjual buku langka asal Bengali bernama Dinanath, atau ‘Deen’, sebagaimana ia dikenal di kalangan kawan-kawan bule-nya. Kala ia kembali ke tanah kelahirannya, secara tidak sengaja, Deen terseret ke ingatan masa lalu ketika ia mengunjungi Sundarbans–rawa bakau luas yang memendam mitos dan segala hal magis yang bisa dibayangkan. Di sana mitos tentang Manasa Devi, dewi ular yang menguasai segala jenis racun, masih hidup dengan subur, terlepas dari hitungan tahun yang telah menunjukkan 2019 setelah Masehi.
Deen masih ingat dengan jelas cerita dari masa kecilnya; tentang murka Manasa Devi atas para pedagang senjata yang beroperasi di wilayah Sundarbans, juga tentang perlindungan Manasa Devi pada sekelompok kecil orang yang selamat dari badai topan Bhola karena berlindung di kuilnya. Melalui penelusuran Deen tentang mitos di ‘pulau para pedagang senjata’, Ghosh dengan cerdik menyelipkan gambaran tentang berbagai persoalan: mulai kerusakan ekologi, naiknya permukaan air laut, hingga migrasi warga dari wilayah Sundarbans. Alhasil, Gun Island adalah salah satu Cli-Fi langka yang mendekati krisis ekologi dari sudut pandang mitos dan cerita magis–mengingat kebanyakan Cli-Fi berpijak pada narasi fakta ilmiah dan wacana perubahan iklim. Dalam Gun Island, Ghosh menawarkan hutan bakau Sundarbans sebagai latar sekaligus simpul utama ceritanya dan menjalin keterkaitan antara kosmologi, mitos, budaya, krisis lingkungan dan petaka manusia.
Hampir dapat dipastikan, tanpa kecerdikan ramuan mitos, Gun Island akan saya tinggalkan bahkan sejak bab pertama. Klaim ini didasarkan pada perbandingan dengan karya-karya Cli-Fi Amitav Ghosh sebelumnya, antara lain The Glass Palace (2002), The Hungry Tide (2004), dan The Great Derangement (2016), yang kurang memiliki daya tarik magis seperti Gun Island. Dalam The Glass Palace, Ghosh mengutuk kekuasaan kolonial yang membawa kerusakan lingkungan di negara-negara jajahannya. Walaupun ditilik dari sudut berbeda, yaitu ekologi, kritik bentuk ini telah dinyatakan Fanon secara lantang dalam Bumi Berantakan (1961). The Hungry Tide menyajikan kritik atas masyarakat teknologi, sedangkan The Great Derangement, Ghosh mengambil sudut semi non-fiksi untuk memaparkan gerakan kolektif anti-perubahan iklim. Mungkin karena fakta ilmiah dalam karya-karya sebelumnya dianggap kurang dapat menggugah pembaca, maka Ghosh meninggalkan gaya Cli-Fi konvensional dan terjun bebas ke alam mitos.
Pendekatan budaya dalam Cli-Fi ala Gun Island sebetulnya bukan hal baru, karena pada dasarnya Cli-Fi bertujuan untuk membangun pengetahuan serta budaya tentang kerusakan lingkungan yang tengah terjadi. Herold (2016) memberikan contoh cerita tradisional Polandia dan Jerman yang ‘peka’ pada perubahan iklim (sebagai contoh: kisah panen yang gagal karena pergeseran musim), menjadi salah satu tonggak dalam membangun kesadaran masyarakat akan perubahan lingkungan. Yang menarik adalah, walaupun Cli-Fi baru belakangan dimasukkan sebagai genre sastra, kisah tentang krisis lingkungan bukanlah sesuatu yang asing dalam dunia kesusastraan.
Dimock (dalam Bellamy, 2018) menyebut bahwa penderitaan akibat bencana alam telah tertuang bahkan dalam epik Gilgamesh (sekitar 2100 sebelum Masehi/BC). Simak saja bait berikut dalam the Lament for Urim (85-94):
“The woman, after she had composed her song (?) for the tearful balaj instrument, herself utters softly a lamentation for the silent house: “The storm that came to be — its lamentation hangs heavy on me. Raging about because of the storm, I am the woman for whom the storm came to be. The storm that came to be — its lamentation hangs heavy on me. The bitter storm having come to be for me during the day, I trembled on account of that day but I did not flee before the day’s violence. Because of this debilitating storm I could not see a good day for my rule, not one good day for my rule.”
Atas dasar pijakan tersebut, Bellamy (2018) berujar, “this [Cli-Fi] is an ancient genre about the beginnings and endings, with lineage longer, diverse, and more tenacious than we think”.
Namun, dalam perkembangannya, upaya berlebihan para penulis Cli-Fi untuk menjadikan karyanya sebagai ‘science communication’ dalam diskusi publik perubahan iklim (Herold, 2016), menjadikan genre ini menjadi seragam dan kurang warna–terlebih jika dibandingkan dengan genre Sci-Fi yang lebih liar dan terbuka; atau open-ending. Tabak (2019) menyatakan dua alasan mengapa Cli-Fi menjadi genre yang begitu ‘canggung’. Pertama, karena kiamat yang digambarkan (seperti bumi yang sekarat karena kekurangan oksigen) adalah persoalan generasi yang akan datang, dan bukan sekarang. Kedua, Cli-Fi yang berpijak pada fakta ilmiah yang penuh kepastian tidak mampu membangun paratext–sebuah interpretasi multi makna yang mampu menyentuh imajinasi pembaca.
Oleh karenanya, keputusan Ghosh untuk bermain dengan kosmologi dan mitos dianggap tepat, karena untuk membangun paratext dan imajinasi (tentang kiamat, atau apa pun itu), dibutuhkan pengetahuan tentang mitos, epos, dan berbagai bentuk kisah lain yang terendap dalam relung-relung ingatan kolektif masyarakat (Bellamy, 2018). Dengan kata lain: bahkan demi membuat kiamat versi manusia modern, diperlukan mitos untuk membangun kesadaran. Jika ketakutan reliji sudah usang, maka dibutuhkan ketakutan saintifik.
Sumber Bacaan:
Bellamy, B. R. 2018. Science Fiction and the Climate Crisis. Science Fiction Studies, 45 (3): 417-419.
Gosh, A. 2019. Gun Island. Penguin Hamish Hamilton.
Herold, E., Farzin, S., & Gaines, S. M. 2016. Between Fact and Fiction: Climate Change Fiction. Science Fiction Studies, 43 (3): 609-611.
Tabak, E. D. 2019. Science in Fiction. RCC Perspectives, 4 (Communicating the Climate from Knowing Change to Changing Knowledge): 97-104.
The Lament for Urim, ETCSL Translation.
Gambar Muka: Pablo Ruis Picasso, Joan Ponç

kontak via editor@antimateri.com