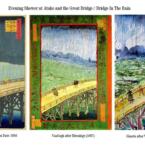Puisi, sebagaimana karya seni lainnya, tak terlepas dari keberadaan sebuah objek. Dalam sejarah seni dan literatur, beberapa objek lantas melekat pada nama seniman terkenal, sebut saja cyprus yang menjadi icon tersendiri bagi Van Gogh, mimpi alam bawah sadar bagi Dali, rembulan dalam stanza-stanza Lorca, kecoa pada karya Kafka, hingga Pipa Cangklong (yang bukan pipa) sebagai karya terkenal Magritte. Namun, kerap kali objek sebagai sebagai benda atau perihal yang didalami oleh seniman, kehilangan makna aslinya karena interpretasi sang seniman. Sebut saja cyprus yang menjelma simbol kematian dalam lukisan-lukisan Van Gogh, atau kecoa yang menjadi metafora ketidakberdayaan manusia dalam karya Kafka. Alhasil, walaupun memiliki fungsi yang esensial, objek dalam karya seni tidak lain sebatas medium penerjemah gagasan abstrak sang seniman – dengan kata lain, makna sebuah objek telah mati ketika ia jatuh di tangan seorang seniman (alterasi paling jelas terpampang dalam lukisan pipa Rene Magritte, lukisan ini mengukuhkan kebebasan seniman dalam mencipta makna layaknya dewa). Melihat gelagat ini, Barthes seperti ingin membalaskan dendam jajaran objek yang dibunuh maknanya. Ia lalu mengutarakan maklumat pahit bahwa seniman pun mati ketika karyanya sampai ditangan khalayak luas. Kini, ditambah dengan maraknya industrialisasi dan riuhnya dunia maya: objek, gagasan dan makna, dibunuh beramai-ramai di halaman sosial media. Lalu untuk apa mendalami puisi objek penyair Jerman Rilke dimasa antah berantah ini?. Jawaban paling tepat adalah, kepingin saja. Sedangkan jawaban yang dibuat seperti tepat adalah: agar tidak tenggelam dalam ironi. Frase ini diambil dari ungkapan Rilke dalam Letters to a Young Poet yang berbunyi “irony: Do not let yourself be governed by it” – dan tidak ada ungkapan yang lebih tepat untuk menggambarkan jiwa jaman masa kini selain kata ironi.

Rainer Maria Rilke adalah penyair Jerman kelahiran Bohemian yang berkiprah pada peralihan abad 19 ke abad 20. Karena banyak puisinya digubah dalam bahasa Jerman, Rilke kemudian dikenal sebagai maestro penyair lirih dalam bangun kesusastraan Jerman. Puisi pertamanya diterbitkan pada tahun 1894 dengan judul Leben und Lieder (Life and Songs), namun dapat dikatakan ia baru dikenal secara luas setelah publikasi antologi Das Stunden-Buch (The Book of Hours) yang diterbitkan antara tahun 1899 hingga 1903. Tema utama dalam The Book of Hours adalah pandangan personal Rilke tentang Tuhan dan agama – menurutnya, religion is the art of those who are uncreative. Atas dasar pandangan ini, ditambah pengaruh Friedrich Nietzsche yang kental, ia menjelajahi labirin yang terbentang antara manusia dengan Tuhan. Atas bentuk penuturannya yang liris dengan penggunaan bait panjang layaknya Iliad dan Odyssey karya Homer, The Book of Hours dinyatakan sebagai antologi yang menggerakan kebangkitan Neo-klasik di Eropa. Sedangkan dari sudut tema, irasionalitas serta eksposisi emosi yang banyak diangkat Rilke kerap disandingkan dalam jajaran Neo-romaticism. Namun Rilke nampaknya tidak berambisi untuk memegang teguh gelarnya, baik sebagai pionir neo-klasik ataupun neo-romanticism. Hal ini ditunjukkan (secara acuh tak acuh) dengan pengembangan gaya baru dalam puisi-puisi selanjutnya. Gaya lirih yang menempatkan Rilke di posisi utama penyair neo-klasik dan neo-romanticism, baru digunakan kembali dalam penulisan dua antologi pamungkas sekaligus pencpaian tertingginya, yaitu: Duineser Elegien (Duino Elegies) (1922) dan Sonette an Orpheus (Sonnets to Orpheus) (1922). Disini, ia kembali mengumandangkan genderang perang, kali ini dengan para malaikat yang menurutnya adalah manifestasi dari teror – Every Angel is terror. And so I hold myself back and swallow the cry of a darkened sobbing. Empat tahun setelah publikasi kedua antologi tersebut, Rilke meninggal karena leukemia yang dideritanya dan meninggalkan puisi terakhir yang ia tulis pada epitaph kuburnya. Rose, oh pure contradiction, delight of being no one’s sleep under so many lids.
Selain puisi, karya Rilke dapat ditemukan dalam bentuk novel (The Notebooks of Malte Laurids Brigge, 1910) dan (uniknya) dalam bentuk surat (Letters to a Young Poet). Pada tahun 1929, seorang penyair muda bernama Franz Xaver Kappus menerbitkan korespondensinya bersama Rilke dengan topik seputar saran tentang penulisan puisi dan buku yang disarankan untuk dibaca. Rilke, layaknya Idrus bagi Pram muda – bedanya, ketika Idrus dengan tanpa aling-aling berkata “Kau bukan menulis, kau berak!”, maka Rilke memiliki nada yang lebih halus dalam mengkritik tulisan sang penyair muda, ujarnya “ask yourself in the stillest hour of your night: must I write?”. Korenspondensi ini memiliki kekuatan tersendiri, khusunya pandangan Rilke tentang “tugas seorang penyair” yaitu untuk menghasilkan karya immaculate yang terbebas dari kekangan waktu. Selain karya-karya yang telah disebut, Rilke memiliki karya lain dalam bentuk monograph yang diterbitkan untuk kepentingan publikasi karya Auguste Rodin. Ia bekerja untuk Rodin di Paris antara 1902 hingga 1910. Pada kurun waktu inilah ia bersinggungan dengan karya impresionist seperti Paul Cézanne, Claude Monet dan Auguste Renoir, yang menghantarkannya pada sublimitas objek – sebagaimana topik yang diuraikan pada pembuka tulisan ini.

Dinggedichte atau poem of things atau puisi objek adalah gaya puisi yang dikembangkan dan dipopulerkan oleh Rilke. Dalam kesusastraan Jerman sendiri, dinggedichte telah berkembang sejak era romantik, dengan salah satu penggagasnya adalah penyair dan novelis Eduard Friedrich Mörike. Dinggedichte secara harfiah dapat diartikan puisi tentang benda (atau objek), namun berbeda dengan simbolisme, objek dalam Dinggedichte bukan sebuah medium metafora, namun merupakan inti dari puisi tersebut – mudahnya: jika puisi itu menceritakan tentang selembar daun, maka ia memang tengah bercerita tentang daun. Penyair Inggris, W. H Auden menyatakan bahwa tujuan dari dinggedichte adalah untuk menembus esensi terdalam dari sebuah objek, oleh karenanya puisi bentuk ini hanya dapat muncul dari pengamatan intens seorang penyair pada sebuah objek. Dalam menjelaskan puisi Rilke, Auden membandingkannya dengan karya Shakespeare: “While Shakespeare, for example, thought of the non-human world in terms of the human, Rilke thinks of the human in terms of the non-human, of what he calls Things (Dinge), a way of thought which, as he himself pointed out, is more characteristic of the child than of the adult” (Auden, 1939, Rilke in English, New Republic).
Bukan sebuah kebetulan ketika dinggedichte baru ditemukan pada puisi-puisi Rilke yang ditulis selama ia berada di Paris antara 1902 hingga 1910. Hal ini berkaitan dengan keterpukauan Rilke pada perspektif impresionisme yang berkembang kala itu. Dalam pendekatannya, impersionisme memiliki simpul yang sama dengan dinggedichte, yaitu: pendalaman pada objek. Mungkin karena ketertarikan pada simpul inilah kemudian Rilke mengubah gaya penulisan neo-klasiknya ke dalam bentuk dinggedichte. Impersionisme sendiri berpijak pada eksistensi objek yang kuat sebagaimana dikemukakan oleh Renoir – bahwa water lily adalah memang water lily. Impresionisme merupakan antithesis dari genre ekspresionisme yang begitu membebani objek dengan beban psikologis. Dengan menekankan pada eksistensi objek, impresionisme mencoba menggenggam apa yang tidak dapat digapai oleh para naturalist. Dinggedichte, dalam intensitas penghayatan pada objek, memiliki nafas serupa dengan impresionisme. The Panther adalah salah satu contoh puisi Rilke yang ditulis dengan gaya ini – sehingga ketika Rilke menulis tentang Panther, maka ia memang menulis tentang Panther. Lalu, mengapa baitnya begitu familiar dengan pengalaman manusia? Saya tidak menemukan jawaban atas pertanyaan ini secara eksplisit dalam karyanya, namun apabila kita menggali dua antologi puisi terakhirnya Duino Elegies dan Sonnets to Orpheus, ia seakan memberikan petunjuk pada kepingan teka-teki terakhir: maybe the birds will feel the expansion of air, in more intimate flight – bahwa intimasi kehidupan adalah sama, baik pada burung, dedaunan, ataupun manusia.
His vision, from the constantly passing bars,
has grown so weary that it cannot hold
anything else. It seems to him there are
a thousand bars; and behind the bars, no world.
As he paces in cramped circles, over and over,
the movement of his powerful soft strides
is like a ritual dance around a center
in which a mighty will stands paralyzed.
Only at times, the curtain of the pupils
lifts, quietly–. An image enters in,
rushes down through the tensed, arrested muscles,
plunges into the heart and is gone.
(The Panther, 1907)

kontak via editor@antimateri.com