Gagasan bahwa musik merupakan ekspresi emosi dan seni bukanlah hal baru. Plato, contohnya, telah memberi pembedaan antara mode Dorian[1] yang sangat cocok untuk menggugah jiwa kepahlawanan seorang tentara, dengan mode Ionian[2] lebih tepat untuk dimainkan dalam pesta minum-minum (Bonds, 2014). Dalam konteks fungsi, ekspresi musik sangat beragam, diantaranya kita mengenal rhapsody[3], psalmody[4], requiem[5], hingga threnody[6]. Dengan mengenal ragam ekspresi dan fungsi, musik tidak dapat lagi dimaknai dalam kerangka hiburan semata.
Lebih lanjut, Bonds (2014) menjelaskan bahwa setelah periode 1550 (yang ditandai dengan berakhirnya fase resonansi isomorphic[7]), musik berkualitas setidaknya harus mampu bersinggungan dengan lima perihal: (1) ekspresi (ketika musik secara fundamental mampu merangkum gagasan dan emosi); (2) bentuk (musik harus memprioritaskan struktur, baik yang berasal dari komposisi ataupun tradisi); (3) keindahan (keindahan harus menjadi inti dari sebuah musik); (4) otonomi (menekankan pada kebebasan ekspresi dan bentuk); dan (5) pengungkapan (memiliki pandangan bahwa musik adalah bagian dari pengetahuan, atau jalan menuju pengetahuan). Melihat kelima prasyarat di atas, kesadaran akan jauhnya jarak antara kualitas dengan realitas musik yang ada, semakin nyata di depan mata.
Musik dan Trauma Abad 20
Namun, adalah kesalahan fatal untuk menyatakan bahwa (kualitas) musik sudah mati sama sekali. Memasuki abad 20, sebuah pemahaman baru tentang musik yang diusung oleh para futurist[8] telah mengubah struktur fundamental dan menghasilkan noise (musik yang diproduksi dari bunyi mesin atau teknologi lain). Perubahan lain dikemukakan oleh Edgard Varese tentang konsepsi musik sebagai spasial–dimana musik bukan hanya tentang melodi atau harmoni, tapi sebuah tekstur bahasa baru yang dihasilkan dari berbagai suara (Varese dalam Burkholder, 2006). Dan sampailah kita pada Krzysztof Penderecki, seorang komposer asal Polandia yang mempraktikkan eksperimen noise sekaligus mengamini konsep musik Varese. Melalui karya berjudul Threnody to the Victims of Hiroshima, Penderecki menjadi epitome bagi komposer yang mampu membangun relasi antara musik dan emosi, khususnya trauma tentang sebuah mimpi buruk yang menjelma nyata.
(Krzysztof Penderecki, Threnody to the Victims of Hiroshima)
Threnody to the Victims of Hiroshima merupakan karya Penderecki paling berpengaruh yang dianugrahi juara pertama UNESCO Tribune Internationale des Compositeurs pada tahun 1961. Threnody ini lantas menyejajarkan Penderecki dengan komposer (eksperimentalist) dunia lain seperti Arnold Schoenberg, Arthur Honegger, Karlheinz Stockhausen hingga John Cage (Bylander, 2004). Uniknya, tanpa harus memiliki telinga seorang musisi ahli, kita dapat mengetahui bahwa komposisi 4′33″ karya Cage beserta threnody karya Penderecki, merupakan dua dari musik paling ganjil yang lahir pada abad 20. Jika yang pertama menawarkan kesunyian sublim, maka yang kedua menampilkan kengerian traumatis. Kekuatan musikalitas kedua karya tersebut berada di barisan pertahanan terakhir dalam mempertahankan kualitas dan pemaknaan musik.
Morgan (1992) memberikan gambaran tentang threnody karya Penderecki sebagai berikut: “The work divides clearly into three parts, the second providing a contrasting middle section, the third returning to music that resembles the opening. The division between the first two sections is unambiguous change in texture and timbre…preceded by a long, sustained single note [solo cello] with diminuendo leading to five seconds of silence. The second and third sections overlap, the third beginning some eight seconds before the second ends. Walaupun Morgan mampu menjelaskan secara detil akan gerak dan tiga bagian dalam threnody karya Penderecki, namun komposisi tersebut hanya dapat dipahami apabila mendengarnya secara langsung. Sang komposer sendiri merasa kaget ketika mendengar threnodynya untuk pertama kali–ungkap Penderecki: “When Jan Krenz recorded it and I could listen to an actual performance, I was struck with the emotional charge of the work”. (Bylander, 2004).
Selain struktur dan bentuk, pemilihan judul memainkan peranan besar dalam pembuatan sebuah komposisi. Karya Panderecki sendiri semula berjudul 8’37” mengacu pada durasi threnody, namun kemudian diubah atas saran seorang kawan demi memperdalam sisi emosional dari threnody tersebut. Alhasil Panderecki memilih judul Threnody to the Victims of Hiroshima dan mendedikasikan karyanya bagi seluruh korban penghancuran bom atom. Judul ini memberi bobot signifikan karena pendengar dimanapun akan terhubung dengan tragedi kemanusiaan melalui gagasan emosional yang terangkum dalam pengalaman traumatis masa perang. Kasus ini memberikan contoh nyata tentang kekuatan judul dalam sebuah karya seni (baik musik ataupun seni lainnya) dan memunculkan asumsi utama bahwa judul yang efektif mampu membangun bingkai emosi yang ikut menentukan arah artistik karya tersebut.
Keberhasilan Penderecki tidak berhenti pada threnody Hiroshima. Pada tahun 1967 ia diundang untuk menggubah komposisi untuk peringatan korban di kamp konsentrasi Auschwitz. Kiprah (musikalitasnya) juga dikenal dalam pergerakkan anti-komunis di Polandia melalui karya yang berjudul Polish Requiem (1981). Karya lainnya mencakup opera dan symphony yang telah dipentaskan berulang kali. Namun diantara karyanya, Threnody to the Victims of Hiroshima tetap menjadi tonggak keberhasilan bagi Penderecki. Mungkin karena musik dan trauma yang begitu mencekam, threnody Penderecki kerap digunakan sebagai musik latar film horror, seperti The Shining karya Stanley Kubrick.
Ketika mendengarnya kembali, muncul sebuah kesadaran yang menggangu: bahwa threnody karya Panderecki adalah peringatan bahwa pada satu titik manusia mampu memunculkan horror yang lebih mencekam dari film manapun. Namun, terlepas dari gambaran traumatik tersebut, karya Penderecki adalah satu diantara musik yang mampu bersentuhan dengan kelima prasyarat musik yang dikemukakan pada awal tulisan. Emotionally shocking adalah ungkapan yang seringkali muncul ketika seseorang pertama kali mendengar karya Penderecki. Ungkapan lainnya adalah disturbingly appropriate–sebagai sebuah pengakuan bahwa hanya seorang maestrolah yang mampu memunculkan tragedi dan trauma melalui musik dan noise, dan pendengar hanya mampu terbelalak ketakutan.
Sumber Bacaan:
Bonds, M.E. (2014). Absolute Music: The History of an Idea. New York: Oxford University Press.
Burkholder, J. P., & Palisca, C.V. (2010) Norton Anthology of Western Music. Vol. 3. New York: W. W. Norton & Company.
Bylander, C. (2004). Krzysztof Penderecki: A Bio-Bibliography. Westport: Preager
Morgan, R.P. (ed). (1992). Anthology of Twentieth-Century Music. New York: W.W. Norton & Company.
_______________
Keterangan:
[1] Mode Dorian memiliki ciri melankolis namun penuh harap, seperti halnya lagu-lagu tentang pahlawan
[2] Atau juga dikenal dengan skala major yang diperkenalan kembali oleh Heinrich Glarean pada tahun 1547
[3] Musik dalam satu gerak (one-movement) yang digunakan untuk mengiringi puisi epik; pada abad 19, rhapsody menjadi gaya utama para musisi dengan karakter musik yang mengalir dan kerap ditandai oleh mood nada yang kontras
[4] Musik untuk mengiringi pembacaan kitab suci
[5] Musik yang digunakan dalam misa kematian
[6] Musik atau ode untuk mengenang seseorang yang telah meninggal
[7] Definisi Phytagoras tentang Resonansi Isomorphic adalah: the ratios that govern the intervals of music are the same ratios that govern the structure of the universe at every level, from that of the individual human to that of the cosmos as a whole.
[8] Musik Futurist dipengaruhi oleh perkembangan mesin dan teknologi, berkembang terutama di Rusia, Italia, Jerman dan Perancis pada awal pertengahan abad 20

kontak via editor@antimateri.com






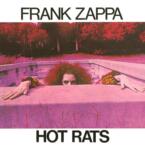

Warning: the song contains disturbing hidden massages ?
di rubbing ma siapa do?