Ketika sosial media mulai merebak, terdapat satu kata yang begitu mengganggu pikiran saya, yaitu kata “follow”. Hingga saat ini saya tidak habis pikir mengapa kata tersebut dipilih sebagai representasi bentuk keterhubungan antar subyek dalam dunia maya. Follow – memiliki padanan kata “ikut” yang memurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti “melakukan sesuatu sebagaimana dikerjakan orang lain”. Ada kesan pasif didalamnya – berbeda dengan kata friend (teman), follower selalu berada selangkah di belakang. Entah apakah ini sebuah kesengajaan atau tidak, tapi bagi saya – kata adalah pilar dari bahasa yang mampu membentuk realita. Ketika subyek menerima kata tanpa syarat, konsekuensinya adalah ia kehilangan kapasitas untuk bertanya. Tapi saya bisa salah – mungkin saja konteks kata follow saat ini sudah berubah dan memiliki makna lain. Atas praduga positif ini, saya lalu membuka-buka kamus dan referensi terkait kemungkinan adanya perubahan makna. Follow dalam media sosial memang bukan aktivitas fisik, namun mengacu pada persetujuan (consent) untuk saling berbagi informasi satu sama lain[1]. Dari definisi ini saya agak sedikit lega, karena dalam konsep follow jaman sekarang, masih terdapat kata “saling berbagi informasi”, yang artinya masih ada ruang untuk berdiskusi dan pertukaran gagasan tidak berjalan satu pihak. Walaupun saya sadar sepenuhnya bahwa rasa lega ini adalah sebuah penyangkalan, karena pada kenyataannya kontestasi pemikiran atau perdebatan dalam sastra di ranah media sosial saat ini adalah barang mewah nan langka, sedang sisanya adalah pembentukan konsensus belaka. Dan tidak ada yang lebih membosankan dari sebuah percakapan satu pihak dimana semua mengangguk setuju[2].
“Lalu bagaimana sih yang namanya perbincangan bermutu?”, celetuk seorang kawan yang melihat saya mencak-mencak sendiri di depan layar komputer ketika membaca pemberitaan berlebihan atas seorang tokoh politik atau figur agamawan yang hanya bisa berbicara dalam bahasa cercaan. “Pastinya perbincangan itu memiliki bobot tidak sembarang dan santun terhadap perbedaan”, jawab saya atas celetukan tadi. Contoh dari perbincangan seperti itu banyak sekali – terangkum dalam manuskrip klasik, tumpukan buku, lipatan-lipatan surat hingga terekam dalam media audio visual. Dialog tentang logika perang antara warga Melos dan perwakilan Athena adalah salah satu diantaranya. Lalu dialog Sri Mahaketu (raja Hastina) dengan dewa dan berbagai orang bijak dalam Kitab Sutasoma. Jika dua contoh tadi terlampau adiluhung, mari kita simak contoh yang lebih kontemporer. Terdapat dokumen surat menyurat antara Sigmund Freud dan Albert Einstein yang memperbincangkan tentang perdamaian. Atau diskusi menarik tentang sifat alamiah manusia antara Michel Foucault and Noam Chomsky. Juga perdebatan menarik antara Umberto Eco dan Kardinal Carlo Maria Martini tentang perbedaan mendasar antara logika sekuler dan logika agama dalam buku berjudul “Belief or Non-Belief: A Confrontation” yang diterbitkan pada 1997 (didalamnya terangkum diskusi sengit tentang hari akhir, kehidupan dan kematian, posisi wanita di mata gereja juga tentang permasalahan etika)[3]. Para filsuf kontemporer ini memperbincangkan permasalahan utama pada jamannya dari sudut pandang yang berbeda, sehingga jangan harap ada konsensus “cuma-cuma” di dalamnya.
Jika contoh diatas masih kurang membumi, mari kita cari sandingan di dunia populer. Salah satu yang paling menonjol adalah film garapan Luois Malle berjudul My Dinner with Andre (1981). Adegan dalam film ini secara harfiah hanya satu: yaitu adegan makan malam Wally Shawn, dengan kawan lamanya, Andre Gregory. Film berdurasi satu jam lima puluh satu menit ini mengagetkan, bukan bagi pemirsa, tapi bagi Louis Malle sendiri. Ia tidak menyangka bahwa film ini mampu mengundang banyak penonton – pada awalnya ia hanya bertujuan membuat sebuah film “yang terhindar dari klise”, namun nampaknya film ini menyentuh alam bawah sadar masyarakat yang terjebak dalam realitas tanpa makna. Jika film ini masih asing, coba kita ingat kancah 1990an. Ada sebuah film nyeleneh dengan peran yang sama-sama antik (baca: idiotik) yaitu Beavis and Butthead. Baiklah, bagi penyuka high-art mungkin film ini akan terlewatkan, namun bagi penggila musik, duet ini adalah salah satu icon komentator musik rock legendaris di era 1990an. Beavis dan Butthead adalah contoh dari perbincangan sarkas anak muda yang diwakili oleh dua kata yang mewakili segalanya, yaitu “suck” atau “cool”. Tidak banyak diksi yang bermunculan didalamnya (bahkan seringkali komentar hanya diwakili suara tawa yang off-beat), namun jika kita ingin memahami jiwa sebuah generasi, maka mereka adalah contoh nyata bagaimana sebuah generasi dibesarkan dalam kebosanan dan mimpi utopis tentang ketenaran. Perbincangan bagi mereka adalah sebuah eskapisme dari rasa bosan yang malah menghadirkan bentuk kebosanan yang lain.
Sedikit keterlaluan memang ketika menyandingkan pemikiran berbagai filsuf dengan genre pop ala Beavis dan Butthead. Namun dengan mengambil resiko ini sebuah benang merah terlihat dengan jelas: bahwa perbedaan dalam dialog adalah sebuah keniscayaan. Dialog bukan hanya pertemuan dua orang, namun kehadiran dua gagasan yang berbeda. Bukanlah dialog namanya jika satu dan yang lain saling sepaham. Oleh karena itu, fitur utama dalam sebuah dialog adalah bagaimana gagasan-gagasan yang berbeda saling bertanya dan menjawab. Dengan prasyarat ini, maka setiap dialog dimulai dari sebuah ketidaksepahaman. Dalam hal ini Beavis dan Butthead lebih maju ketimbang seorang followers tokoh inetektual yang tahu tentang berbagai macam teori. Setidaknya, kedua anak muda kurang kerjaan ini berani berkata “suck” pada grup musik yang tidak disukainya (disusul dengan argumen yang terkadang “sangat ajaib”). Namun Eco dan juga Martini menekankan bahwa pernyataan tidak setuju haruslah otentik – dalam arti ia bukanlah hasil dari kesepakatan semu apalagi hasil mengekor. Dari sinilah frase perbincangan antara dua manusia bebas berasal: bahwa ketika dua orang berdialog, maka selayaknya ia menanggalkan seluruh gelar dan jabatan, dengan demikian pemikirannya sebagai manusialah yang akan hadir[4].
Karena didasarkan pada adanya perbedaan, maka setiap dialog (atau perbincangan) yang baik harus beretika. Eco mengungkap bahwa agar sebuah dialog berguna, “kita harus menelusuri subyek-subyek dimana kita tidak bisa lagi menemui kesamaan pendapat” – sehingga kita akan mampu mengenali batasan sejauhmana sebuah pemikiran dapat kita utarakan. Sebagai contoh, tidak selayaknya memaksakan pemahaman tentang Roh Suci pada individu diluar komunitas agama. Pemahaman atas batasan ini menghindarkan kita dari pemaksaan kehendak dan gagasan pada subyek lain. Hal inilah yang kerap hilang dalam dialog atau perbincangan ditengah masyarakat saat ini. Batasan, dimanapun adalah wilayah yang berbahaya, sehingga tanpa adanya pemahaman atas batasan ini, maka sebuah dialog rentan menjadi ajang caci maki. Dalam My Dinner with Andre, terdapat sebuah kutipan menarik: We can’t be direct, or we end up saying the weirdest things. Ironis memang bahwa dialog dalam film yang dibuat hampir tiga dekade yang lalu masih relevan dengan kondisi saat ini (atau bahkan lebih buruk). Dan yang lebih buruk lagi adalah: orang yang “mengatakan hal-hal aneh” jumlahnya jadi berlipat ganda karena fenomena follow-memfollow dilakukan tanpa pikir panjang. Dihadapkan pada kenyataan ini, sebuah pil pahit harus kita telan: bahwa perbincangan antara manusia bebas dalam media sosial saat ini adalah sebuah kemewahan yang sangat langka. Mungkin kita harus menunggu sebuah gairah dimana aksi saling follow, berubah menjadi aksi saling meng-unfollow. Tapi itupun harus dilakukan secara otentik.
Keterangan:
[1] cambridge dictionary
[2] Kutipan terkenal dari filsuf renaisan asal Perancis, Michel de Montaigne
[3] Eco, Umberto dan Kardinal Martini, 1997, Dua Khotbah dari Iman: Sebuah Pertentangan, Jalasutra: Jakarta
[4] Walaupun hal ini bersebrangan dengan konsep komunikasi Habermas, yang menjelaskan bahwa tidak mungkin seseorang dapat terbebas sepenuhnya dari jejaring gagasan dan labirin ruang sosial

kontak via editor@antimateri.com

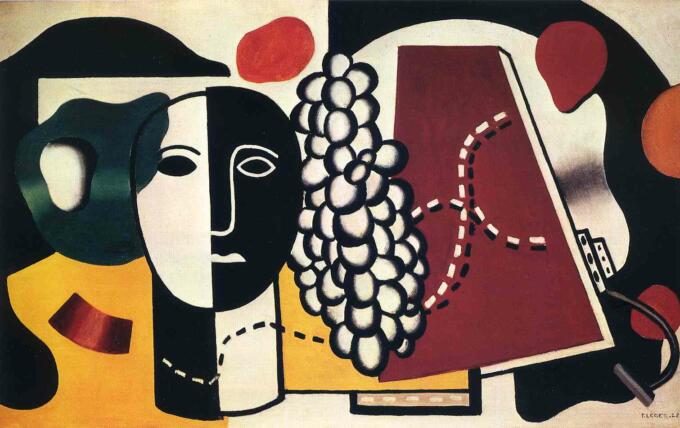






Terima kasih atas artikel yang sangat menghibur Teh Ali 🙂
‘Follow’ itu menurut saya sebenarnya berarti ‘Stalking’ secara implisit dalam konteks sosmed. Stalk=Menguntit, menguntit = mengikuti secara diam diam dalam rangka mengobservasi. Banyak lho yang punya akun sosmed kedua yang didedikasikan untuk kegiatan stalking ini (saya sih cukup pakai akun utama saja hehe).Kegiatan saling berbagi ini kadang kala tidak terjadi, karena akun khusus stalking ini tidak memiliki isi apapun dan dijadikan alat data mining amatiran untuk dijadikan bahan gosip intra grup teman sepermainan…atau untuk memprospek calon teman kencan yang ditemui secara online.
Hehehehe