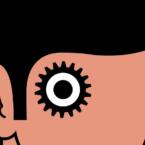Tahun 1932, merupakan jaman tak menentu arah. Konflik besar yang disebut sebagai Perang Dunia I memang telah lama usai, namun perang dan kehancuran tetap membuntuti bagai mimpi buruk di siang hari. Kondisi ini, rupanya begitu mengganggu bagi seorang pakar sains kelas dunia, Albert Einstein. Ia, kemudian melayang sebuah surat kepada pakar kelas dunia lainnya dari bidang psikoanalisis, Sigmund Freud, untuk mencari jawab atas empat pertanyaan penting: (1) Apakah ada cara untuk membebaskan umat manusia dari ancaman perang?; (2) Bagaimana mungkin ‘klik kecil’ [elite politik] membengkokkan keinginan mayoritas, yang akan kalah dan menderita, untuk melayani ambisi mereka?; (3) Bagaimana klik ini berhasil dalam membangkitkan antusiasme liar, bahkan membuat banyak rela berkorban untuk mereka?; dan terakhir, (4) Mungkinkah mengendalikan evolusi mental untuk membuat manusia mampu melawan psikosis kebencian dan kehancuran?–empat pertanyaan, yang rasanya, mampu menyentuh dasar dari segala bentuk konflik
Einstein memberi tajuk pada surat tertanggal 30 Juli 1932 dengan sebuah pertanyaan mendasar: Why War? Dalam surat tersebut, ia memberikan pandangannya atas upaya penghentian ‘konflik antar negara yang kerap ditangani secara dangkal dengan hanya menyentuh masalah administratif semata’. Bisa jadi ia gemas dengan berbagai bentuk perjanjian internasional juga organisasi hukum internasional–yang seharusnya menjadi acuan dalam penyelesaian konflik dan kekerasan namun malah di atur oleh tekanan elite (ekstrayudisial). Ujarnya (surat Einstein dapat dilihat pada halaman unesco.org):
“..As one immune from nationalist bias, I personally see a simple way of dealing with the superficial (i.e. administrative) aspect of the problem: the setting up, by international consent, of a legislative and judicial body to settle every conflict arising between nations. Each nation would undertake to abide by the orders issued by this legislative body, to invoke its decision in every dispute, to accept its judgments unreservedly and to carry out every measure the tribunal deems necessary for the execution of its decrees. But here, at the outset, I come up against a difficulty; a tribunal is a human institution which, in proportion as the power at its disposal is inadequate to enforce its verdicts, is all the more prone to suffer these to be deflected by extrajudicial pressure. This is a fact with which we have to reckon; law and might inevitably go hand in hand, and juridical decisions approach more nearly the ideal justice demanded by the community (in whose name and interests these verdicts are pronounced) in so far as the community has effective power to compel respect of its juridical ideal. But at present we are far from possessing any supranational organization competent to render verdicts of incontestable authority and enforce absolute submission to the execution of its verdicts. Thus I am led to my first axiom: the quest of international security involves the unconditional surrender by every nation, in a certain measure, of its liberty of action, its sovereignty that is to say, and it is clear beyond all doubt that no other road can lead to such security.
The ill-success, despite their obvious sincerity, of all the efforts made during the last decade to reach this goal leaves us no room to doubt that strong psychological factors are at work, which paralyse these efforts. Some of these factors are not far to seek. The craving for power which characterizes the governing class in every nation is hostile to any limitation of the national sovereignty. This political power-hunger is wont to batten on the activities of another group, whose aspirations are on purely mercenary, economic lines. I have specially in mind that small but determined group, active in every nation, composed of individuals who, indifferent to social considerations and restraints, regard warfare, the manufacture and sale of arms, simply as an occasion to advance their personal interests and enlarge their personal authority.”
Mengacu pada uraian di atas, terlihat jelas bahwa kekecewaan Eisntein pada malfungsi sistem internasional telah membawanya untuk masuk ke dalam lapisan lain dari perspektif perang dan kehancuran, yaitu faktor psikoanalisis. Dan tidak ada orang yang lebih tepat untuk memberikan penjelasan tentang faktor satu ini, daripada sang pionir psikoanalisis sendiri, Sigmund Freud. Surat balasan diterima Einstein dua bulan kemudian (September 1932), dan tentu saja, langsung menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan. Jawaban detail Freud menjadi jembatan untuk memahami fenomena sosial politik dari sudut psikoanalisis–sebuah sudut yang menurut Einstein “perlu dikenali untuk mencari cara agar perang dan kekerasan dapat dihindari”. Tanpa panjang lebar, berikut adalah rangkuman singkat dari surat sang pakar psikoanalisis tentang perang hingga kebencian psikosis. Surat lengkap dapat dilihat pada halaman unesco.org.
Freud mengawali penjelasan dengan mengurai konsep kekuatan dan kekerasan, yang keduanya walaupun memiliki antinomi tersendiri, sangat mudah untuk membuktikan bahwa baik kekuatan ataupun kekerasan, saling bersinggungan dan mempengaruhi alur evolusi satu sama lain. Contoh nyata dapat ditemukan dalam penyelesaian konflik antara manusia dan manusia, yang pada prinsipnya, dapat diselesaikan dengan menggunakan kekerasan. Hal yang sama terjadi di dunia hewan (mengingat manusia adalah salah satu di antaranya); bedanya, manusia rentan pula pada konflik bentuk lain: mulai dari silang pendapat, hingga konflik pemikiran [abstrak], yang tampaknya membutuhkan penyelesaian dengan metode lain. Penyempurnaan ini, bagaimanapun, merupakan perkembangan yang terlambat karena keduanya (kekerasan dan kekuasaan) terlanjur mendefinisikan segala bentuk relasi konflik juga penyelesaiannya. Terkait relasi antara kekerasan dan hukum [internasional], Freud memberikan sebuah argumen unik, yaitu dengan mendefinisikan “hak” (yaitu hukum) sebagai kekuatan komunitas. Namun jangan lupa, bahwa dalam setiap bentuk “kekuasaan” terdapat pula kekerasan. Ia lalu memberikan gambaran transisi dari kekerasan kasar ke penegakkan hukum yang hanya mungkin terjadi jika persatuan mayoritas telah stabil dan bertahan lama. Dengan kata lain, harus terdapat keseimbangan terlebih dahulu–dan inilah yang tidak ditemukan dalam konteks hukum internasional [saat itu].
Penjelasan tentang hukum dan komunitas, memberi jalan pada penjelasan Freud tentang keberadaan sebuah otoritas tertinggi. Melalui konsep tersebut, Freud mengungkap fakta bahwa “pelaksanaan kekerasan tidak dapat dihindari ketika kepentingan yang bertentangan dipertaruhkan”. Sejarah dunia mengindikasikan hal ini, bahwa perang kerap berakhir dengan penjarahan atau penaklukan, kejatuhan disisi yang kalah dan otoritas mutlak bagi pemenang. Otoritas, dalam hal ini, menjamin adanya sebuah stabilitas. Poin ini mengungkap sebuah paradoks: di satu sisi kita harus mengakui bahwa perang mungkin berfungsi untuk membuka jalan menuju perdamaian tak terputus yang kita inginkan; namun disisi lain, dalam praktiknya, tujuan ini tidak akan tercapai, karena sebuah kemenangan hanya berumur pendek (unit yang baru dibuat runtuh sekali lagi, umumnya karena tidak ada kohesi sejati dalam masyarakat yang dilekatkan oleh kekerasan).
Poin terakhir yang diangkat Freud adalah insting kekuatan hidup dan kematian dalam diri setiap manusia. Hal ini ia angkat sebagai respons atas pandangan Einstein tentang “betapa mudahnya menginfeksi manusia dengan demam perang yang didorong oleh naluri aktif untuk membenci dan menghancurkan”. Jawaban untuk pernyataan ini, lantas diurai sang pionir psikoanalisis melalui penjelasan dua jenis naluri manusia: (1) naluri yang melestarikan dan menyatukan, yang kita sebut “eros”; dan (2) naluri untuk menghancurkan dan membunuh “thanatos”, yang kita asimilasi sebagai naluri agresif atau destruktif. Kedua naluri ini adalah aspek polaritas, ketertarikan, dan penolakan abadi yang hadir di setiap diri manusia (tetapi kita harus berhati-hati dan tidak terjebak dalam konteks baik dan jahat. Masing-masing naluri ini sama pentingnya dan semua fenomena kehidupan berasal dari stimulus mereka, baik berjalan beriringan ataupun berlawanan; dan manusia ditakdirkan untuk merangkum polar oposisis in dalam dirinya). Berpijak pada dua naluri ini, upaya manusia dalam mencapai perdamaian selalu berada dalam sebuah lingkaran tanpa ujung. Karena seringkali, naluri [eros dan thanatos] berbicara lebih keras dari rasio [reason]. Namun, Freud mengindikasikan sebuah titik terang melalui pernyataan berikut:
The psychic changes which accompany by the process of cultural change are striking, and not to be gainsaid. They consist in the progressive rejection of instinctive ends and a scaling down of instinctive reactions. Sensations which delighted our forefathers have become neutral or unbearable to us; and, if our ethical and aesthetic ideals have undergone a change, the causes of this are ultimately organic.
Dalam paragraf tersebut, Freud mengindikasikan bahwa melalui perkembangan kebudayaan (cultural change), naluri kekerasan dapat direpresi. Cultural development, lanjutnya, adalah metode ampuh untuk mengubah arah evolusi kekerasan dan psikosis kebencian. Surat dari Freud ditutup dengan sebuah paragraf menarik:
How long have we to wait before the rest of men turn pacifist? Impossible to say, and yet perhaps our hope that these two factors man’s cultural disposition and a well-founded dread of the form that future wars will take may serve to put an end to war in the near, future, is not chimerical. But by what ways or by-ways this will come about, we cannot guess. Meanwhile we may rest on the assurance that whatever makes for cultural development is working also against war.
Pernyataan ini–atau lebih tepatnya harapan ini–memberi sebuah cermin atas kondisi berulang yang kita hadapi saat ini, ketika Perang (dengan mengacu pada lirik lagu The Rolling Stones), hanya berjarak satu tembakan peluru saja. Dan hingga tulisan ini dibuat, “cultural development“ yang diharapkan oleh Freud , nampaknya masih jauh dari kenyataan.

kontak via editor@antimateri.com