Terdapat seorang penulis, yang bagi saya, karyanya mampu memporak-porandakan imajinasi layaknya badai dalam secangkir teh. Penulis tersebut adalah Marcel Proust, salah satu figur terkemuka dalam sastra Perancis. Namun kesepakatan umum atas tempat terhormat tersebut didapatkan publik dari cukilan kritik sastra atau penggalan review buku sebuah koran, karena di balik nama besar Proust terdapat sebuah fakta menarik: bahwa karyanya tidaklah laku terjual. Posisi tulisan Proust hampir serupa dengan Benedict Anderson bagi orang Indonesia, karya-karyanya secara luas dirayakan, walau jika boleh jujur hanya segelintir orang yang mendalami gagasan pemikirannya secara menyeluruh (harus ditekankan bahwa maksud kalimat ini bukanlah mengerdilkan karya Anderson, tapi merupakan otokritik atas euforia massa yang seringkali mengangungkan sesuatu tanpa tahu makna sebenarnya). Di Indonesia, kondisi ini disebabkan oleh krisis membaca yang akut, sedangkan dalam kasus Proust, keberjarakan publik Perancis dari karyanya disebabkan oleh satu hal sederhana – á tout de souffle – Proust kerap membuat pembacanya (secara harfiah) kehabisan nafas. Salah satu muasalnya adalah halaman À la Recherche du Temps Perdu (In Search of Lost Time) yang jumlahnya melebihi 4000 halaman (3 kali lipat dari karya epik Tolstoy, War and Peace). Selain dari jumlah halaman yang “mengerikan”, karya Proust jauh dari pola novel pada umumnya: À la Recherche du Temps Perdu tidak memiliki plot yang jelas – ini merupakan sebuah pendekatan kronologis yang baru dalam sastra, membuat karya Proust seakan melayang diluar (lintasan) waktu. Bagi publik yang terbiasa dengan karya Victor Hugo atau Emile Zola, À la Recherche du Temps Perdu tidak memberikan narasi yang menggugah – bahkan seri terakhir Le Temps Retrouvé, tidak menampilkan klimaks yang berarti. Namun dibalik kegamangan pembaca, Martin Hägglund (dalam Dying for time : Proust, Woolf, Nabokov) menyatakan bahwa karya Proust memiliki sifat yang personal – À la Recherche du Temps Perdu hanya dapat dipahami melalui pengalaman, dan bagi yang telah bersinggungan dengannya, le Temps Perdu (waktu yang hilang) akan menjelma menjadi sebuah epiphany waktu.
Pada kenyataannya, ketika saya bersinggungan dengan karya Proust, analogi Hägglund tentang efipani waktu lebih terasa seperti hentakan peluru – memaksa kita mengada antara dua kutub ekstrim realita: hidup dan mati. Kutub pertama saya rasakan ketika saya bersama seorang kawan mencoba memahami multi-struktur waktu melalui sebuah project foto. Beragam sudut pandang bermunculan, mulai dari perspektif kosmologi tentang sejarah kelahiran waktu, paganisme yang berpijak pada esensi kesatuan waktu hingga masyarakat modern yang memiliki hobi memecah-mecah waktu (dalam detik, menit, dan jam). Namun ketika menyandingkan bangun waktu dengan estetika, seluruh referensi mengacu pada konsepsi tulisan Proust tentang sensibilitas waktu – yang dikenal dengan konsep a proustian moment. Menurut Proust, seni (art) adalah paragon dalam memaknai kehidupan. Seni dibutuhkan untuk menghilangkan sisi tumpul manusia dan mengembalikan apresiasi atas kehidupan itu sendiri. Lalu apa yang membuat seni bersinggungan dengan waktu?. George Poulet (dalam Hägglund) menyatakan bahwa sebuah pengalaman estetik akan mampu mengungkap “esensi diri seseorang, membebaskannya dari ketergantungan waktu, dan menjadikannya sosok yang abadi”. Kita bisa menyebut El Greco hingga Egon Schiele, Michaelangelo hingga Rodin, Shakespeare hingga Brecht, Johann Sebastian Bach hingga Karl Heinz Stockhausen – adalah segelintir contoh jiwa-jiwa abadi yang mampu melepaskan diri dari waktu. Senada dengan Poulet, Paul Ricoeur menekankan bahwa keterhubungan seni dan waktu terletak dalam pengalaman estetik yang menghantarkan pada “exaltation of the extratemporal” (mendorong pengalaman diluar temporal) dan menempatkan seseorang untuk berdamai dengan keterbatasan waktu. Dalam hal ini, Poulet menyebutkan sebuah formula: “time regained is time transcended” – bahwa seni mampu membuat seseorang tetap abadi dalam esensi waktu yang transenden.
Pemahaman ini begitu membekas dalam ingatan saya dan memberikan sebuah perspektif lain dalam memaknai waktu: bahwa waktu dapat dilihat, layaknya amuba, melalui mikroskop metaforik berupa lukisan, naskah drama, puisi hingga karya fotografi. Lukisan Vermeer yang berjudul The Milkmaid misalnya, adalah sebuah kehidupan yang dipadatkan kedalam kanvas berukuran 45 x 41 cm hampir lima abad yang lalu. Namun melalui sebuah pengalaman estetik, kita masih dapat melihat waktu mengalir bersama air susu yang dituang dan cahaya yang merayap di dinding. Deleuze menyatakan bahwa lukisan seperti karya Vermeer merupakan “realita absolut dari waktu, yang hanya terafirmasi melalui karya seni”. Dalam pandangan Proust, hanya melalui pengalaman intens atas waktulah kita dapat memaknai kehidupan. Bagaimanapun, tidak ada yang istimewa dari aktivitas keseharian dalam karya Vermeer, juga tidak ada pemandangan luar biasa dari ladang gandum yang dilukis oleh Van Gogh – namun, lukisan-lukisan tersebut menjadi sublim karena Vermeer juga Van Gogh, merasakan waktu dengan sangat intens, melalui percikan susu atau hembusan angin di antara bulir gandum. Dalam proses penciptaan karyanya, mereka memaknai dan memberikan apresiasi terhadap kehidupan dalam bentuk yang paling tinggi. Pengalaman waktu yang intens dapat terjadi pula pada penikmat lukisan: yaitu ketika seseorang berhadapan dengan lukisan Van Gogh, melalui pengalaman estetik, ia akan berada dalam epiphany waktu yang sama dengan sang pelukis – sebuah dimensi tanpa batas temporal – un peu de temps à l’état pur.
Namun, ketika waktu disandingkan dengan pemaknaan kehidupan, maka konsekuensinya adalah kehadiran kutub realita kedua: kematian – baik secara fisik maupun metaforik. Proust sendiri digambarkan sangat sensitif akan kematian (dikarenakan masalah kesehatan di akhir masa hidupnya) sehingga À la Recherche du Temps Perdu merupakan caranya dalam menghadapi ketakutan akan waktu terakhirnya. Alhasil, ia menemukan jalan keluar dari waktu juga kematian – sebagaimana diuraikan dalam karyanya: “Marcel knows that his body is going to die, but this does not trouble him, for his spirit has just been resurrected in memory”. Marcel adalah nama tokoh utama dalam À la Recherche du Temps Perdu, menjadikan novel ini tidak sepenuhnya fiksi dan lebih menyerupai sebuah memoir. Marcel (dan juga Proust tentu saja) lalu menemukan immortalitas dalam kebenaran estetik (the Truth of art) dan memori. Memori memiliki fungsi vital dalam karya Proust – Samuel Becket dalam essaynya menyebutkan bahwa memori adalah negasi Proust terhadap kematian (gagasan ini terangkum dalam frase yang dikenal sebagai the Proustian Solution: the negation of Time and Death, the negation of Death because the negation of Time). Sebuah bagian terkenal dalam karyanya berbunyi sebagai berikut:
“More than a year after her funeral, he understands that she is dead. During the past year, he has often spoken and thought of her; he has even supposedly mourned her. But he has not understood that she is dead”.
Melalui gambaran ini, Proust menegaskan bahwa selain pengalaman estetik (yang menjadikan seniman abadi), negasi akan kematian dapat dihadirkan melalui memori. Hal ini berlaku lebih luas daripada the Truth of art karena memori dimiliki oleh semua orang, tidak seperti pengalaman estetika yang hanya menjadi berkah bagi para seniman dan penikmat seni dengan bakat mumpuni. Lebih spesifik lagi, Proust menyatakan bahwa kronologis waktu menjadi tidak relevan karena pada dasarnya manusia hidup dalam memori masa lalu, dan tidak pernah sepenuhnya mengada pada “saat ini”. Dalam À la Recherche du Temps Perdu, memori berloncatan kesana kemari mengacaukan lintasan temporal sehingga beberapa kritik sastra menyatakan bahwa novel ini berada di luar waktu. Bahkan dalam sebuah bagian, Proust seakan menemukan badai waktu dalam secangkir teh dan celupan biskuit madeleine. Melalui gambaran sejernih kristal, tulisan Proust memberikan memberikan gambaran jelas akan persinggungan waktu dengan (apa yang disebut oleh psikolog sebagai) involuntary memories:
“And soon, mechanically, dispirited after a dreary day with the prospect of a depressing morrow, I raised to my lips a spoonful of the tea in which I had soaked a morsel of the cake. No sooner had the warm liquid mixed with the crumbs touched my palate than a shudder ran through me and I stopped, intent upon the extraordinary thing that was happening to me….- this new sensation having had on me the effect which love has of filling me with a precious essence; or rather this essence was not in me it was me”.
Involuntary memories merupakan gerak memori yang hadir seketika seseorang mengalami impuls yang mengingatkannya pada sebuah pecahan waktu. Butuh upaya lebih bagi saya untuk memahami teka-teki tersebut, terlebih Proust menyebut kehadiran involuntary memories menjadi penanda kematian bagi masa lalu – bahwa kronologis waktu (saat ini, masa lalu dan juga masa depan) tidak lagi menjadi penting karena satu dan lainnya berhimpitan kedalam sebutir peluru. Peluru inilah yang kemudian menghentak tajam ketika minggu lalu sebuah kabar duka sampai ke tangan saya melalui sebuah pesan singkat: seorang kawan lama meninggal. Seketika seluruh tulisan Proust tentang memori menjelma dalam bentuk yang nyata – bahwa seseorang menjadi abadi justru setelah ia menjelma dalam bentuk memori. Dan disinilah saya, mencoba berdamai dengan memori dan menulis tentang waktu dalam perspektif baru: bahwa keberadaannya menjadi artifisial dan tidak lagi menjadi penting. Dalam penutup karyanya, Proust menyatakan bahwa penemuan kembali waktu hanya dimungkinkan ketika involuntary memories muncul ke permukaan dan memberi makna atas kehidupan dan juga kematian. Hilangnya pemaknaan, akan mengakibatkan manusia menjelma semacam makhluk chronolibidinal yang senantiasa didorong hasrat penaklukan waktu – tanpa tahu bahwa sang waktu, telah lama usang dan membatu.
Sumber Tambahan:
Hägglund, Martin, 2012. Dying for time: Proust, Woolf, Nabokov, Harvard University Press, Massachusetts
Beckett, Samuel, 1930, Proust, (1989 ed,), Riverrun Press, New York

kontak via editor@antimateri.com

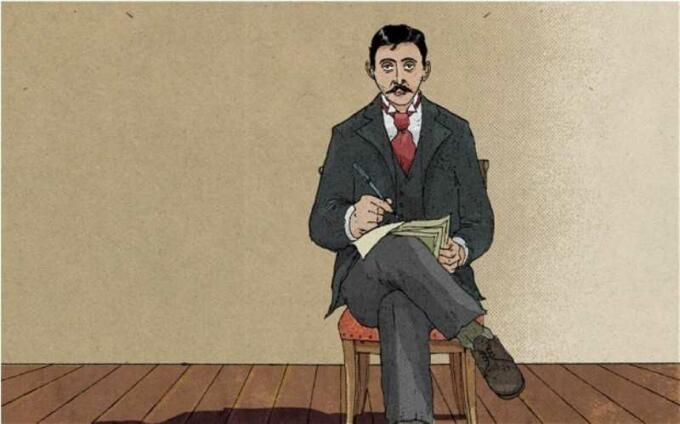



![[ill]usion man ray - rayograph the kiss](https://antimateri.com/wp-content/uploads/2016/10/Man-Ray-Rayograph-the-kiss-145x145.jpg)


Interesting, Teh. Meskipun saya punya konsep sendiri tentang waktu. Saya hanya melihat yang mempresepsi waktu adalah mereka yang hidup, sederhananya karena tidak ada bukti dari mereka yang mati untuk mempresepsi waktu. Tapi kalo gitu, gimana cara seseorang yang hidup mempresepsikan adanya waktu?
spacetime continuum?
ehm well..since we’re not the center of universe, so…yeah, that’s one possible explanation, the other is: time flexes, like a wing (eta mah laguna bowie ketang hahaha)