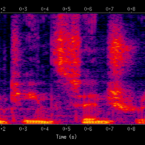Terdapat kecenderungan aneh belakangan ini di masyarakat Indonesia – tapi tidak aneh juga sih sebenarnya, karena sejarah merupakan pengulangan – yaitu ketika pemahaman politik masyarakat bergerak dalam trajektori (mundur) menuju garis batas identitas. Hitler pernah mempertontonkan politik identitas dalam skala kekerasan ekstrem: menarik garis batas tegas antara superioritas ras arya dan ras lain yang lebih rendah – dengan Yahudi sebagai batas margin paling bawah. Setelah kengerian paska perang dunia kedua, manusia mengira mereka akan mampu menata kehidupan berpolitik dengan lebih baik – namun nyatanya, manusia adalah anak sejarah yang begitu malas untuk belajar, sehingga alih-alih mewujudkan politik yang lebih beretika, humanis dan indiskriminatif, saat ini semakin kental dengan warna primordial politik: baik etnik, agama, ras, atau golongan. Saat ini, hampir di seluruh dunia primordialisme menjadi salah satu instrumen jualan para politisi untuk menjegal lawannya (lihat saja bagaimana Donald Trump membangun argumen politiknya, dan bagaimana persoalan identitas digunakan sebagai bahan bakar perang di wilayah Timur Tengah). Gambaran ini adalah sebuah bayang-bayang kekerasan yang lalu mengingatkan kita pada propaganda Hitler beberapa dekade silam.
Lalu bagaimana dengan primordialisme di Indonesia?. Ternyata di tanah airpun tidak ada bedanya. Indonesia sendiri berada pada pijakan yang begitu rapuh: sebuah bangsa multietnis, dimana pluralisme menjadi perekat di satu sisi, namun bila tidak ditangani dengan baik, dapat menjadi mesiu yang dapat dengan mudah meledak sewaktu-waktu. Pemilihan kepala daerah adalah panggung sandiwara primordialisme yang berulang, terlebih apabila salah satu calonnya adalah etnis minoritas – maka isu identitas dianggap sebagai senjata ampuh memenangkan pertarungan. Primordialisme mewujud menjadi sebuah senjata yang diasah oleh ikatan emosional mendalam untuk memperjuangkan sesama kelompoknya – bahkan hingga dalam taraf yang perjuangan yang buta. Sebagai penjelas mengapa primordialisme tidak ubahnya seperti cinta buta seperti pernyataan di atas, Pierre van den Bergh[1] memiliki sebuah pandangan untuk memahami partisipasi politik identitas berdasarkan etnis. Pendapat pertama menyatakan pandangan ekstrem tentang primordialisme, yaitu bahwa kelompok identitas etnis harus berdasarkan pada keturunan biologis. Sedangkan pandangan kedua menyatakan bahwa identitas mengacu pada identifikasi kelompok hasil konstruksi [identitas] yang dibentuk untuk kepentingan tertentu dan dimobilisasi sebagai kelompok penekan. Di Indonesia sendiri, istilah etnik atau kelompok etnis (ethnic group) sebetulnya tidak terlalu tepat jika diterjemahkan sebagai suku atau suku bangsa. Penggunaan istilah etnik sebagai terjemahan langsung dari ethnic dari bahasa Inggris perlu dilakukan secara hati-hati karena faktor sejarah yang berbeda. Istilah suku bangsa yang dipakai di Indonesia memiliki sejarah tersendiri yang menunjukkan bahwa kelompok-kelompok etnis yang ada di Indonesia merupakan bagian dari komunitas yang lebih besar yaitu komunitas bangsa Indonesia. Keadaan ini menunjukkan kuatnya hubungan-hubungan antara bangsa (nation) dan suku bangsa sebagai hasil dari sejarah politik bangsa Indonesia.
Pandangan lain tentang primordialisme di Indonesia dinyatakan oleh Thjin[2] yang menyatakan bahwa etnopolitik di Indonesia menjadi sebuah fenomena mengemuka dan hangat diperbincangkan sejak bergulirnya reformasi tahun 1998. Kungkungan dan diskriminasi politik yang telah berakhir menyusul berakhirnya pemerintahan otoriter Orde Baru menyiratkan harapan akan kebangkitan dan partisipasi berbagai etnis minoritas. Pengertian Etnopolitik sendiri merujuk pada hubungan timbal balik antara komposisi etnodemografis dan proses politik[3]. Secara mendasar etnopolitik dapat dianalisis melalui pembedaan antara partisipasi etnis dan politisasi perbedaan antara kelompok. Dengan menggambarkan kedua poin tersebut maka dapat dilakukan pengukuran celah politik antara kelompok etnis untuk menjelaskan variasi partisipasi dalam pemilihan umum. Sebuah kelompok etnis dikonstruksi ketika individu dalam masyarakat yang jamak secara budaya, secara sadar memilih satu atau lebih penanda objektif etnis untuk membedakan in-group dengan out-group.
Namun, sebagaimana halnya pemahaman atas segala permasalahan, kita harus berupaya meletakkan segala sesuatu pada konteksnya. Primordial, secara konseptual memiliki arti “a basis for community to hold a fixed nature over time”, dalam konteks ini, primordial memiliki fungsi sebagai perekat sebuah komunitas. Namun ketika kata “primordial” telah dihinggapi imbuhan “isme” maka maknanya berubah. Ia tidak lagi bermakna sosial, namun beralih wajah menjadi instrument politik. Secara definitif, primordialisme menekankan pada upaya pencapaian kepentingan kolektif, dan kemampuan identitas kolektif ini untuk mendefinisikan dan mengartikulasi pandangan umum masa lalu dan saat ini, juga membentuk visi untuk masa depan. Pendekatan primordial mengemukakan bahwa kepentingan individual dibuat untuk menunjang kepentingan kelompok dan pimpinannya untuk memperkuat basis etnisitas. Sebagai instrument, etnisitas dianggap sebagai suatu sumber dan kekuatan sosial, budaya dan politik dari berbagai kelompok yang berkepentingan di dalam masyarakat. Salah satu pendekatannya adalah melihat kompetisi dari kelompok-kelompok elit dalam menguasai sumber-sumber dukungan massa sehingga memanipulasi berbagai simbol untuk memperoleh dukungan dari masyarakat. Instrumentalisme lebih menaruh perhatian pada proses manipulasi dan mobilisasi politik ketika kelompok-kelompok sosial tersebut tersusun atas dasar atribut awal etnisitas.
Intrumentalisme menjelaskan bahwa elit politik memanipulasi identitas etnis untuk keuntungan mereka sendiri. Pandangan ini mengasumsikan bahwa masyarakat pada tingkat lokal diarahkan secara politis untuk mendukung pemimpin tertentu dan melakukan tindakan yang menguntungkan kelompok yang berkuasa dan cenderung mengesampingkan dinamika dan kepentingan dalam masyarakat itu sendiri – alhasil apa yang ditawarkan dalam kampanye, seringkali janji klise untuk kemajuan etnis tertentu, yang tentu saja hal ini menjadi kontradiktif dengan bangun masyarakat Indonesia. Namun, mengapa masyarakat pada umumnya membiarkan diri mereka dimanipulasi untuk kepentingan elit politik?. Brown[4] mengemukakan bahwa ketakutan dan intimidasi seringkali terjadi dalam kondisi dimana kekerasan etnis terjadi, tidak dapat digunakan untuk menjelaskan analisis identitas dalam situasi kompetisi tanpa kekerasan, seperti pemilihan umum. Ia pun menjelaskan bahwa masyarakat pada tingkat lokal juga memiliki kepentingan tersendiri dan strategi untuk mempromosikan kerjasama intragroup yang menjadi sarana efektif dalam negosiasi dengan pemerintah atau elit politik tentang akses terhadap sumber daya dan kesempatan politik. Hal ini sejalan dengan pandangan tokoh lain yaitu Horowitz[5] yang memberikan penjelasan tentang ikatan etnis dalam pembentukan kelas atau kelompok identitas. Menurutnya, walaupun etnisitas memang dapat dimanipulasi (instrumentalisme), namun juga secara luas etnisitas diterima secara bawaan (primordial). Dalam berbagai sisi, pendekatan instrumentalis banyak mendapatkan kritik karena dianggap terlalu materialistik, tidak memperhitungkan keterkaitan primordial dari seseorang terhadap etnisnya. Namun, bukti bahwa identitas primordial seringkali digunakan sebagai instrumen politik terlalu “nyata” untuk diabaikan, sehingga seperti kata pepatah “anjing menggonggong, kafilah berlalu”, dan instrumentalisme hingga saat ini merupakan salah satu pendekatan utama dalam menjelaskan etnopolitik.
Pendekatan lain terkait etnopolitik merupakan pengembangan dari instrumentaslisme dan dinamika internal etnis. Dalam negara yang terdiri dari multi identitas dan etnisitas, seperti Indonesia, politik perbedaan tumbuh subur dan memicu munculnya perjuangan kelompok-kelompok terpinggirkan yang mencoba menampilkan diri dan bertahan. Di Indonesia, munculnya politik identitas sebagai akibat runtuhnya masyarakat “terkontrol” ala orde baru memaksa munculnya sandingan dari identitas nasional, yaitu identitas etnis, agama, golongan, ataupun identitas lain yang selama tuga puluh dua tahun terpinggirkan. Dengan kata lain: kebangkitan etnisitas merupakan sebuah kekuatan internal. Pandangan ini menggabungkan kedua teori, yaitu primordialisme dan instrumentalisme untuk menjelaskan bahwa pengidentifikasian etnis (etnisasi) akan berhasil bila melakukan promosi identitas primordial yang mengikat seseorang dengan masa lalunya. Namun kebangkitan ini, pada akhirnya akan menjadi ajang etnisasi politik oleh para pemimpin partai untuk mencapai tujuan politiknya.
Sehubungan dengan etnopolitik dan gonjang-ganjing primordialisme di Indonesia, kebangkitan etnis merupakan kondisi alamiah atas terlahirnya sebuah bentuk politik identitas. Pemahaman politik identitas sendiri mengacu pada seorang filsuf poststrukturalis-postmodernis Perancis, Michel Foucault yang mengkritik konsekuensi-konsekuensi negatif modernisme dan menunjukkan keberpihakanya pada “wacana besar” yang mendominasi dan mengontrol “wacana-wacana yang tertindas”. Dalam sebuah negara yang plural, seperti Indonesia, minoritas akan selalu muncul dan menjadi permasalahan utama dalam konteks nation-building. Minoritas merupakan produk dari situasi, tentang bagaimana masyarakat mempersepsikan keterhubungan mereka dalam berbagai aspek – agama, etnis, ekonomi, dan juga politik. Identitas politik muncul sebagai konsekuensi karena adanya perlakuan tidak adil terhadap etnis minoritas. Ketika sedikit saja demokrasi tercemari primordialisme, maka akan muncul pola-pola intoleransi, kekerasan dan pertentangan etnis. Bagaimanapun, identitas tidak ubahnya trampolin – semakin ia ditekan, maka jauh ia akan memantul. Dan dalam struktur sosial masyarakat yang terbelah, demokrasi adalah pekerjaan rumah yang menantang.
Keterangan Sumber:
[1] Pierre van den Bergh dalam Brass, Paul. 1991. Ethnicity and Nationalism: Theory and Comparison. New Delhi: Sage Publication.
[2] Thjin, Cristine Susana. 2006. Partisipasi Politik Tionghoa dan Demokrasi. Jakarta: CSIS.
[3] Miller, Arthur, Patricia Gurin, Gerald Gurin and Oksana Malanchuk. 1981. Group Consciousness and Political Participation, dalam American Journal of Political Science, Vol. 25, No. 3, Midwest Political Science Association.
[4] Brown, David. 1989. Ethnic Revival: Perspectives on State and Society, dalam Third World Quarterly, Vol. 11, No. 4, Taylor and Francis Ltd.
[5] Horowitz, D. 1985. Ethnics Groups in Conflict. Berkeley-CA: University of California Press.

kontak via editor@antimateri.com