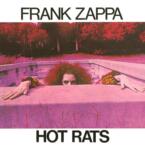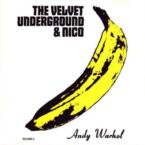Di akhir sebuah penampilan live lagu “Ball and Chain” yang dibawakan oleh Big Brother and the Holding Company, Janis Joplin sang vokalis, dengan setengah meratap, bertanya lirih: “I don’t understand why half the world is still crying, and the other half of the wold is still crying too, but it can’t get it together” – dan pendengarpun bergemuruh, mungkin karena pertanyaan naif seorang Janis adalah pertanyaan mereka juga. Janis pergi begitu cepat, tapi ratapannya tetap menggantung di langit, bersama ribuan tangis yang tersekat – bahkan hampir setengah abad kemudian. Tangisan memang tidak pernah pergi kemana-mana: manusia, dengan berbagai macam caranya mampu memproduksi tangisan dengan jumlah hampir sama banyaknya dengan darah yang tumpah sejak Habil dibunuh Kabil. Tapi tangisan tidak pernah ada dalam ruang kosong – ia memiliki arti yang berbeda, dengan ekspresi yang berbeda pula, dan tidak jarang berkelindan dengan perbedaan ideologi atau sentimen primordial buta. Perbedaan inilah yang pada akhirnya membuat tangis memiliki sekat, serupa tapi tak pernah sama.
Sekat ini membawa implikasi lebih jauh dari sekedar perasaan emosional seseorang – ia menjadi alasan mengapa pendekatan kemanusiaan seringkali gagal dalam menghentikan konflik atau perang: sebuah kenyataan pahit yang harus kita hadapi, bahwa simpati semata tidaklah cukup untuk mempertahankan gencatan senjata. Di depan mata, jelas-jelas kita lihat bagaimana syair, nyanyian, reka visual, bahkan do’a, telah gagal meruntuhkan tembok agresivitas manusia – dan harapan akan simpati yang sifatnya universal, kembali masuk dalam sekat imajiner yang memisahkan persepsi masyarakat.
Sebuah penggambaran tentang betapa batasan imajiner mampu memilah persepsi masyarakat digambarkan oleh Gunawan Muhammad:
“yaitu ketika sebuah tarian berjudul Cabang Musim Gugur dipentaskan di berbagai negara, tanggapan penonton dapat beragam – orang jerman memandangnya sebagai tarian kamp konsentrasi, orang london berpikir tentang kota yang dijatuhi bom, sedang orang jepang berimajinasi tentang kehancuran Hirosima”[1].
Perbedaan persepsi ini disebabkan oleh sejarah dan pengalaman yang berbeda dari setiap penontonnya, dan pada setiap karya seni, interpretasi bisa muncul tanpa batas. Gambaran ini sangat jelas diurai oleh Jacques Ranciere melalui konsep “distribusi rasa” (distribution of sensible). Adapun distribusi rasa sendiri mengacu pada sistem persepsi tentang suatu perasaan umum yang dialami (atau dirasakan) masyarakat kemudian membentuk ruang eksklusif yang dibagi bersama[2]. Ketika sisi emosional seseorang bersentuhan dengan pengalaman bersama, maka ia memposisikan dirinya dalam sebuah ruang yang berbeda dengan (pengalaman) kelompok lain. Pemisahan inilah yang kita kenal dalam bentuk ruang politik, dengan hukum dan aturan main yang berbeda pada setiap kelompoknya – melalui penjelasan tersebut, sangatlah wajar apabila antar kelas masyarakat (yang kaya dan miskin, penguasa dan rakyat, pemegang senjata dan warga sipil) tidak pernah berbagi simpati dan empati, karena satu kelompok dan kelompok lainnya tidak pernah berada dalam sebuah pengalaman yang sama.
Menghadapi kebuntuan dan saling ketidakpahaman ini, Ranciere mengajukan estetika sebagai salah satu remedinya. Menurutnya, estetika mampu membangun jembatan antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lain. Contohnya puisi sebagai sebuah bangun estetika mampu memunculkan metafora yang dapat menghancurkan batasan ruang “rasa” melalui bait-baitnya. Namun tidak semua puisi dapat memenuhi fungsi estetik tersebut, karena puisi yang dapat menghancurkan batasan hanyalah puisi tanpa embel-embel legitimasi dari ruang pengalaman tertentu [3] – ia harus menyentuh ruang universal: tanpa wajah, tanpa bangsa, tanpa ras, tanpa ideologi, tanpa kelas. Dari sudut ini, Ranciere seakan menjelaskan mengapa puisi tentang Gaza tidak akan pernah menyentuh oponennya melalui sebuah argumen sederhana: karena sang oponen berada pada ruang “rasa” yang berbeda. Begitupun dengan berbagai reka visual yang ada, baik foto, film ataupun lukisan – kita harus akui bahwa foto-foto kekejaman konflik di Afrika atau Kurdi, misalnya, kurang dapat menggerakkan simpati masyarakat dunia, termasuk di tanah air, karena wajah-wajah tersebut bukan bagian dari ruang “rasa”mereka (karena sekat semakin kuat jika didalamnya terkandung “rasa” agama, etnis, dan ras).
***
“All you really have that really matters are feeling, that’s are music to me” – Janis Joplin
Pada kesempatan lain, Janis berkata, bahwa satu-satunya hal penting baginya adalah perasaan, yang ia tuangkan dalam musiknya. Dan pada era-nya lah kita melihat bagaimana estetika musik mampu mendobrak sekat rasa di kalangan muda Amerika pada akhir 1960-an, hanya melalui satu bentuk perasaan yang dibagi bersama: Love. Rasa yang disuarakan lantang melalui musik ini berhasil menembus batas kelas maupun ras, sehingga “Love” memiliki arti yang sama baik bagi seorang pacisfist, anti-rasisme, maupun pecinta kebebasan materialism – dan hasilnya adalah subkultur antiperang paling fenomenal yang pernah dicatat sejarah.
Selain fenomena “love generation”, kita menemu dobrakan estetika lain dalam bentuk lukisan – disini kita bertemu dengan Guernica karya Pablo Picasso sebagai salah satu kritik perang paling ampuh.
Guernica, lukisan yang diselesaikan Picasso pada pertengahan Juni 1937, merupakan gambaran tentang Guernica, sebuah desa di wilayah Basque, sehari setelah digempur pesawat bom Jerman pada 26 April 1937. Dengan latar belakang hitam, kelamnya reruntuhan memang nyata terlukisakan, namun eksposisi yang dipilih Picasso tidak terletak wajah kengerian etnis basque secara eksplisit, tapi pada abstraksi kekejaman perang sehingga siapapun akan menemukan diri mereka didalamnya. Disinilah letak kekuatan estetika Guernica, ia menjadi simbol anti-perang yang tidak hanya berbicara untuk satu bangsa atau ras saja, tapi untuk seluruh (sejarah) umat manusia.
Namun, kekuatan estetik yang mampu menembus sekat rasa seperti halnya Guernica, sangat jarang ditemukan. Tidak semua syair, lukisan, atau musik dapat memunculkan dobrakan “rasa” dan simpati universal. Seni (sebagai media estetika), merupakan bentuk representasi dari realita, dan karena realita seringkali diiris-iris oleh pisau persepsi, maka seni pun menjadi rentan menjadi representasi satu pihak dan bukan representasi universal. Bahkan dalam bentuk metafora paling liar pun dobrakan estetika ini sulit untuk dilakukan, dan hanya seorang penyair dengan visi universallah yang mampu melakukan itu. Dari segelintir yang ada, salah satunya adalah penyair besar Rabindranath Tagore – yang melalui syair-syairnya mampu menembus batas “rasa” timur dan barat.
Dobrakan Estetik Janis Joplin
Hampir lima dekade lalu Janis bertanya tentang sekat yang memisahkan tangis manusia, namun setelah sekian lama, sekat itu masih kuat terasa – dan pertanyaannya kembali membentur rasionalitas para pemilik kepentingan yang berdiam dalam “ruang rasa”nya tersendiri. Memang berbagai upaya untuk menembus rasionalitas bebal ini kerap disuarakan dalam berbagai macam cara, namun tanpa meremehkan upaya kritik tersebut, terdapat sebuah kelemahan mendasar dari representasi yang disajikan baik melalui musik, syair ataupun media lainnya: seringkali kata-kata maupun visual yang digunakan tidak menyentuh secara estetis – sehingga ia tidak mampu menembus berbagai pengalaman “rasa” dalam masyarakat. Alhasil, kritik menjadi terkotak-kotakan kembali, kedalam apa yang disebut oleh Ranciere, “distribusi rasa”.
Adapun dobrakan estetik terhadap sekat “rasa” dapat muncul dalam dua bentuk. Pertama, melalui penghilangan batas imajiner kelompok, dalam arti representasi estetik tersebut diterima secara luas oleh berbagai latar belakang pengalaman (mulai dari intelektual hingga tukang becak). Kedua, ia bisa memunculkan “migrasi”, yaitu perpindahan rasa dan pengalaman seseorang sehingga ia dapat merasakan apa yang dialami oleh kelompok lainnya. Dan ketika sebuah puisi atau musik dan karya lainnya berhasil mendobrak batas pengalaman, rasionalitas kekuasaan, emosi primordial, juga kekangan logika kelas, maka dapatlah diserukan ke seluruh pelosok dunia bahwa revolusi estetik telah terjadi!. Dan pada saat itulah semua akan berbagi tangis yang sama, Janis.
Keterangan:
[1] Haryono, Edi, 1999, Tentang Pengarang (Memberi Makna pada Hidup yang fana), Pabelan Jayakarta, Jakarta, hal. 5
[2] Ranciere, Jacques, 2004, The Politics of Aesthetics, (terj: Gabriell Rockhill), Continuum, New York, hal. 12
[3] Robet, Robertus, 2010, Disensus, Politik dan Etika Kesetaraan Jacques Ranciere, Salihara, Jakarta, hal. 9
Sumber Gambar: Janis Joplin

kontak via editor@antimateri.com