Ulasan untuk Perilisan Buku “Setiap Api Butuh Sedikit Bantuan” karya Herry Sutresna
Bandung, 23 November 2025
Musik dan politik, walaupun keduanya memiliki makna berlapis dan membutuhkan sumber entah berapa ribu buku, konteks praktisnya relatif dekat dengan benak pembaca–dalam arti memiliki makna yang diterima secara common sense. Namun tidak demikian dengan lingkaran hermeneutik, walaupun konsep ini telah menjadi gagasan populer, perlu kiranya menjelaskan duduk perkara mengapa ‘konsep njelimet’ ini perlu disampaikan terlebih dahulu sebelum mengulas lebih lanjut buku karya Herry Sutresna a.k.a Morgue Vanguard a.k.a Ucok Homicide kali ini.
Secara sederhana lingkaran hermeneutik adalah sebuah proses pemahaman berulang atas sebuah peristiwa atau gagasan. Sejumlah filsuf, diantaranya Friedrich Schleiermacher, Martin Heidegger, Wilhelm Dilthey, hingga Hans-Georg Gadamer–erat dikaitkan dengan perkembangan konsep tersebut (Gadamer, 1989). Secara singkat Gadamer (1989: 76) mengungkap: ‘In between strangeness and familiarity…is the true place of hermeneutics”. Dengan kata lain, ‘pemaknaan liar’ (strangeness) diperlukan untuk menghantarkan pada pemahaman tentang realita itu sendiri. Pada posisi inilah buku berjudul Setiap Api Butuh Sedikit Bantuan memberikan arti–menghadirkan keliaran pada fenomena yang familiar.
Setidaknya, terdapat tiga fenomena yang dilabrak “pemaknaan liar” Herry Sutresna kali ini, yaitu: aktivisme politik, estetika musik, dan relasi antara keduanya. Yang pertama–perkara aktivisme politik–dibahas Herry secara gamblang, khususnya dalam dua artikel, yaitu Malam Terakhir di RW 11 Tamansari; dan Metis, Rambutan Garongan dan Talking Heads. Yang dimaksud ‘gamblang’ adalah: memang fenomena aktivisme yang dibicarakan disini, melalui dua kasus perebutan ruang–Tamansari dan Kulon Progo.
Berita tentang keduanya hanya dibaca khalayak dengan algortima tertentu saja; karena memang tidak pernah masuk kedalam berita arus utama. Pun, bagi yang bersimpati, tetap ada jarak–entah itu ruang ataupun gagasan–yang menjadikan kedua kasus tersebut (dan kasus perebutan ruang lainnya), hanya hadir selewat saja. Sialnya, melalui dua artikel di atas, Herry memberikan pemaknaan liar yang mengajak untuk berpikir ulang. Strangeness, laiknya ungkapan Gadamer, hadir dari pengalaman mikroskopik Herry yang meresapi peristiwa-peristiwa tersebut dalam jarak yang begitu dekat–seakan memberikan dosis kesadaran melebihi takaran. Alhasil, kita limbung di buatnya: ada yang hilang dan tak terkatakan ketika apa yang seharusnya dilakukan, telah tenggelam dalam mimpi buruk masa silam.
Fenomena kedua, yang berada pada ‘teritori’ Herry, adalah perkara musik. Di sini ia membahas ragam genre, mulai dari punk, hardcore, jazz, folk, hingga–yang satu ini menjadi penekanan–hip hop dan segala yang ada disekitarnya. Musik, dalam konteks buku ini, memiliki khasanah personal–dalam arti, musik yang hidup dalam pengalaman sang penulis. Namun, justru karena personal, maka artikel-artikel tentang musik dalam buku ini, memberi kesan tersendiri. Misalnya: terdapat berbagai kisah tentang persinggungan pertama Herry dengan beberapa karya (diantaranya Jerusalem In My Heart, album pamungkas Johhny Cash, hingga memori masa kanak-kanak tentang David Bowie); atau tentang eksistensi dan resistensinya bersama Grimlock Record; hingga cerita patah hati tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh musisi idolanya, Chuck D., yang menyerah pada sistem yang semula ia lawan.
Lalu, dimana kita menemu lingkaran hermeneutik dari pembacaan artikel-artikel musik karya Herry Sutresna? Jawabannya–sama halnya dengan konteks sang penulis–adalah personal; tidak ada jawaban yang sama atas pengalaman satu dengan lain. Pada posisi ini, estetika memberikan makna, bahwa seni (baik musik, ataupun dalam bentuk tulisan), bertujuan untuk menggugah pemaknaan–apapun itu. Bagi sebagian, mungkin berupa penambahan katalog musik atau lagu; bagi sebagian lain, berupa kesadaran politik; atau mungkin juga berupa anggukan halus atas komentar sang penulis yang mewakili keresahan bersama.
Tulisan tentang musik mendominasi buku yang tebalnya melebihi 300 halaman ini, sehingga tidak salah jika buku ini masuk ke dalam kategori kritik musik. Namun, beberapa tulisan melebihi fungsi kritik dan menjelma menjadi komentar sosial. Pada poin ini, pemaknaan ketiga hadir, yaitu tentang relasi musik dan aktivisme politik. Tulisan tentang INPRES, misalnya, atau tentang refleksi berjudul “Dekaden Satu Dekade”, merupakan contoh nyata bahwa musik adalah tanda sekalgus penanda sebuah jaman. Relasi ini lalu merangsek, bukan hanya dalam politik praktis, tapi juga dalam kesadaran kolektif massa, sebagaimana disampaikan Herry (2025: 56):
“Mungkin kita tak pernah benar-benar mengukur waktu dengan kalender. Kita mengukurnya dengan album yang kita dengarkan, jalan yang kita blockade, dan wajah-wajah yang masih kita rindukan”.
Pengalaman memberi pijakan pada proses pemaknaan ulang lingkaran hermeneutik. Waktu yang bergerak maju, senantiasa mangajak kita memaknai realita dengan sudut pandang baru. Namun apa jadinya jika realita yang ada malah ‘jalan di tempat’ atau bahkan ‘mundur ke belakang’? Herry, dalam bukunya memberikan jawaban: dengan refleksi setengah emosi, juga rangkaian sumpah serapah, ia menghadirkan pemaknaan liar untuk sekedar menjaga api tetap menyala. Melalui bukunya ia mengajak untuk bersama menjaga pijaran api, dengan sedikit bantuan, dan jika memungkinkan, lewat kegaduhan.
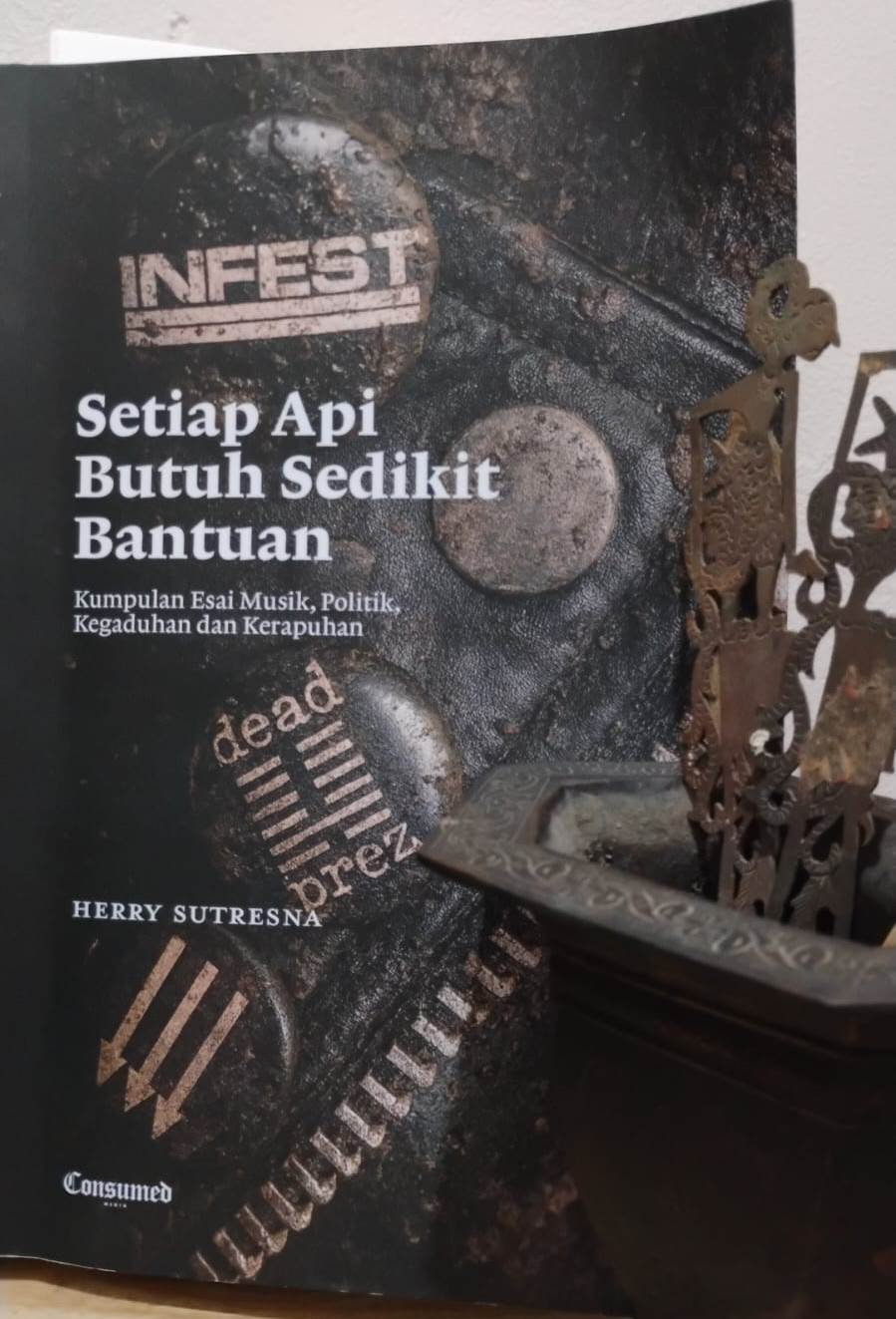
Sumber Gambar Muka:
Fire Painting, Yves Klein, 1961 (wikiart)
Sumber Bacaan:
Gadamer, H.-G. (1989). On the Circle of Understanding. Dalam J. Weinsheimer & D. G. Marshall (Terj.), Truth and Method (hal: 268–274). Continuum.
Sutresna, H. (2025). Setiap Api Butuh Sedikit Bantuan: Kumpulan Esai Musik, Politik, Kegaduhan, dan Kerapuhan. Consumed Magazine.

kontak via editor@antimateri.com




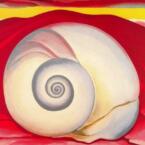
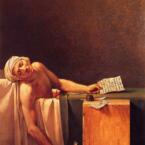

*Sedikit koreksi;
-di antaranya, di sini, di sekitarnya, di mana.
-dibuatnya.
Waah keren tata bahasanya,
Gapapa lah ya, males koreksi, yg penting makna tersampaikan
Sori nilai bahasa indo saya butut :p