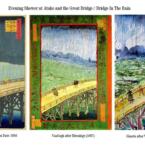Pada Kisaran 1968, lima fotografer asal Jepang– Koji Taki, Takuma Nakahira, Yutaka Takanashi, Daido Moriyama, dan Takahiko Okada–menggagas sebuah pendekatan radikal dalam produksi foto yang kemudian dipublikasikan dalam majalah bertajuk Provoke. Dengan menggunakan slogan “Are, Bure, Boke” (kasar, kabur, dan tidak fokus), foto-foto dalam majalah Provoke berhasil memperkenalkan sebuah bahasa visual baru dan mempengaruhi gaya fotografi, bahkan jauh setelah era Provoke berakhir. Pemilihan kata Provoke sendiri memiliki tujuan yang jelas, yaitu membedakan diri dari fotografi tradisional, juga menanggapi perubahan sosial dan politik yang berkecamuk di Jepang, juga di seantero dunia yang saat itu tengah dilanda perang tak berkesudahan.
Lalu, apa yang menjadikannya relevan untuk diangkat saat ini? Jawabannya: kepingin saja–juga karena dua alasan yang dibuat-buat: pertama, walaupun gerakan Provoke niscaya telah diulas berulang, di Indonesia tulisan tentang gerakan ini masih minim; kedua, untuk menjawab rasa penasaran tentang keterkaitan antara gerakan seni radikal ini dengan protes massa dan pandangan sosial dan politik Jepang kala itu. Adapun teknik fotografi yang digunakan oleh para maestro Provoke tidak menjadi menu dalam tulisan ini, bukan karena tidak menarik, tapi karena alasan praktis: penulis tidak tahu apa-apa tentang teknik fotografi :p.
Majalah Provoke sendiri hanya bertahan tiga terbitan, antara 1968 hingga 1970, namun berhasil meninggalkan jejak mendalam (dikenal sebutan the Provoke Era). Bahkan, dalam lingkup gerakan seni, Provoke kerap disandingkan dengan Dadaisme yang mengemuka di Eropa awal abad 20 (antara 1911 hingga 1920an). Tidak ada tujuan lain dari para pemberontak visual ini kecuali untuk menggugat pakem fotografi tradisional. Shakes (2015) memberikan keterangan bahwa Provoke, secara tidak langsung, meletakkan manifestonya pada upaya kolektif untuk menghindari subjektivitas berlebihan dari seorang fotografer. Saat itu, gagasan Provoke dapat dikatakan radikal karena menentang kebiasaan umum yang mendasarkan kekuatan sebuah foto pada naratif (padahal fotonya biasa saja, atau bisa jadi sangat buruk). Hal ini senada pandangan Nishii (dalam Chong, 2012) yang menyebut bahwa Provoke adalah satu-satunya gerakan visual di Jepang yang mempertanyakan sudut pandang fotografi, dengan mengkonfrontir peran seorang fotografer. Sebagaimana diungkap Takanashi (dalam Aarons, 1999): “[Many photos] was too explanatory, too narrational for me; I was trying to make my own work […] I was always irritated by photography being a tautology. I think [Taki and Nakahira’s] style of blurred, grainy photographs came about because of a similar frustration.”
Upaya menentang sifat naratif dalam fotografi membawa para seniman Provoke pada dekonstruksi gaya, yaitu melalui penggunaan kekasaran (graininess) ekstrem dan kontras yang tinggi. Namun, selain daripada itu, idiosinkratik-lah yang berbicara. Tidak ada satu tema yang mengikat dalam setiap terbitannya–setiap fotografer berbicara dengan gaya dan bahasa [visualnya] sendiri. Baker (dalam Tsuyoshi, 2017) menggambarkan bahwa terdapat banyak pendekatan yang digunakan dalam Provoke–bahkan satu fotografer dapat menggunakan pendekatan yang berbeda (sebagai contoh, dalam Provoke 1, Nakahira Takuma memotret kehidupan malam di Shinjuku, Taki Kōji mendokumentasikan kerusuhan pada sebuah tambang batu bara di Hokkaido, sedangkan Takanashi Yutaka berkutat dengan tema seputar fashion). Sehingga, dapat dikatakan bahwa kebebasan atas gaya, eksperimen, dan jenis fotografis, adalah karakteristik yang menyatukan Provoke. Karakteristik lain, tentu saja, menentang naratif penjelas foto. Alih-alih menggambarkan subjek mereka dengan jelas, para fotografer Provoke sering memilih fragmen kehidupan yang sarat emosi (gambaran kegembiraan dan kesedihan) layaknya sebuah foto yang sarat dengan kecamuk eksistensialisme khas paska perang yang tengah berkembang pada periode yang sama.
Eksistensialisme dan penggalian emosi dari subjek foto inilah yang kemudian menghantarkan Provoke pada posisinya yang dikenal saat ini: sebagai medium protes sosial politik. Uniknya, Baker (dalam Tsuyoshi, 2017) menggambarkan bahwa keterlibatan Provoke dalam protes politik bukanlah sesuatu yang disengaja–tapi lebih karena daya tarik protes para mahasiswa (Zengakuren) yang mencerminkan emosi satu generasi yang meluap di berbagai sudut jalanan Jepang saat itu. Sas (2020) berpandangan bahwa melalui fotografi, Provoke membuat protes mahasiswa laiknya atraksi seni pertunjukan (performance art), bahkan disebut pula sebagai ‘the post-war Japanese fine arts’. Kekuatan emosi yang ditampilkan Provoke dinyatakan sebagai salah satu pendorong semakin meningkatnya aktivisme mahasiswa Jepang, bersandingan dengan permasalahan sosial politik dan berkembangnya gagasan-gagasan new left di Jepang.
Kini, Provoke memiliki tempat tersendiri dalam perkembangan seni dengan meletakkan diri sebagai oposisi dari subjektivitas fotografer (yang mereka anggap terlalu banyak bicara, ketimbang memotret). Majalah tersebut berhasil mempengaruhi budaya visual Jepang pasca-perang dengan gaya eksperimental khas yang hanya dapat lahir ketika seseorang “membuka tirai tebal yang menyelubungi dunia” (Taki dalam Provoke 1). Walaupun demikian, Nakahira menyesalkan bahwa gaya ‘are, boke, bure’, secara bertahap kehilangan kekuatan aslinya karena perkembangan eksperimen para anggota Provoke yang menghantarkan pada ketidakberlanjutan publikasi majalah tersebut. Terlepas dari perbedaan visi dan gaya yang kemudian dikembangkan oleh para fotografernya, terdapat satu publikasi lagi yang mereka lakukan bersama setelah bubar, dengan nama Provoke 4. Adapun rangkuman dari keseluruhan karya mereka dikumpulkan dalam buku berjudul Mazu tashikarashisa no sekai o sutero (First Abandon the World of Certainty).
Selain meletakkan pengaruh pada pembaruan perspektif, Provoke juga dikenal sebagai majalah yang mengawal dan menawarkan bentuk protes yang subversif. Namun, walaupun para pendiri Provoke menyatakan diri tidak terhubung dengan pesan politik tertentu, ketajaman emosi yang disajikan berhasil mengangkat kembali format estetika revolusioner untuk menantang norma dan tradisi yang mengekang kebebasan berpikir. Dengan kata lain, memprovokasi diskusi demokratis melalui fotografi. Keterangan tentang keterkaitan fotografi dalam protes politik hanya dijelaskan secara minim oleh Moriyama. Ungkapnya (dalam Moriyama dan Nakahira, 1972): “This era is marbled with innumerable political veins…when taking photographs, it is not that I turn my camera towards culture itself, and hence by pressing the shutter obtain it. To the contrary, no matter what I photograph, it is already political in itself. Bahwa tidak perlu membuat narasi tentang politik, karena politik telah menyatu dalam urat nadi budaya sehingga dapat ditemukan dimana-mana.
Rasanya, penjelasan singkat sang maestro telah lebih dari cukup untuk membangun jembatan antara estetika dengan gerakan aktivisme massa–baik saat dulu, ataupun sekarang.





Sumber Foto: japan-photo.info, aperture, wikimedia commons
Sumber Bacaan:
Aarons, P Provoke. Numbers: Serial Publications by Artists since 1955. Zurich, Switzerland: PPP Editions in Association with Andrew Roth.
Chong, D. 2012. Redefining the Relationship between Humans and the World. From Postwar to Postmodern: Art in Japan 1945-1989: Primary Documents. New York: Museum of Modern Art: 213.
Moriyama, D & Nakahira, T. 1972. Moriyama Daido and Nakahira Takuma–Dialogue at Yamanoue Hotel in Farewell Photography [Shashin yo sayōnara]. Tokyo: Shashin Hyoronsha, hal, 291.
Sas, M. 2020. Provoke: Between Protest and Performance—Photography in Japan 1960/ 1975 ed. by Diane Dufour and Matthew S. Witkovsky (review). The Journal of Japanese Studies, 46 (1): 234-239
Shakes, S-A. 2015. Provoke: A Visual Language of Protest. New York: Fordham University Lincoln Center
Tsuyoshi, I. 2017. The Provoke Moment. Aperture

kontak via editor@antimateri.com