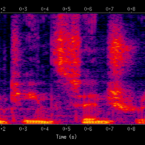Terdapat dua cara yang sering digunakan para penulis untuk menggambarkan kematian: brutal penuh agoni atau ringan membebaskan. Cara pertama kita temukan pada setiap babak dalam drama Macbeth karya Shakespeare. Rangkaian tragedi ini diawali oleh teriak mengerikan yang membelah langit malam ketika Duncan, Raja Skotlandia, mati dihujam belati. Jerit kesakitan sang Rajalah yang kemudian menghantui Macbeth dan menyeretnya ke lorong kegilaan serta kematiannya sendiri. Dalam drama ini, kematian adalah ujung dari sebuah ramalan akan malapetaka yang datang secara perlahan dan menyakitkan. Tragedi lain dikisahkan oleh Lu Hsun, sang sastrawan kawakan Tiongkok, yang memilih cara kedua untuk menceritakan kisah kematian tragis seorang begundal kelas teri bernama Ah Q. Tokoh Ah Q ini sama sekali bukan sosok yang mengagumkan, tapi Lu Hsun bersikukuh bahwa penulisan kisah hidup (biografi) merupakan hak semua orang, termasuk Ah Q yang nyaris tidak memiliki kontribusi apapun bagi masyarakat. Ah Q merupakan pembual yang senantiasa dirundung kesialan, bahkan ia kena kutuk tidak memiliki keturunan karena mencuri lobak di sebuah biara – dengan kata lain, hidupnya adalah tragedi. Klimaks dari cerita hidup ini adalah bagaimana Lu Hsun menggambarkan kematian Ah Q dengan begitu ringan membebaskan – “semua yang ada di depannya menjadi hitam, terdengar dengungan samar di telinga dan seolah-olah tubuhnya berhamburan menjadi debu”. Dalam karya sastra, kematian adalah bagian yang terlalu penting untuk diabaikan – sebisa mungkin dihadirkan untuk menggugah emosional pembaca. Namun sayangnya kehidupan nyata bukanlah karya fiksi, dan kematian dalam berita pagi adalah uraian angka yang dingin dan impersonal.
Saya tidak menonton televisi, tapi di jaman riuh informasi ini – entah bagaimana caranya – berita selalu sampai ke tangan saya dibarengi bombardir tindak kekerasan. “Aksi teror” adalah tajuk yang muncul hampir setiap pagi dengan berbagai varian cara: pemboman, penembakan, penusukan hingga penabrakan kerumunan orang dengan truk berkecepatan tinggi. Setelah memaparkan cara, motif pelaku adalah paparan selanjutnya, dan berita diakhiri dengan cakupan jumlah korban. Pola pemberitaan ini tidak berubah walau berita tentang teror begitu marak dalam dua tahun ke belakang: diawali dengan penyerangan kota Paris, pemboman di Belgia, rentetan teror di Turki, hingga penembakan di Jerman. Namun jika boleh jujur, respon kita sajalah yang berlebihan, karena kekerasan bukan sesuatu yang baru. Pemboman perkampungan di Irak, kekerasan sektarian di Yaman, perang sipil di Suriah, hingga konflik sumber daya alam di Afrika – mengalami peningkatan bahkan sebelum Eropa diguncang aksi teror. Disini terlihat jelas bagaimana sejarah panjang kolonialisme telah berhasil meredam kekerasan di beberapa bagian dunia dengan membuatnya senyap, sehingga teror baru menghentak ketika terjadi di Champ Elysees atau di jantung kota Munich. Dan kita, sambil menahan nafas, terlambat menyadari bahwa realita telah berubah menjadi plot dalam novel-novel dystopia.
Hannah Arendt mengalami keterkejutan serupa hampir satu abad yang lalu. Dalam On Violence (1969), ia memaparkan keterhenyakan dirinya (dan dunia pada umumnya) terhadap eksalasi kekerasan yang terpampang nyata pada awal abad 20. Perang dunia I adalah awalnya, diikuti dengan perang dunia II dan penemuan bom atom, membuat dunia dipaksa menyaksikan kekerasan brutal yang terjadi di depan mata. Beruntung Arendt memiliki pandangan berjarak dari narasi kekerasan Eropa, sehingga walaupun terhenyak pada kekerasan perang dunia, ia tetap menyadari bahwa kekerasan bukanlah hal baru bagi Eropa – karena kekerasan adalah instrumen utama dalam kerangka imperialisme. Hal ini sejalan dengan pendapat Sartre dalam pengantar buku Fanon, The Wretched of the Earth, yang menyatakan bahwa “irrepressible violence…is man recreating himself” – sebuah argumen pemakluman akan fungsi kekerasan yang selalu hadir dalam proses pembentukan diri manusia. Fanon yang berbicara tentang dekolonialisasi, menyatakan bahwa kekerasan diperlukan dalam kelahiran sebuah bangsa, namun Sartre menariknya lebih jauh ke sisi esksistensial – dimana kekerasan bukan semata-mata tindak interpersonal, tapi juga terjadi dalam kelahiran konsepsi diri. Selanjutnya kekerasan menurut Arendt digambarkan sebagai anatomi yang tidak terpisahkan dari kekuasaan – sehingga ketika manusia bersinggungan dengan kekuasaan (baik negara, institusi agama, klasifikasi kelas, hingga persinggungan identitas), kekerasan akan selalu ada disana. Menurutnya, hanya kekuasaan absolut dengan kepatuhan mutlak yang tidak membutuhkan kekerasan dalam bentuk nyata (walaupun kekerasan dalam bentuk laten akan tetap ada dan menjadi bayang-bayang bahkan bagi seorang raja paling adil sekalipun).
Satu abad kemudian, kita melihat kekerasan dalam bentuk lain – bukan perang memang, tapi teror yang terserak hampir di seluruh pelosok dunia. Namun, kekerasan tetaplah kekerasan, dan yang terjadi saat ini merupakan anagram dari bentuk kekerasan abad lampau. Kekerasan menurut Arendt memiliki sisi kembar kekuasaan – walaupun dalam penjelasannya, legitimasi negara tidak hanya dikonfrontir oleh civil disobedience atau oposisi ideologi, tapi oleh entitas yang lahir dari rahim globalisasi, yaitu transnational organized crimes. Uraian menarik dikemukakan oleh Louise Shelley dalam Dirty Entanglements: Corruption, Crime, and Terrorism (2014) yang mengemukakan bahwa kemajuan teknologi informasi dan transportasi telah mengubah peta kekuasaan dalam interaksi ekonomi – awalnya jaringan seperti yakuza, triad, dan mafia membutuhkan negara untuk beroperasi (sebagai contoh: perang adalah salah satu cara paling mudah untuk membuka akses lalu lintas narkotika, juga transaksi lain seperti pencucian uang yang hanya dapat dilakukan dengan berpijak pada interaksi ekonomi antar negara). Namun ketika monopoli teknologi tidak lagi dikuasasi negara (kita bisa lihat bagaimana jihadist dengan leluasa memposting video via Youtube di pedalaman afghanistan), maka kapasitas negara menjadi nihil dan kekuasaannya tidak lagi absolut. Kondisi ini memicu sebuah konsekuensi logis, yaitu: negara tidak lagi dibutuhkan, sehingga dalam beberapa kasus, transnational organized crimes berevolusi menjadi jaringan terorisme global yang mengibarkan bendera perang melawan negara – dengan menggunakan strategi teror acak yang menyasar warga sebagai instrumen pencapaian tujuannya. Dalam On Violence, Arendt mengungkap “Terror is not the same as violence as legitimate means…having destroyed all power, it does not abdicate, but on the contrary, remains in full control”. Melalui penjelasan Arendt, kita meyadari dampak utama dari aksi teror yang terpampang saat ini – yaitu kita tersesat dalam rangkaian kekerasan, tanpa tahu apa tujuannya – pada akhirnya, violence is for violence’s sake.
Hal lain yang begitu mengganggu dari gelombang aksi teror dan kekerasan saat ini adalah motifnya yang bersinggungan dengan sensitifitas primordial – ras, etnis, juga agama. Segregasi ras di Amerika Serikat yang telah dihapuskan setengah abad lalu tidak menghentikan gelombang arus bawah rasisme yang masih kuat melanda di negara tersebut. Islamophobia menumbuhkan alienasi bagi sebagian pelaku teror – walaupun dalam beberapa kasus pelaku tidak terafiliasi dengan jaringan teroris global, namun mereka menjadi cermin buram dalam persinggungan dua identitas kebudayaan. Johan Galtung dalam Cultural Violence (1990) mengemukakan bahwa persinggungan identitas yang berbeda riskan berujung pada kekerasan karena satu dan yang lain mengalami kemandegan dalam komunikasi. Individu menjadi teralienasi dari lingkungan sekitarnya dan kita menyaksikan bahwa alienasi sosial kerap menjadi pemicu dalam beberapa kasus penembakan, termasuk yang terjadi di Munich beberapa waktu lalu. Titik ekstrem yang ditarik oleh Galtung dalam memahami kekerasan atas dasar alienasi identitas adalah terjadinya spiritual death, dimana seseorang bukan hanya teralieansi secara sosial tapi juga teralienasi dari narasi identitasnya – fakta dari analisis ini ada dimana-mana, salah satunya adalah ketika agama dijadikan pembenaran atas tindak kekerasan. Melihat kondisi sosial saat ini, saya merasakan pesimisme akut menggantung di udara – bagaimana tidak, dengan mengacu pada pola interaksi sosial saat ini (baik melalui mobilitas penduduk atau interaksi dunia maya), alienasi adalah sisi muram globalisasi yang menempati ruang-ruang tertutup dalam gegap gempita interaksi sosial. Setiap orang seakan riuh berkata-kata, namun tidak berkomunikasi – realita ini menghadirkan sebuah kematian dalam bentuk lain: yaitu ketika seseorang tidak dapat lagi dimengerti. Kematian bentuk inilah yang menurut Galtung menjadi pemicu rangkaian kekerasan yang dilakukan oleh identitas-identitas terbelah.
Melalui gambaran diatas, dystopia saat ini bukanlah sesuatu yang mengada-ada. Kekerasan yang terpampang hampir setiap hari di halaman-halaman koran secara perlahan meresap ke alam bawah sadar dan berubah menjadi sesuatu yang banal. Dunia tidak lagi terkejut atas aksi teror (mungkin sedikit terkejut ketika teror terjadi dalam radius yang terjangkau, namun ketika ia berada di belahan bumi lain, teror telah kehilangan daya gebraknya). Kekerasan dan kematian tidak lagi dibicarakan dalam pemaknaan dan simbol (seperti dalam lukisan mencekam Goya), tapi dipaparkan tanpa tedeng aling-aling layaknya lukisan hiperrealitas dengan detil grosteque dan warna tajam menusuk mata. Alhasil, kekerasan dan kematian tidak lagi signifikan – seperti percakapan Juan dan Tom dalam The Wall karya Sartre, yang entah mengapa salah satu dialognya memiliki kemiripan sangat dekat dengan kejadian teror di Perancis pada perayaan St. Bastille day di pertengahan Juli lalu. Ketika ia tidak lagi asing, maka kematian dibicarakan layaknya gosip di siang hari, tanpa beban dan emosi – Tom berkata pada Juan, “Saya dengar di Saragosa mereka dieksekusi dengan cara digilas truk, katanya untuk menghemat peluru”, lalu Juan menjawab “ya, memang menghemat peluru, tapi tidak menghemat bensin”.
Referensi:
Arendt, Hannah, 1969, On Violence, Harcourt Brace Jovanovich Publishers, New York
Galtung, Johan, 1990, “Cultural Violence” dalam Journal of Peace Research, Vol. 27, No. 3. (Aug., 1990), hal. 291-305
Sartre, Jean Paul, 1961, Intoduction to The Wretched of the Earth (Frantz Fanon), Grove Press
Sartre, Jean Paul, 1969, The Wall: (Intimacy) and Other Stories, New Direction
Shelley, Louise, 2014, Dirty Entanglements: Corruption, Crime, and Terrorism, Cambridge University Press

kontak via editor@antimateri.com