Hampir sebulan belakangan tiba-tiba saya memiliki ketertarikan dengan segala hal tentang Jepang. Sebetulnya sastra Jepang bukanlah hal baru karena sejumlah karya dari para penulis kawakannya seperti Yukio Mishima, Yasunari Kawabata hingga Jun’ichirō Tanizaki, berada pada jajaran penulis favorit saya. Namun nampaknya ketertarikan kali ini sudah mencapai fase gawat hingga seorang kawan yang kebetulan pengkaji dan penikmat budaya Jepang saya buat kesal atas bombardir pertanyaan tiada henti (sekaligus khawatir karena dia mengira saya kesambet setan serdadu Jepang sisa perang dunia dulu). Mungkin kawan saya ada benarnya, karena sepertinya saya memang kesambet, tapi bukan oleh hantu serdadu Jepang, melainkan oleh kumpulan tulisan Yoshida Kenko berjudul Tsurezuregusa yang diterjemahkan sebagai Essays in Idleness, sebuah karya klasik sastra Jepang. Setelah membaca esay-esay karya Kenko inilah, fase “Nippon Binge” saya bermula.
Saat ini Tsurezuregusa dikenal sebagai salah satu karya klasik abad pertengahan yang mempengaruhi baik gaya penulisan ataupun gagasan estetika kesusastraan Jepang. Ditulis dalam jangka waktu dua tahun antara 1330 hingga 1332, Tsurezuregusa memiliki arti secara harfiah Tsurezure (leisure) dan Gusa (memiliki arti kata “mentah” sering digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang belum selesai). Yoshida Kenko sendiri adalah figur yang istimewa: seorang penjaga istana (merangkap penyair) yang mengabdikan masa tuanya sebagai seorang Biksu. Lance Morrow (Smithsonian Magazine, 2011) membandingkan Kenko dengan Dante dalam kualitas kedalaman pemikiran. Bedanya: jika Dante memandang akhir dunia dalam kemurungan (yang diikuti dengan pengukuran sistematis tentang surga dan neraka), maka Kenko malah menikmati kehancuran dan ketidakabadian (saya membayangkan Kenko sumringah ketika mengucapkan “The most precious thing in life is its uncertainty”). Sosok Kenko lalu menjadi legenda dalam sastra klasik Jepang sebagai seseorang yang berhasil merangkum estetika Jepang dimana keindahan hadir dalam ketidaksempurnaan (dikenal dengan konsep Wabi-sabi) – sebuah bangun estetika yang bagi budaya lain terasa janggal dan sulit dipahami.
Adapun karya monumental Tsurezuregusa ditulis sang biksu eksentrik pada lembaran-lembaran kertas yang lantas ia tempel memenuhi dinding kamar. Paska kematiannya, Imagawa Ryoshun, seorang kawan baik Kenko-lah yang mengumpulkan dan memberi penomoran sebagaimana cetakan yang dipublikasikan saat ini. Kenko tidak pernah bermaksud untuk menyebarluaskan Tsurezuregusa sehingga gagasannya bukanlah sebuah pendalaman yang memiliki awal dan akhir, sebab-akibat, ataupun “metode validitas” sebagaimana dikembangkan para filsuf di seberang lautan (gagasan filosofis Barat kental dengan gerak pikir ini, juga filosofi China yang terkenal sangat logis dan sistematis). Namun, walaupun tidak memenuhi kriteria “metodologis”, 243 essay dalam Tsurezuregusa adalah fragmen filosofis Jepang dengan rentang yang luas: mulai dari musik, puisi, kehidupan politik istana, relasi sosial, waktu dan semesta, peringatan atas “kebahagiaan yang berlebihan”, hingga kematian. Kelihaian Kenko membuat essay yang sarat dengan sindiran sarkas ini mampu bersandingan dengan gagasan spiritualnya – alhasil pengaruh Budhisme sangat terasa pada kumpulan tulisan ini. Selain menekankan pada spiritualitas Budhisme, Tsurezuregusa juga menempatkan nilai emosional sebagai sesuatu yang begitu berharga – sisi ini membuat Tsurezuregusa memiliki keriangan khas, yang terasa bahkan ketika Kenko tengah membicarakan kematian. Paine (dalam The Art and Architecture of Japan, 1955) mengemukakan bahwa pengaruh Budhisme dan penekanan emosional inilah yang menjadi pembeda utama antara karakter filsafat Jepang dan China. Jika pemikiran filsafat China tumbuh di tangan para sarjana dan akademisi, maka filsafat Jepang berkembang di lingkungan spiritualist Budha – hal ini menjadikan karakter Jepang lebih terasa bebas dan alamiah.
Berikut kita simak bagaimana Kenko mengurai gagasan tentang “kebahagiaan yang berlebihan” melaui sebuah esay bebasnya:
This is a story of the priests of the Ninnaji. They had a feast to celebrate the farewell to the world of a young acolyte about to enter the priesthood. In their revels they became drunken, and the acolyte, beginning to feel merry, took a three-legged iron pot that lay nearby and put it on his head. Then, though it fitted very tight, he flattened out his nose, pulled the pot over his face, and began to dance. The whole company grew merry beyond measure, until after performing awhile, he at length tried to pull it off—but in vain!
This sobered the feast, and they were thrown into confusion and doubt, wondering what they should do. While they were debating, the pot cut into his head, and blood began to flow and his face swelled up so that he could hardly breathe. They tried to break it, but it was not easily broken, and as the force of the blow went to his head, he could not bear it, and they were obliged to stop. They did not know what to do next, so, throwing a black gauze cloak over the three legs, which looked like horns, they led him, supported by a staff, to the house of a physician in Kyoto. People looked at them with amazement as they went along.
It must have been a queer scene when they brought him face to face with the physician on entering his house. When he spoke, his voice was muffled, and resounded so that they could not hear what he said. The physician said that he had never seen such a case in the books, nor had he ever had any oral instruction on the point, so they were obliged to return to the temple. There his friends and relatives, with his old mother, gathered at his bedside and wept and grieved—not that they thought he could hear! At last someone said, “Suppose he does lose his ears and nose, so far as living goes there is no reason why he should not survive. Let us then pull the thing off by main force.” So they thrust rice straw all round between his head and the metal, and pulled as if to drag off his head. His ears and nose were torn away, and he escaped with his bare life, suffering afterward many a long day.
Gambaran diatas hanya satu contoh dari berbagai essay Kenko. Keseluruhan karyanya tidak memiliki ikatan yang eksplisit (namun justru melalui tema sembarang, semakin terlihatlah pola universal yang berulang). Pola penulisan acak ini pada akhirnya menjadi genre tersendiri yang dikenal dengan sebutan Zuihitsu, sebuah pola penulisan gagasan (biasanya prosa atau esay) yang alurnya ditentukan oleh “flow of conciousness” (alur kesadaran). Dengan kata lain, esay dan prosa dalam genre ini tidak memiliki alur baku – biasanya mengacu pada respon penulis tentang lingkungan sekitar atau fenomena tertentu. Selain Tsurezuregusa karya Kenko, terdapat dua karya lain yang dianggap sebagai pionir Zuihitsu, yaitu Makura no Sōshi (The Pillow Book) karya Sei Shōnagon dan Hōjōki karya Kamo no Chōmei (yang juga seorang Budhist seperti Kenko). Selain memberi pengaruh dalam penulisan melalui Zuihitsu, Kenko juga memberikan pandangan yang tajam tentang puisi. Ia menuliskannya dalam essay berikut:
Kalimat Kenko tentang puisilah yang kemudian membuka mata saya tentang karakter spesifik estetika Jepang: yaitu memberikan nilai pada sesuatu yang biasa. Paine menggambarkan bahwa letak kekuatan kebudayaan Jepang adalah kapasitasnya untuk menghargai segala sesuatu – termasuk retakan di vas bunga (dalam konteks Wabi-sabi: keretakan memiliki nilai dan bukan sebuah cacat), atau rerumputan liar di sebuah taman bunga, yang merupakan esensi kehidupan itu sendiri. Sekilas, terlintas adegan dalam film garapan Yasujirō Ozu ketika kamera menyorot diam sebuah teko yang dibiarkan mendidih dan mengepulkan asap. Atau alegori Mishima tentang gunting, buku, dan alat tulis lain yang saling berdampingan tanpa tujuan di atas meja tulis Yuichi (tokoh dalam Forbidden Colors). Dalam dua alusi tadi, Ozu dan Mishima, memiliki napas yang sama dengan keindahan sublim Tsurezuregusa karya Kenko.
Didorong rasa penasaran akan rasa estetika Jepang inilah, maka saya tidak ubahnya orang kesetanan yang menggali berbagai macam hal tentang Jepang: mulai dari arsitektur, musik, seni teater, hingga budaya pop (manga dan anime) yang menjadi wajah utama Jepang saat ini. Tujuannya memang bukan membandingkan – karena bagaimanapun, sublimitas Tsurezuregusa tentu tidak akan terulang – namun untuk mencari kembali gerak estetika yang diwariskan Kenko dalam seni modern saat ini. Tentu pertanyaan ini mustahil untuk dijawab melalui kajian singkat satu bulan dengan referensi minim (beberapa ebook bajakan dan kuliahan online), tapi setidaknya terdapat sebuah kalimat menarik yang dikemukakan Lance Morrow (seorang pengkaji Jepang dari Museum Smithsonian), yang memberi jawaban sementara atas rasa penasaran saya. Morrow telah mengunjungi Jepang berulang kali dan menemukan bahwa sublimitas telah banyak terkikis dalam keseharian masyarakat Jepang. Kesibukan semu dan riuh informasi menjadi sebab utama semakin terpinggirnya kesederhanaan dalam hati negeri itu (Morrow, 2011). Penjelasan Morrow memperkuat pandangan bahwa kebanyakan dari kita (seluruh warga dunia, termasuk Jepang), telah kehilangan naluri untuk bertahan dalam lautan realita. Seorang pelaut akan memandangi objek yang jauh untuk menghilangkan mabuk laut – dan mungkin seperti itulah fungsi Tsurezuregusa – sebagai penangkal bagi gegap gempita hiperrealitas.
Sumber Bacaan:
Paine, Robert T. dan Alexander Soper, The Art and Architecture of Japan, 1955, Penguin Book, London
Kenko, Yoshida, Essays in Idleness, terj. George Sansom, 1955, Grove Press, New York
Morrow, Lance, Timeless Wisdom of Kenko, 2011.

kontak via editor@antimateri.com



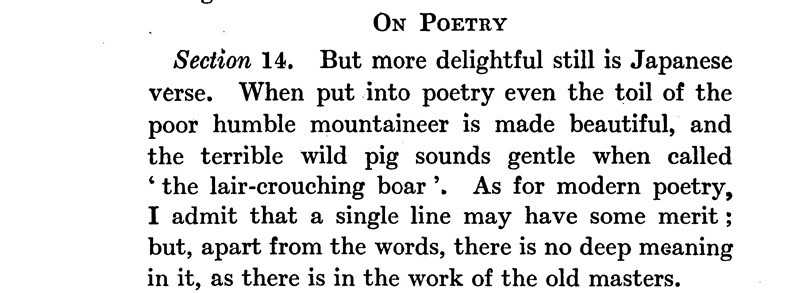




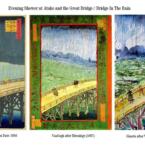

Ali Senpai memang menyebalkan, khazanah wawasan estetikamu itu loh, bikin banyak orang ngiri. Tapi, saya tertarik juga tentang bagaiamana orang Jepang menghargai yang biasa. Yang biasa pun bisa menjadi begitu estetik. Mungkin itu sebabnya, bisnis anime di Jepang segmen genrenya sudah kelewat banyak sekali. Dari anime yang bercerita tentang petugas kereta api sampai anime tentang kegemaran memancing. Sungguh, yang biasa bisa menjadi unik. Ah, kapan Endonesa begini ya bu Ali Senpai?