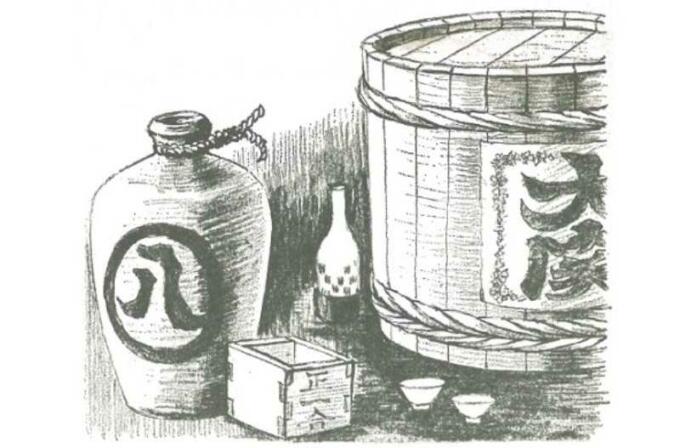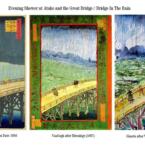Entah berapa botol sake dan berapa gelas brandi yang telah dihabiskan Guru Nankai ketika menjamu dua tamunya. Sang Guru yang terkenal dengan sebutan “Guru Laut Selatan” itu memang terkenal pemabuk ulung – dan siapapun tahu, dalam mabuknya Guru Nankai kerap meracaukan berbagai pandangan tentang ilmu filsafat, ilmu sejarah, ilmu bumi hingga politik. Biasanya setelah botol ketiga “kuliahnya” dimulai, pada saat seperti ini Guru Nankai sendiri merasa “bahwa Akulah kompas bagi seluruh masyarakat dunia. Sayang betul bahwa politikus-politikus dunia yang picik pandangannya memegang kemudi dan menyebabkan kapal menghantam karang atau kandas di lautan dangkal, dengan demikian membawa bencana bagi diri sendiri dan orang lain”[1]. Guru Nankai merasa bahwa mabuk selalu memberikan pencerahan dan membuat otaknya begitu encer, namun sang Guru berhadapan dengan sebuah kenyataan pahit: bahwa ketika tersadar ia selalu lupa apa yang ia katakan selama mabuk – alhasil tidak ada satu teoripun yang berhasil dibukukan. Pada suatu sore, untuk alasan yang hampir sama dengan semua orang, dua orang datang ke rumah Guru Nankai dengan membawa brandi merk terkenal dari eropa. Guru Nankai tidak mengenal mereka, tapi ia menyebut yang pertama sebagai Priyayi (karena kesan intelek dari penampilannya) dan yang kedua ia sebut Pahlawan (karena menurut Guru Nankai, ia terkesan berasal dari golongan manusia unggul). Setelah gelas brandi dituang, maka dimulailah perbincangan antara ketiganya – perbicangan yang kemudian dikenal dengan judul A Discourse by Three Drunkards on Government (Ansuijin Keirin Mondo, 1887), sebuah karya legendaris sastra Jepang.
Kisah tentang Guru Nankai dan dua tamunya merupakan karya seorang jurnalis dan pengembang terjemahan bahasa asing di Jepang, Nakae Chomin. Bagi pengkaji politik Jepang, Chomin dikenal dengan sebutan “Rousseau dari Timur”[2] atas sepak terjangnya dalam dunia politik. Chomin sendiri memiliki arti “rakyat banyak” (sedangkan nama asli sang jurnalis adalah Nakae Tokusuke, anak dari seorang samurai rendahan yang mengabdi pada klan Yamauchi di Tosa). Modernisasi yang diusung pemerintahan Meiji memberi kesempatan pada Chomin untuk mengkaji bahasa dan gagasan dari para pemikir Perancis di negara asalnya. Sekembalinya ke Jepang pada tahun 1874, Chomin membuka akademi bahasa Perancis yang berkutat pada pendidikan dan terjemahan (diantara hasil terjemahannya adalah L’Esthetique karya Vernon dan Histoire de la Philosophie karya Fouille). Nampaknya pengaruh dari alur pikir liberal membuat Chomin tidak betah hanya sekedar menterjemahkan – ia lalu terjun ke dunia politik dengan menerbitkan surat kabar Oriental Free Press (Tōyō Jiyū Shinbun) yang mengusung gagasan-gagasan demokrasi. Atas propaganda yang disuarakannya, Oriental Free Press ditutup pada tahun 1887 dan Chomin diasingkan dari Tokyo. Pada tahun 1889, pengasingan Chomin berakhir dan ia berupaya mengubah pemerintahan dari dalam (dengan memenangkan pemilihan sebagai wakil Distrik Keempat Osaka)[3]. Namun, berada dalam pemerintahan ternyata malah membuatnya tambah uring-uringan – ia lalu mengundurkan diri di bulan keempat dan bertekad untuk “menjadi penganjur hak-hak rakyat”[4] dengan kembali menyebarkan propaganda demokrasi.
Tapi Chomin (sebagaimana Guru Nankai dalam fiksinya), bukanlah seorang politisi pada umumnya. Ia seorang alkoholik kelas berat dan ketika surat kabarnya terancam bangkrut akibat kebiasaan minumnya, Chomin membuka rumah pelacuran sebagai sumber biaya. Sisi eksentrik ini mengingatkan kita pada Rousseau yang juga seorang pemberontak tatanan sosial, sehingga bukan sebuah kebetulan jika A Discourse by Three Drunkards on Government pun ditulis dalam semangat pembebasan atas kungkungan sosial. Dalam waktu singkat, karya Chomin langsung mendapat perhatian sebagai parodi penuh humor yang mengkritik politisi di era Meiji. Sang Priyayi mencerminkan para politisi yang keranjingan teori barat, menelannya bulat-bulat serta mengutip filsuf kesukaan mereka di setiap kesempatan. Sedangkan sang Pahlawan adalah seorang konservatif penuh nostalgia pada pemerintahan tanpa basa-basi ala kediktatoran militer Shogun. Adapun karakter Guru Nankai mencerminkan gagasan Chomin sendiri – yang walaupun secara teguh mengamini pemikiran Rousseau, namun tidak menihilkan kuatnya nilai-nilai aristrokat pada masayarakat Jepang[5]. Melalui humor mabuk Guru Nankai, Chomin menyindir kelemahan berpikir kaum intelektual dan aristrokat, juga memprovokasi masyarakat untuk menentang pengekangan hak-hak rakyat. Chomin nampaknya paham betul fungsi humor dalam mempereteli superioritas – racauan mabuk Guru Nankai sama tajamnya dengan Majnun si Gila dalam literatur Arab[6] atau Si Bodoh (The Fool) dalam King Lear karya Shakespeare. Humor juga menjadi senjata bagi Chomin untuk mendorong kesetaraan antar individu, seperti perkataan mabuk sang Priyayi tentang kebangsawanan, bahwasannya “begitu menggelikan ketika seonggok daging diberi gelar Yang Mulia”[7]. Melalui diskursus para pemabuk, Chomin berhasil mengangkat pandangan Delueze tentang gagasan alamiah (natural reason), yang menurutnya: The idiot has always been a function of philosophy. The philosopher is the one who does not have of all knowledge, and which has but one faculty, natural reason. The idiot is the man of natural reason.
Ketika Chomin menulis diskursus pemabuknya pada tahun 1887, Jepang tengah mengalami perubahan dalam berbagai sudut kehidupannya – mulai dari sistem pemerintahan, munculnya pemahaman tentang individualitas, pengurangan anggaran militer, keterbukaan pendidikan, hingga gaya hidup (salah satunya melalui trend berpakaian ala eropa). Namun bersandingan dengan perubahan ini konservatisme peninggalan pemerintahan Bakufu masih mengakar dengan kuat. Pertentangan dua kutub ini menyebabkan kegelisahan sosial berkepanjangan dan kebingungan di masayarakat. Titik balik masyarakat Jepang inilah yang dipotret oleh Chomin dalam A Discourse by Three Drunkards on Government. Dengan gaya yang mengalir, Chomin berhasil mengurai argumen dasar dari kedua pihak: sang Priyayi bersikukuh dengan evolusi masyarakat demokrasi yang harus dicapai dalam waktu singkat, sedangkan sang Pahlawan memegang teguh pemerintahan terpusat karena menurutnya mampu memberikan keselamatan, khususnya dari ancaman luar. Selama perdebatan antara keduanya berlangsung, Guru Nankai duduk santai sambil sesekali memberikan komentar (dan tak lupa mengisi ulang gelasnya). Ia sepertinya menahan diri (walau sebenarnya terlihat jelas bahwa Guru Nankai lebih terhibur karena brandi daripada ocehan politik kedua tamunya), dan baru ikut ambil bagian setelah gelas terakhir brandi kandas ia minum. Pandangan Guru Nankai ternyata tidak sesuai dengan keinginan kedua tamunya, ia berujar: sebuah negara merupakan campuran dari berbagai keinginan, terdiri dari penguasa, pejabat pemerintah dan rakyat biasa. Karena itu, negara tidak dapat menentukkan arahnya hanya dari kemauan pribadi. Jawaban ini sontak diprotes oleh keduanya, namun Guru Nankai yang semakin mabuk tidak mempedulikan protes mereka dan menekankan, bahwa walaupun ia setuju dengan demokrasi, namun demokrasi tidak dapat tumbuh dalam waktu semalam. Sang Priyayi menganggap gagasan Guru Nankai abstrak dan tidak sistematis, sedangkan sang Pahlawan berujar bahwa pemikiran Guru Nankai kacangan seperti pola pikir anak-anak. Kokok ayam lalu terdengar, kedua tamu memohon diri dan tidak pernah kembali lagi.
Dibalik kritik dan gagasan yang terangkum dalam A Discourse by Three Drunkards on Government, terdapat sebuah hubungan menarik antara Chomin (sang penulis), dengan Guru Nankai (tokoh dalam karya fiksinya). Karakter keduanya terasa tidak berjarak – seakan Chomin dengan sengaja menjadikan Guru Nankai sebagai juru bicara. Perihal menahan diripun mereka senada: Guru Nankai menahan diri selama perdebatan, sedangkan Chomin menahan diri untuk tidak gegabah dalam menyampaikan gagasan demokrasinya selama masyarakat Jepang belum sepenuhnya siap menerima ide kebebasan ini. Melalui penokohan Guru Nankai, Chomin menggambarkan tentang gagasan terpenting dan tidak bisa digaggu gugat yaitu kesetaraan dan pemenuhan hak rakyat, sedangkan bentuk pemerintahan sendiri, menurutnya harus didasarkan atas keinginan bersama. Pandangannya inilah yang kemudian dianggap sebagai jalan tengah dalam struktur modern pemerintahan Jepang – bahwa bentuk kekaisaran masih tetap dapat dipertahankan selama memenuhi hak seluruh rakyatnya. Atas pengaruhnya, A Discourse by Three Drunkards on Government diberi tempat kehormatan oleh UNESCO sebagai salah satu karya yang merepresentasikan politik Jepang. Sedangkan pengaruhnya bagi bangun kesusasteraan adalah pengakuan terhadap Chomin sebagai salah satu sastrawan terbaik – sebuah penghargaan tinggi mengingat Chomin adalah seorang jurnalis yang berasal dari luar lingkungan sastra. Jelas bahwa melalui pengaruhnya yang luas, buku ini merupakan karya penting bagi perkembangan struktur pemerintahan juga pemahaman demokrasi di Jepang – bahkan beberapa pengamat politik menyatakan bahwa tanpa adanya buku ini, bisa jadi bentuk kekaisaran Jepang berakhir di masa Meiji. Namun, Chomin (seperti halnya Guru Nankai) rasa-rasanya tidak mau ambil pusing. Saya membayangkan, ketika tahu bahwa karyanya mendapat perhatian istimewa (dengan sederet penghargaan), Chomin malah akan ngeloyor pergi mencari botol sake atau mengundang beberapa kawannya untuk membawa brandi atau cognac, dan ia pun melanjutkan mabuknya.
Sumber dan Keterangan:
[1] Chomin, Nakae, 1989, Perbincangan Tiga Pemabuk tentang Pemerintahan (Terjemahan dari A Discourse by Three Drunkards on Government, 1984), Jakarta: Gramedia, hal. 3-5
[2] Nakae Chomin dijuluki Rousseau dari Timur atas kiprahnya dalam memperkenalkan pemikiran-pemikiran filsuf liberal Perancis, terutama Jean Jaques Rousseau, pada publik Jepang di era pemerintahan Meiji
[3] Kuwabara Takeo, 1983, Japan and Western Civilization, Tokyo: University of Tokyo Press, hal, 144
[4] ibid., 255
[5] Pemikiran ini dirangkum dalam dialog A Discourse by Three Drunkards on Government (Chomin, 1989, op.cit, hal. 96): “Guru Nankai berkata, Saya hanya akan mendirikan konstitusionalisme, mempertinggi kehormatan dan kemuliaan kaisar di atas dan menambah kebahagiaan dan perdamaian di rakyat bawah”.
[6] Miquel, André, 1984, Majnûn et Laylâ : l’amour fou, Paris: Sindbad, hal. 11
[7] Chomin, op.cit. hal. 13

kontak via editor@antimateri.com