Joseph Garcin terlihat kebingungan ketika ia diantar oleh semacam petugas valet memasuki sebuah ruangan kosong. Dalam perjalanan Garcin telah mempersiapkan diri untuk yang terburuk: alat penyiksaan, tungku panas hingga jerit kesakitan – karena itulah gambaran kebanyakan orang tentang neraka. Namun kini dihadapannya hanya ada sebuah ruang kosong, tiga buah kursi, dan sebuah ornamen tembaga di pojokan, sehingga serta merta ia bertanya: “dimana alat-alat penyiksanaannya?”, atas kebingungan Garcin sang petugas valet menjawab ringan “ah, semua cerita tentang penyiksaan itu cuma lelucon saja kok”. Dialog tersebut merupakan adegan pembuka dalam drama berjudul Huis Clos (diterjemahkan sebagai No Exit) karya eksistensialis Sartre.
Drama yang ditulis Jean Paul Sartre pada tahun 1944 ini memiliki karakter yang unik: hanya terdiri dari satu babak, satu setting dan tiga pemain dengan bobot peran yang sama (ditambah satu peran minor petugas valet). Huis Clos sebagaimana digambarkan dari awal adalah drama yang berlatarkan neraka – dan dimanapun, neraka adalah tempat penyiksaan. Namun di tangan Sartre, neraka paling menyiksa tidaklah hadir dalam bentuk lecutan cambuk atau deraan luka fisik, tapi melalui kehadiran orang lain. Drama ini dipentaskan pertama kali di Teater du Vieux-Colombier, Paris, pada Mei 1944 dan semakin mendapatkan perhatian luas ketika ditayangkan di Broadway, Manhattan, dua tahun kemudian. Namun mengapa drama yang digubah Sartre tujuh dekade lalu, memiliki irisan makna yang sama dengan kondisi saat ini?. Karena rasa-rasanya, frase “Neraka adalah Orang Lain”, dapat kita temukan dengan mudah dalam realita pada layar televisi hingga halaman media sosial.
Irisan makna antara dunia imajiner Sartre dengan dunia hiperelitas media sosial terletak pada bentuk relasi destrukstif yang hadir didalamnya. Dalam Huis Clos, ruang tertutup memaksa ketiga tokoh (Garcin, Inez dan Estelle) untuk berelasi satu sama lain. Dan ternyata, relasi buruk antar manusia (mulai dari saling menghakimi, lontaran pelecehan verbal hingga pembunuhan karakter), berdampak lebih traumatis daripada penyiksaan fisik. Situasi inilah yang digambarkan Sartre dalam Huis Clos: sebuah “neraka modern” yang higienis, tanpa noda darah ataupun tumpahan minyak panas, juga tanpa algojo – hanya sebuah ruangan kosong dimana ketiga tokoh yang terjebak didalamnya saling menghancurkan persepsi diri satu sama lain, berulang kali, dalam keabadian. Huis Clos, walaupun berlatar neraka, tidak dibangun dalam narasi agama. Perdebatan tentang “apakah surga dan neraka memang ada?” tidak diangkat dalam drama ini. Dengan kata lain, neraka dalam Huis Clos berpijak pada pandangan ateistik dimana Garcin, Inez dan Estelle, harus menerima konsekuensi atas tindakan yang pernah mereka lakukan – atau dalam kalimat Inez: “kita tidak dikutuk tanpa alasan”.
Seiring berjalannya plot, satu persatu kesalahan para tokoh terpapar ke permukaan. Garcin adalah seorang disertir sok pahlawan, tukang selingkuh dan penipu. Inez adalah seorang lesbian yang mencuri istri orang, namun menghimpit pacarnya tersebut dengan rasa bersalah yang berujung pada tindakan bunuh diri. Sedangkan Estelle berselingkuh lalu menenggelamkan anak hasil perselingkuhannya. Hampir setengah dari dialog Huis Clos berbentuk pertanyaan tajam yang diutarakan satu tokoh kepada tokoh lainnya. Disini kita dapat melihat bagaimana Sartre begitu lihai dalam membangun interogasi yang berfungsi layaknya ujung sebuah gunting: menelanjangi masa lalu hingga mereka tak punya apa-apa lagi untuk menutupi rasa bersalah yang dipertontonkan secara paksa. Rasa bersalah memang tidak secara eksplisit diungkap dalam dialog antar tokoh, tapi justru karena perasaan bersalah yang ditekan, setiap tokoh mencoba untuk saling menghakimi dan memojokkan. Adegan ini – dimana setiap individu memaksakan kehendak untuk bertindak sebagai hakim atas yang lain – bukanlah sesuatu yang asing saat ini. Berbagai plot dibuat untuk membuktikan diri adalah yang paling benar – seakan kebenaran adalah sebuah tropi yang diperebutkan. Mungkin kita yang begitu bersemangat untuk membuktikan diri (benar), tidak lain adalah cerminan Garcin, Inez dan Estelle yang muak akan diri sendiri. Beberapa individu berupaya untuk menjaga kewarasan dengan berteriak: Berhentilah, kita akan menyakiti satu sama lain! (seperti yang dilakukan Estelle di pertangahan babak), tapi neraka bukanlah tempat dimana keluhan diterima dengan baik – dan penyiksaanpun berlanjut tanpa kompromi dan tanpa akhir.
Irisan lain antara Huis Clos dengan realita di depan mata terletak pada pandangan Sartre tentang subjektivitas. Melalui atmosfir yang dibangun di atas panggung, kita dapat merasakan bahwa posisi ketiga tokoh sebagai subjek individu yang mampu memaknai diri, perlahan hancur berkeping-keping. Dalam relasi brutal antara ketiganya, arti seorang individu ditentukan oleh pandangan orang lain, yang digambarkan sebagai berikut: Garcin merupakan seorang disertir yang berupaya meyakinkan Inez dan Estelle bahwa dirinya bukanlah pengecut, Inez adalah seorang dominatrix yang ingin mengalahkan Garcin dan mendapatkan perhatian Estelle, sedangkan Estelle selalu haus kasih sayang dengan segala cara mencoba mendapatkan perhatian dari Garcin – namun relasi ini tidak berjalan sebagaimana yang mereka inginkan dan berujung pada negasi atas persepsi diri setiap tokoh didalamnya. Kondisi inilah yang bersentuhan dengan pemaknaan Sartre tentang pandangan Subjektivitas. Saling negasi merupakan klimaks dalam Huis Clos, dimana penyiksaan terjadi melalui pandangan (negasi) orang lain. Pada akhirnya Garcinlah yang pertama menyadari bahwa neraka adalah–orang lain.
Subjektivitas dalam Huis Clos secara tajam menggambarkan permasalahan utama pada pembentukkan persepsi diri saat ini. Ketidakmampuan seseorang untuk melepaskan diri dari penilaian orang lain telah menjadi penyakit akut yang belum diketemukan obatnya. Dalam wabah ini, individu sebagai subjek murni (yang mampu memaknai diri sendiri) tidak lagi ditemukan – karena selamanya kita adalah objek dari pandangan orang lain. Hiruk pikuk dunia maya melipatgandakan peng-objek-an ini dengan sama sekali tidak memberikan seseorang waktu memaknai dirinya sendiri. Konsekuensinya adalah: kita tidak lagi memiliki kebebasan – karena kebebasan kita untuk mempersepsikan diri ditolak oleh pandangan orang lain. Dalam Huis Clos, kematian adalah batas kebebasan yang tidak bisa diganggu gugat (Garcin, Inez dan Estelle tidak memiliki pilihan lain kecuali bertahan dalam siksaan relasi destruktif yang mereka hadapi). Namun dalam konteks realita saat ini, batas kebebasan lebih berupa dinding ketidaktahuan yang menjadi kuburan massal manusia-manusia malang yang terjebak dalam neraka dunia maya. Sartre menutup Huis Clos dengan kalimat setengah pasrah dari Garcin: “Mari kita lanjutkan saja”. Ini adalah sesuatu yang tidak biasa kita temukan dalam karya Sartre – yaitu kesan ketidakberdayaan. Namun pada akhirnya kita harus mengakui, bahkan existensialist sekelas Sartre harus menerima adanya batasan dalam kebebasan. Tapi ketika dibandingkan, entah batasan mana yang lebih membuat merinding: apakah batasan ruang dan waktu yang didefinikan melalui kematian, atau batasan pengetahuan yang didefinisikan melalui kedunguan?. Yang pasti, Sartre telah membuat dipredisksi setelahnya: bahwa “neraka” adalah konsekuensi dari kebebasan yang tidak bertanggung jawab.
Sumber Bacaan:
Sartre, Jean Paul (Translation: Stuart Gilbert), 1989, No Exit and Three Other Plays, Vintage (Reissue edition)
McBride, William I. (ed.), 1997, Existensialist Literature and Aesthetics, Garland Publishing, New York

kontak via editor@antimateri.com

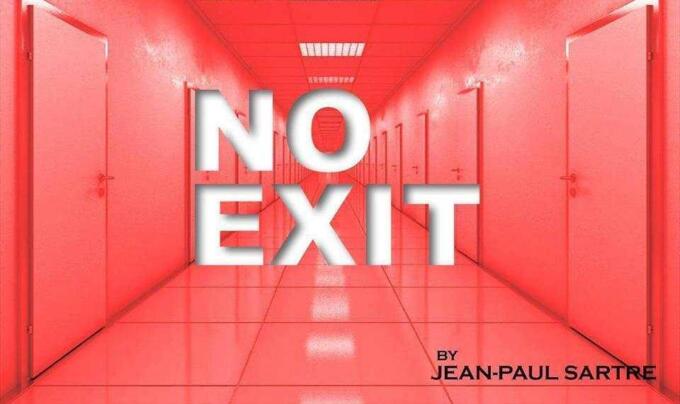





![[ill]usion man ray - rayograph the kiss](https://antimateri.com/wp-content/uploads/2016/10/Man-Ray-Rayograph-the-kiss-145x145.jpg)